KUPI BEUNGOH
Menggali Solusi: Menata Tambang Emas Rakyat di Aceh tanpa Represi
Tambang ilegal bukan hanya merusak lingkungan dan hutan Aceh, tetapi juga melahirkan persoalan hukum dan sosial
Oleh Edy Mirza,ST*)
Tambang emas ilegal di Provinsi Aceh masih menjadi persoalan besar.
Data terbaru menunjukkan bahwa hingga akhir 2024 terdapat sekitar 8.107 hektare wilayah pertambangan emas ilegal tersebar di berbagai kabupaten, mulai dari Aceh Barat, Nagan Raya, Pidie, Aceh Jaya, hingga Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Aceh Besar (Mongabay, 2024).
Luas ini meningkat dari 6.805 hektare pada tahun sebelumnya, menandakan bahwa penertiban represif yang selama ini dilakukan belum menyentuh akar masalah. Tentunya, angka tersebut terus bertambah hingga kini.
Tambang ilegal bukan hanya merusak lingkungan dan hutan Aceh, tetapi juga melahirkan persoalan hukum dan sosial.
Baca juga: Mualem Ultimatum Tambang Ilegal, Minta Tarik Semua Alat Berat dalam Hutan dalam 2 Minggu
Menurut Pansus minerba dan migas DPR Aceh, aktivitas tambang ilegal di provinsi ini berlangsung masif: sekitar 450 titik operasi dengan 1.000 unit alat berat aktif bekerja.
Ironisnya, DPR juga mencatat dugaan praktik setoran hingga Rp 360 miliar tiap tahun kepada oknum aparat agar aktivitas tersebut tetap berjalan.
Tradisi menambang emas di Aceh bukan hal baru. Catatan kolonial menunjukkan bahwa sejak abad ke-17, kawasan Woyla dekat Meulaboh sudah dikenal sebagai pusat perdagangan emas yang diawasi VOC (van Leeuwen, 2014).
Hingga kini, tradisi itu masih berlangsung dalam bentuk artisanal and small-scale gold mining (ASGM) yang menjadi tumpuan ekonomi ribuan keluarga di pedalaman Aceh (Meutia et al., 2022).
Sayangnya, negara lebih sering hadir dalam bentuk penertiban represif.
Aparat melakukan razia, namun masyarakat menilai tindakan ini justru memperburuk keadaan.
Hal ini bukan hanya karena tambang sudah menjadi mata pencaharian turun-temurun, tetapi juga karena ada dugaan keterlibatan aktor besar dalam melanggengkan praktik tambang ilegal.
Investigasi menunjukkan adanya relasi antara penambang, pemodal, dan oknum aparat. Studi tentang tambang emas ilegal di Indonesia mencatat bahwa penambang sering kali dipaksa “membayar perlindungan” kepada aparat, politisi, atau militer agar aktivitasnya dibiarkan berjalan (Hasibuan & Tjakraatmadja, 2022).
Bahkan, laporan di Aceh menyebutkan adanya praktik setoran uang di kantor polisi sebagai bentuk “jaminan keamanan” bagi aktivitas tambang (McCulloch, 2005).
Baca juga: TA Khalid Ajak Semua Pihak Kawal Ultimatum Mualem Soal Praktik Haram Tambang Ilegal
Persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari fenomena yang dikenal sebagai resource curse atau kutukan sumber daya.
Dalam pengantar buku Escaping the Resource Curse, George Soros menjelaskan bahwa paradoks negara kaya sumber daya yang justru miskin dipicu oleh tiga faktor utama: apresiasi mata uang, fluktuasi harga komoditas, serta pengaruh asimetris politik.
Dari ketiga faktor ini, Soros menekankan bahwa asimetris politik adalah penyebab utama yang membuat sumber daya menjadi malapetaka alih-alih berkah, karena kekuasaan terkonsentrasi di tangan elite atau aparat yang mengabaikan kepentingan rakyat (Soros, 2007).
Situasi tambang emas ilegal Aceh yang memperlihatkan keterlibatan “cukong” dan oknum aparat dalam jaringan tambang ilegal merupakan gambaran nyata bagaimana asimetris politik bekerja.
Baca juga: Butuh Ratusan Miliar Pulihkan Eks Tambang Ilegal
Pendekatan represif yang dijalankan pemerintah selama ini terbukti tidak efektif.
Pertama, penertiban cenderung mengorbankan penambang kecil yang bergantung pada tambang untuk hidup, sementara aktor besar kerap lolos dari jeratan hukum.
Kedua, praktik setoran kepada oknum aparat membuat tambang ilegal tetap eksis, meski operasi resmi dilakukan berkali-kali (Meutia et al., 2023).
Ketiga, karena beroperasi secara sembunyi-sembunyi, para penambang semakin sulit dikontrol dan sering menggunakan teknologi berbahaya seperti merkuri yang merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Tidak bisa di pungkiri dalam pelaksanaannya, proses penambangan memerlukan pembukaan lahan.
Namun aktivitas penambangan yang dilakukan secara ilegal akan memberikan dampak yang tidak terukur dan tidak bisa terpantau oleh pemerintahan.
Dalam kasus ini, Aceh dapat belajar dari pengalaman negara lain dalam menangani tambang rakyat.
Baca juga: Ketua PAS Aceh Tu Bulqaini Siap Bantu Mualem Basmi Tambang Ilegal
Pemerintah Aceh harus menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di lokasi-lokasi yang sudah lama ditambang oleh masyarakat.
IUPR bisa diberikan kepada kelompok masyarakat dengan syarat penggunaan teknologi non-merkuri.
Ini akan memberi legalitas kepada penambang kecil sekaligus membuka jalur pajak dan pengawasan resmi (UU Minerba 3/2020).
Dengan jalur legal, pemerintah bisa mengawasi penggunaan teknologi, memungut pajak, sekaligus melindungi hak penambang (Lumowa et al., 2022).
Model koperasi tambang rakyat seperti di Bolivia dan Peru juga bisa diadopsi, di mana penambang bergabung dalam organisasi resmi yang memudahkan akses pasar dan pendampingan teknis, serta mengurangi ketergantungan pada cukong.
Koperasi tambang rakyat juga dapat mengembangkan usaha sampingan, seperti perhutanan sosial atau perikanan darat, sehingga masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada emas.
Selain itu, skema sertifikasi emas berkelanjutan seperti Fairmined atau Fairtrade Gold terbukti memberi harga lebih baik bagi penambang yang menaati standar lingkungan.
Baca juga: Heboh Gubernur Sumut Razia Plat Kendaraan Aceh, Haji Uma: Jangan Rusak Hubungan Aceh-Medan
Sementara itu, pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, universitas, LSM, dan masyarakat lokal terbukti lebih efektif dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan (Meutia et al., 2023).
Aceh kini berada di persimpangan jalan. Jika hanya mengandalkan operasi aparat, tambang emas akan tetap menjadi sumber konflik dan kerusakan.
Namun, jika jalur izin resmi dibuka, koperasi rakyat diperkuat, dan mekanisme pengawasan dibuat transparan, emas dapat menjadi berkah.
Pemerintah Aceh Barat harus berani mengubah pendekatan: bukan lagi represi, tetapi legalisasi, edukasi, dan kolaborasi.
Hanya dengan cara ini, masyarakat tetap dapat hidup layak, lingkungan terselamatkan, dan negara benar-benar hadir sebagai pengayom, bukan penindas.
*) PENULIS adalah Underground Production, Drilling & Blasting Engineer di PT Freeport Indonesia I Alumni Teknik Pertambangan Unsyiah
KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Isi artikel menjadi tanggung jawab penulis.
Baca artikel KUPI BEUNGOH lainnya di SINI
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Edy-MirzaST_Blasting-Engineer-di-PT-Freeport-Indonesia-_Alumni-Teknik-Pertambangan-Unsyiah.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Veesam-SamohMahasiswa-USK-Banda-Aceh-asal-Thailand.jpg)



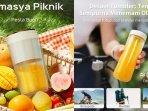


:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Renggha-Prima-ST-MH_Penggiat-Jaminan-Sosial-Ketenagakerjaan.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Dr-Mawardi-S-Th-I-MA-Dosen-Prodi-SAA-Fak-Ushuluddin-dan-Filsafat.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Miswar-Ibrahim-Njong-RTA.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Rifki-Hasan-Gayo.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Khairah-Mahasiswa.jpg)

![[FULL] Ekonom Celios Sebut Indonesia Belum Siap Redenominasi Rupiah: RI Butuh 8 hingga 9 Tahun Lagi](https://img.youtube.com/vi/E_lguIar2Dg/mqdefault.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Said-Ardiansyah-bin-Tamren-Al-Aydrus-Pengurus-di-Yayasan-Asyraf-Aceh-Darussalam.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/titi-anggraini-perludem.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Humam-Hamid-Whoosh.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/FERI-IRAWAN-Magelang.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Veesam-SamohMahasiswa-USK-Banda-Aceh-asal-Thailand.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.