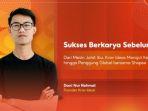Opini
Kantor Urusan Luar Negeri Aceh
Hampir satu tahun yang lalu, sebuah video berjudul "Dari Helsinki ke Stockholm" beredar di YouTube. Video itu menceritakan

Teuku Zulman Sangga Buana, S.H
Alumni Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Aktivis International Law Association (ILA) Indonesian Branch
Hampir satu tahun yang lalu, sebuah video berjudul "Dari Helsinki ke Stockholm" beredar di YouTube. Video itu menceritakan, di antaranya tentang bagaimana ketika Tim Perunding GAM melapor kepada Teungku Muhammad Hasan di Tiro mengenai upacara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki di kediamannya, Swedia.
Secara garis besar para tokoh Aceh itu membicarakan perihal bagaimana respon pihak asing terhadap Perjanjian Helsinki. Apa yang paling menarik perhatian dari perbincangan itu bagi penulis, ialah penggunaan dua bahasa sebagai bahasa pengantar pertemuan, bahasa Aceh dan Inggris.
Beberapa kali terdengar percampuran antara keduanya, seperti: "Nyoe na saboh teuk dari U.S. State Department" dan "Oh lheuh nyan, tapajoh lunch together." Untuk menyebut Menteri Luar Negeri dan Kementerian Luar Negeri, istilah yang digunakan ialah "menteri lua" dan "Kementerian Lua", cukup khas.
Video ini menambah keyakinan penulis, bahwa memang kemampuan Aceh dalam menjalin hubungan luar negeri pada masa kerajaan dahulu, bukanlah sesuatu yang terlalu dilebih-lebihkan. Lagi pula, banyak sudah tulisan-tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan menceritakan hal ini, antara lain sebagaimana digambarkan oleh Anthony Reid dalam bukunya "Asal Mula Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19 (2007)".
Keistimewaan secara hukum
Aceh kini sebagai bagian dari Republik Indonesia, secara hukum telah lama memiliki keistimewaan dalam bidang hubungan luar negeri. Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, dan juga Pasal 23 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur tentang keistimewaan itu.
Sayangnya hingga hari ini, Pemerintah Aceh tampak belum memanfaatkan secara maksimal keistimewaan itu. Walaupun ada upaya-upaya ke arah sana yang dapat disaksikan langsung oleh publik, seperti pelaksanaan turnamen sepak bola internasional Aceh World Solidarity Cup (AWSC), ikhtiar menghidupkan kembali Pelabuhan Kuala Langsa, dan upaya menyambungkan Aceh dengan Kepulauan Andaman-Nicobar, India-yang sekarang tidak lagi terdengar.
Belum maksimalnya pengelolaan kekhususan ini salah satunya dapat dilihat dari sisi struktur organisasi Pemerintah Aceh, yang tidak memiliki bidang khusus untuk menangani kekhususan dimaksud. Berbeda dengan struktur Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai Subbagian Kerja Sama Luar Negeri. Berbeda juga dengan Pemerintah Provinsi Papua yang memiliki Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri.
Untuk tingkat kabupaten/kota, Pemerintah Kota (Pemko) Bandung juga memiliki bidang yang serupa, yaitu Kerja Sama Luar Negeri (KSLN). Sehingga tidak mengherankan, kerja sama sister city (kerja sama antara pemerintah kota dengan pemerintah kota di luar negeri) Kota Bandung dapat dikelola dengan baik.
Sebagai perbandingan, berdasarkan data dari situs resmi masing-masing pemerintah kota, Pemko Bandung telah menjalin kerja sama sister city dengan setidaknya empat belas kota di luar negeri yang berasal dari sembilan negara yang berbeda. Berbanding jauh dengan Pemko Banda Aceh yang baru memiliki kerja sama sister city dengan tiga kota di luar negeri dari tiga negara yang berbeda.
Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud al-Haytar, memang pernah meminta kepada Wakil Menteri Luar Negeri untuk membuka foreign office atau Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) di Aceh agar memudahkan para investor dan orang asing mendapatkan informasi yang berhubungan dengan Aceh.
Namun yang mengagetkan, beliau meminta sebuah Kanwil dan mengapa bukan Kantor Urusan Luar Negeri sendiri? Mengingat kewenangan yang dimiliki Aceh dalam hal ini bukanlah kewenangan biasa, tetapi sebuah kewenangan khusus-dalam format desentralisasi.
Hubungan internasional
Penting disadari, bahwa hubungan internasional bukan soal orientasi ekonomis semata, tidak melulu soal investor saja, tapi berkenaan juga dengan banyak aspek lain: rule of law, politik, keamanan, kemanusiaan, kesehatan, dan yang menjadi salah satu isu global paling penting saat ini, yakni perubahan iklim.
Selain itu, hubungan internasional juga tidak hanya melibatkan pemerintah suatu negara atau pemerintah daerah suatu negara, tetapi melibatkan pula aktor-aktor lain seperti organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan multinasional, kelompok-kelompok minoritas, hingga individu. Ini menunjukkan bagaimana kompleksitas dari hubungan internasional itu.
Saat ini, interaksi people to people dalam masyarakat internasional pun terus meningkat. Bahkan secara teoritis dalam konsep hukum internasional, sudah lama sekali, setidaknya sejak awal abad dua puluh, individu telah diakui sebagai subjek hukum internasional (Malcolm N. Shaw QC, 2013: 234).
Pasal (1) ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pun menyebut bahwa, "Hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia."
Meskipun dalam konteks Aceh, bahkan Indonesia sekarang ini, hubungan dengan masyarakat awam dari negara lain masih merupakan hubungan yang superfisial, istilah Agus Wandi dalam bagian pengantar bukunya Terra Australis: Biografi Singkat Australia: Tetangga Penting dan Benua Terdekat Indonesia (2020). Dalam artian, hubungan itu masih acuh tak acuh yang tidak membuat saling kenal mengenal, atau tidak akrab.
Landasan dan kerangka
Oleh karenanya, untuk meningkatkan kerja sama luar negeri, perlu adanya arah yang jelas. Aceh perlu merumuskan dasar-dasar hubungan luar negerinya seperti apa, platform-nya bagaimana. Dengan demikian, upaya peningkatan tersebut dapat dikoordinasikan dengan baik. Tentunya dengan penyesuaian terhadap politik dan kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia.
Jika memiliki acuan dan kerangka kerja yang jelas, Aceh mungkin dapat memberikan respon yang lebih baik dalam bentuk solusi jangka pendek maupun jangka panjang terhadap isu-isu kemanusiaan, seperti yang baru saja dan telah berulang kali-sejak tahun 2009-kita hadapi, krisis Pengungsi Rohingya. Bukan tidak mungkin akan ada lagi gelombang berikutnya yang akan terdampar. Dan ini tentu hanya satu dari begitu banyak urusan internasional yang padanya Aceh dapat mengaitkan diri secara lebih nyata.
Maka kehadiran sebuah kantor atau badan yang fokus membidangi penyelenggaraan urusan luar negeri di Aceh menjadi urgen. Sebagai contoh konkrit, seperti Office of International Affairs (OIA) Universitas Syiah Kuala atau Kantor Penghubung Pemerintah Aceh yang ada di Jakarta, yang sebagian dari tugas dan fungsinya sudah menyentuh aspek-aspek kerja sama luar negeri.
Dengan begitu, diharapkan keistimewaan Aceh yang memiliki akar sejarah yang kuat dan diperjuangkan dengan penuh pengorbanan, tidak hanya tertulis saja di dalam lembaran negara, tetapi dapat benar-benar dimanfaatkan dengan baik. zulmansangga@gmail.com