Opini
Refleksi HUT Ke-819 Banda Aceh, Bangkit Bersama Menuju Impian Kota Bebas Sampah
Banda Aceh dengan sampah ibarat dua kata lucu yang sulit ditentang, bila dikata Banda Aceh adalah kota gemilang yang terbebas dari aroma-aroma tak men
Oleh: Muhammad Balia M Sos, Ketua Himpunan Pengusaha Santri Indonesia-Aceh
TANGGAL 22 April 2024 merupakan tanggal penuh harapan untuk Kota Banda Aceh, karena di tanggal istimewa tersebut, kota tua ini akan memperingati hari ulang tahunnya yang ke-819.
Banda Aceh sebagai kota urban yang banyak disinggahi kawanan orang-orang migran dari berbagai penjuru daerah pastinya akan menagih harapannya untuk bisa terwujud di hari ulang tahunnya ini.
Banda Aceh sudah lelah dengan semua carut marut yang terjadi, namun ia terus dipaksa bekerja tanpa henti, tanpa diberi waktu istirahat untuk memulihkan sendi-sendinya yang telah rapuh.
Romantisme Kota Banda Aceh telah terkikis dengan perlahan, ini semua disebabkan oleh tumpukan sampah yang terus-terusan menjadi persoalan.
Banda Aceh dengan sampah ibarat dua kata lucu yang sulit ditentang, bila dikata Banda Aceh adalah kota gemilang yang terbebas dari aroma-aroma tak menyenangkan, nyatanya Banda Aceh masih berkemelut dengan bau busuk sampah yang dihasilkan.
Menurut data Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan (DLHK3) Kota Banda Aceh, produksi sampah di tahun 2023 telah menyentuh angka 93 ribu ton. Angka sampah merangkak naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 90 ribu ton.
Baca juga: Sejak Januari Hingga April 2024 di Aceh Ada 184 Orang Meninggal Karena Kecelakaan
Untuk kisaran per harinya, rata-rata sampah yang dibawa armada pengangkut sampah bisa mencapai 250-an ton. Volume sampah ini diperkirakan akibat penambahan kepadatan jumlah penduduk serta diakibatkan oleh beberapa kegiatan yang dipusatkan di Kota Banda Aceh.
Sementara itu, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Banda Aceh yang berada di Gampong Jawa juga mengalami masalah pelik. TPA yang menampung sampah dari masyarakat kota gemilang sudah overload atau kelebihan beban.
Bahkan sebagian sampah yang berada di sana mesti di-sharing dengan tetangganya, yaitu TPA Regional Aceh Besar, agar menormalkan ketinggian tumpukan sampah untuk menghindari resiko terjadinya bencana longsor sampah.
Dilansir dari dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tahun 2024, Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh rupanya sudah menyusun peta jalan pengendalian sampah di kota berjuluk Serambi Mekkah itu.
Terdapat beberapa agenda yang akan diwujudkan dalam tahun ini, diantaranya dengan melakukan revitalisasi beberapa program lama yang telah dicetus sebelumnya, kemudian juga akan mengajak partisipasi masyarakat dan stakeholder terkait untuk secara aktif memilah sampah.
Pemko Banda Aceh rupanya menyadari betul bahwa pemilahan sampah saat ini masih belum berjalan maksimal. Oleh sebab itu, Pemko Banda Aceh berencana akan menambah titik-titik pemilahan sampah serta menambah sarana-prasarana pengolahan sampah.
Pemko Banda Aceh juga akan membuat jadwal sosialisasi, memberikan teguran kepada masyarakat dan stakeholder terkait yang tidak melakukan pengurangan sampah, serta memberikan informasi dan komunikasi kepada pihak-pihak yang terlibat secara berkelanjutan.
Apa yang Dibutuhkan? Hilirisasi!
Banda Aceh sudah berkemelut dengan sampah bertahun-tahun lamanya. Pemko Banda Aceh rupanya juga tidak pernah kehabisan akal untuk memikirkan aspek penting pengendalian lingkungan kota bebas sampah.
Ada banyak program yang telah dicetus dan dirangkai pemerintah untuk mengajak partisipasi masyarakat dalam menekan lonjakan sampah.
Salah satunya adalah Depo Bank Sampah Waste Collecting Point (WCP). Program ini telah berlangsung sejak tahun 2015, bahkan sudah ada 35 titik Depo Bank Sampah WCP yang tersebar di gampong-gampong Kota Banda Aceh.
Depo Bank Sampah WCP ini mengajak partisipasi masyarakat untuk mengelola dan memilah sampah langsung dari sumbernya. Kemudian sampah-sampah yang dipilah ini nantinya dapat ditukarkan dengan sembako maupun dengan mata uang.
Baca juga: Sejak Januari Hingga April 2024 di Aceh Ada 184 Orang Meninggal Karena Kecelakaan
Kemudian Pemko Banda Aceh juga membangun program rumah Composting House yang terletak di Gampong Ilie, Kecamatan Ulee Kareng. Rumah Composting House ini adalah tempat pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos.
Kompos-kompos yang dihasilkan sebagiannya ada yang dibagi-bagikan untuk warga sekitar, ada juga yang diperjualbelikan kepada pengusaha garden (kebun) yang ada di Kota Banda Aceh.
Itulah setidaknya dua kegiatan hilirisasi di samping kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Pemko Banda Aceh dalam menekan lonjakan sampah di Kota Serambi Mekkah.
Namun hilirasi tidak boleh berhenti pada dua inovasi yang ada. Pemerintah harus bisa memikirkan cara terbaik lainnya untuk membebaskan Banda Aceh dari tumpukan sampah.
Banda Aceh sebetulnya sudah lelah dengan sampah. Jika Banda Aceh manusia, mungkin saat ini ia sudah menyerah dengan keadaan.
Namun sayangnya ia tidak bisa beristirahat karena ada tugas dan amanah yang harus ia lakukan untuk memulihkan dirinya menjadi lebih “layak huni” bagi warganya.
Banda Aceh yang sabar ya. Meskipun baumu tak seharum dulu, kami wargamu masih sangat menyayangi dirimu.
Banda Aceh Zero Waste? Mengapa Tidak!
Segenap warga harus menjadikan HUT Banda Aceh ke-819 sebagai upaya untuk merefleksi dari rasa memiliki dan cinta tanah leluhur.
Rasa cinta itu bisa dimanifestasi dalam bentuk sederhana dengan rasa keterpanggilan untuk saling menjaga dan peduli terhadap kepentingan bersama.
Bahwa menjaga keindahan kota memang menjadi tanggung jawab pengelola kota ini, namun tanpa kepedulian dan keterpanggilan warga untuk saling menjaga dan berempati, rasanya terlalu berlebihan mengharapkan pengelola kota berkerja sendirian.
Upaya untuk menjadikan Banda Aceh sebagai kota impian bebas sampah bisa dimulai dari hal terkecil, misalnya dengan meneladani kemampuan Jepang dalam memanajemeni sampah.
Menurut literatur sejarah pengolahan sampah yang bertanggung jawab di masyarakat Jepang bukanlah kebiasaan yang dilakukan sejak zaman dahulu, tetapi kesadaran itu baru bangkit sekitar 25 tahun yang lalu.
Antara tahun 1960-1970-an, Jepang tempo dulu sama seperti Banda Aceh, kepedulian terhadap sampah dan lingkungan masih sangat rendah.
Sebagai negara yang baru bangkit pasca perang, Jepang berubah haluan menjadi negara industri yang fokus dalam pembangunan ekonomi negara.
Dengan menjadi negara industri, Jepang memproduksi lebih banyak sampah dari sebelumnya. Akibatnya polusi, pencemaran lingkungan, bahkan keracunan meningkat akibat dari pertumbuhan industri di Jepang.
Saat itu, Kota Tokyo menjadi salah satu kota yang mengalami dampak dari hal tersebut. Limbah dan sampah rumah tangga, menjadi masalah terbesar yang dirasakan oleh warga Tokyo.
Karena dampak negatif dari pertumbuhan industri dan ekonomi semakin dirasakan oleh masyarakat Jepang, barulah pada pertengahan tahun 1970 bangkit gerakan masyarakat peduli lingkungan atau dalam bahasa Jepangnya disebut “chonaikai”.
Sejak saat itu, kata Balia, masyarakat Jepang mulai menanamkan rasa peduli lingkungan lewat sosialisasi cara membuang dan memilah sampah agar memudahkan proses pembuangannya.
Chonakai menggunakan tema utamanya yaitu mengurangi pembuangan sampah, menggunakan kembali barang yang bisa digunakan dan daur ulang.
Chonaikai semakin didukung oleh masyarakat, tetapi pemerintah Jepang belum juga memiliki undang-undang yang mengatur pengelolaan sampah karena pemerintah beranggapan bahwa permasalahan sampah belum menjadi sebuah prioritas.
Hingga di bulan Juni 2000, Pemerintah Jepang mengesahkan undang-undang yang mengatur mengenai orientasi daur ulang atau Basic Law for Promotion of the Formation of Recycling Oriented Society.
Undang-undang ini dibuat untuk mengurangi dampak negatif yang masif di masa yang akan datang. Tidak hanya proses daur ulang, tetapi proses pembakaran sampah juga diterapkan untuk memenuhi program Zero Waste to Landfill (ZWTL).
Tidak hanya disebabkan oleh jumlah sampah yang berlebih di Kota Tokyo, Balia menjelaskan bahwa awal mula dari munculnya kesadaran masyarakat Jepang untuk melakukan gerakan peduli lingkungan juga diakibatkan dari munculnya efek dari tragedi Minamata pada tahun 1958.
Tragedi Minamata terjadi akibat dari buruknya pengolahan dan pembuangan limbah pabrik yang dilakukan oleh Pabrik Chisso. Pabrik Chisso membuang merkuri dan limbah berbahaya lain ke teluk Minamata yang menyebabkan tercemarnya air dan ikan yang ada di teluk tersebut.
Karena hal ini juga muncul kasus penyakit Minamata dimana penderita mengalami gejala kerusakan pada otak dan juga jaringan saraf tulang belakang. Di tahun 2001 ada lebih dari 1.700 korban meninggal akibat tragedi ini. Kejadian ini dijadikan sebagai pembelajaran oleh pemerintah Jepang.
Semenjak saat itu Jepang menjadi sangat peduli dengan pengolahan sampah dan limbah yang ada di negaranya. Bahkan menurut informasi, setiap warga Jepang dibekali dengan buklet berisi instruksi detail penyortiran 518 jenis barang. Hal ini dilakukan agar para warga mampu menyortir sampahnya sendiri dengan tepat.
Kesuksesan Jepang dalam memanajemeni sampah bisa dijadikan tolak ukur referensi oleh warga Banda Aceh yang ingin menjadikan Kota Banda Aceh sebagai taman impian kota bebas sampah.
Menurut Balia, jika Jepang mampu menjadi objek dunia sebagai negara bebas sampah, maka prestasi serupa juga mampu dicapai oleh Kota Banda Aceh.
Kuncinya terletak di kolaborasi. Kolaborasi sebagai pintu harapan untuk bangkit bersama, kolaborasi yang menjadi impian untuk maju bersama dan kolaborasi sebagai tujuan untuk masa depan bersama.
Optimisme Banda Aceh menuju Banda Aceh zero waste bukanlah hal yang mustahil untuk kita capai. Dengan semangat nilai-nilai para leluhur yang telah diajarkan kepada kita, sinergi yang solid serta kebersamaan untuk saling merawat dan menjaga lingkungan, pasti Banda Aceh mampu menjadi taman impian kota bebas sampah di Indonesia.

:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/meninjau-langsung-kondisi-Pasar-Rakyat-Kuala-Batee.jpg)




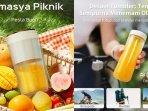


:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/uniki-080624-b.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Weri-2025.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Prof-Dr-Muhammad-Yasir-Yusuf-Warek-UIN.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/MUSLIM-KHADRI-MSM-Anggota-Komisi-Informasi-Aceh.jpg)


:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/emas-perhiasan-toko-emas-harga-emas-di-Banda-Aceh.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Gubernur-Aceh-Muzakir-Manaf-atau-Mualem_19032025.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Cerita-Adik-Kandung-Penembakan-Penjual-Bakso-Korban-Ramah-dan-Baik-Sama-Tetangga.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Kenak-Bujuk-Rayu-Kekasih-Wanita-Muda-Berzina-dengan-Pacar-di-Hotel-Banda-Aceh-Begini-Ceritanya.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/TITO-KARNAVIAN-12122025.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.