Opini
Spirit dan Strategi Pembangunan Aceh
ARTIKEL ini bermaksud menyambung diskusi para tokoh dalam acara Silaturrahmi Tahun Baru Islam 1440 Hijriah
Oleh Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad
ARTIKEL ini bermaksud menyambung diskusi para tokoh dalam acara Silaturrahmi Tahun Baru Islam 1440 Hijriah bersama Adnan Ganto, pada 13 September 2018 di Banda Aceh. Dalam diskusi yang membahas tentang masa depan pembangunan Aceh itu disampaikan bahwa penyebab kemandegan pembangunan Aceh adalah moral, etika, dan ego. (Serambi, 15/9/2018). Adnan Ganto berulang kali menyebutkan kata-kata ini yang menjadi penyebab kegagalan ketika ada harapan baru dalam pembangunan Aceh. Demikian pula, setiap pembangunan Aceh hendak dipersoalkan, selalu dimulai dengan angka kemiskinan. Hal lain yang muncul adalah persoalan non-teknis yang selalu menjadi penyebab kegagalan beberapa program strategis pembangunan Aceh.
Dalam opini ini, saya ingin menambahkan terdapat kesalahan berpikir di dalam membangun Aceh saat ini, yaitu selalu melihat Aceh dalam angka. Ketika angka naik, kita seolah-olah dikondisikan bahwa pembangunan Aceh sukses. Sebaliknya, jika angkanya turun, maka seolah-olah pembangunan di Aceh sudah gagal. Kerangka berpikir ini tidak keliru, walaupn tidak benar seluruhnya. Dalam membangun suatu daerah terdapat “persoalan non-angka” yang diwujudkan dalam bentuk rekayasa sosial dalam pembentukan mental dan pemanfaatan spirit dan energi rakyat.
Beberapa catatan
Dalam konteks ini, saya ingin memberikan beberapa catatan penting di dalam membangun Aceh ke depan: Pertama, harus diperbanyak orang Aceh yang menjalankan roda pemerintahan adalah mereka yang sudah selesai dengan diri sendiri. Mencari individu yang selesai dengan diri sendiri merupakan pekerjaan yang amat sulit. Sebab, jika belum selesai dengan diri sendiri, maka ketika menjalankan roda pembangunan, dia akan menjadi penyelesaian untuk dirinya sendiri, manakala diberikan otoritas dan kekuasaan untuk membangun Aceh. Djoko Santoso dalam Menggagas Indonesia Masa Depan (2014: 261-262), menutup karyanya tersebut dengan mencari pemimpin yang telah selesai dengan diri sendiri.
Jika pemimpin belum selesai dengan diri sendiri, maka kekuasaan tersebut akan menjadi masalah bagi dirinya sendiri. Pola pikir yang dibangun adalah mencari apa pun kesempatan untuk memuaskan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Perilaku ini lantas ditiru oleh bawahannya sampai ke level terbawah. Saat ini, situasi sosial dan budaya dalam pembangunan Aceh masih banyak dijumpai mereka yang belum selesai dengan diri sendiri. Padahal ketika ada masalah di diri sendiri, maka sebenarnya masalah tersebut akan berdampak pada proses dan hasil pembangunan, yang kemudian dirasakan dampaknya oleh rakyat kecil.
Kedua, keliru ketika memandang bahwa mengatur Aceh seperti mengatur negara. Setelah damai disepakati, memang ada kesan Aceh itu seperti negara yang berdaulat. Namun, piramida kekuasaan di Aceh sesungguhnya bukan piramida kekuasaan untuk menjalankan negara. Sebagai contoh, pemimpin Indonesia saat ini memiliki piramida di dalam menjalankan roda pembangunan. Di atas ada presiden, selanjutnya di bawah terhadap konglomerat, media, partai politik, aparat keamanan, dan rakyat kecil. Jadi, presiden hanya menjaga piramidnya supaya tidak tumbang kekuasaannya.
Sementara di Aceh, seorang pemimpin tidak akan mampu mengelola piramid kekuasaan secara sempurna. Saling sikat dan sikut adalah hal yang lumrah dijumpai saat ini di Aceh. Bahkan mereka yang berada di puncak, tidak pernah memiliki kekuasaan yang tuntas sampai ke akar rumput.
Para pemimpin kerap menjaga agar roda pemerintahannya tidak terganggu oleh orang-orang di sekitarnya. Sehingga dia terlalu sibuk ingin mempertahankan kekuasaannya, terkadang abai di dalam merealisasikan program-program pemerintahannya secara komprehensif. Karena itu, tidak mengejutkan ketika piramid kekuasaan beberapa pemimpin di Aceh, malah menjadi benalu di dalam kemelut kekuasaannya mereka sendiri, yang berdampak pada pembangunan jangka pendek dan jangka panjang.
Di Aceh, jika dibentuk piramid kekuasaan, mulai dari Wali Nanggroe atau Gubernur, maka sampai ke bawahnya selalu berada dalam kemelut atas nama kepentingannya sendiri. Kondisi ini menyebabkan muncul ego sektoral --sebagaimana disinyalir oleh Adnan Ganto-- di antara dinas/badan yang menjadi penggerak pembangunan di Aceh. Tidak hanya, pembangunan di Aceh harus tersungkur di hadapan para individu yang dipandang memiliki pengaruh dalam piramida kekuasaan. Akibatnya, yang muncul ke permukaan adalah tontonan mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri, ketimbang berpikir menyelesaikan masalah rakyat Aceh.
Ketiga, perlu dipikirkan bahwa jangan terlalu meng-angka-kan masalah sosial di Aceh. Masalah sosial perlu diselesaikan melalui pola pikir pada level apa rekayasa sosial yang ingin diwujudkan dalam pembangunan Aceh. Saat ini, ketika Aceh dibidik dalam angka pembangunan, maka yang kerap dikupas adalah angka kemiskinan. Setiap seminar, isu ini seolah-olah menjadi masalah utama pembangunan Aceh. Kemudian yang paling sering disalahkan pada masalah mental dan moral yang berujung pada nilai-nilai agama.
Sedangkan yang sesuatu yang menjadi anugerah di Aceh (sumber daya alam) yang menjadi nilai plus, selalu dinikmati hasilnya oleh provinsi tetangga dan negara luar. Padahal ketika angka-angka dimunculkan, didiskusikan, diputuskan, diprogramkan, dan direalisasikan dalam berbagai kegiatan, nilai-nilai agama malah tidak pernah dijadikan sebagai pedoman. Saat ada masalah, ramai-ramai mengundang agama di dalamnya untuk menyelesaikan kemelut dalam pembangunan.
Rekayasa sosial di dalam pembangunan bukanlah hanya persoalah angka. Ketika Snouck Hurgronje (1857-1936), mengubah kebijakan pemerintah Belanda di Aceh, dia melakukan proses perubahan pada struktur kesadaran masyarakat Aceh. Struktur kesadaran adalah bagian terdalam ketika membangun jiwa dan pikiran yang mampu mengubah perilaku rakyat. Ilmuwan dapat memetakan pola-pola kesadaran di dalam masyarakat, mulai dari level tertinggi hingga terendah.
Para ilmuwan juga dapat memetakan lanskap sosial dan budaya dalam suatu masyarakat. Sehingga pembangunan yang didampakan sebagai perubahan dapat dilakukan secara holistik. Pemerintah pada ujungnya melakukan implementasi rekayasa sosial yang dihasilkan oleh para ilmuwan. Inilah salah satu jasa terbesar Snouck Hurgronje di dalam melakukan proses rekayasa ulang terhadap kehidupan rakyat Aceh.
Kesadaran sosial
Struktur kesadaran sosial dapat dibangun melalui pola etika, seni, nilai, moral, agama, dan ilmu pengetahuan. Jutaan pemirsa merinding ketika menyaksikan tarian Aceh di acara Asian Games 2018 lalu. Dalam tarian singkat ini mampu memuat semua aspek fondasi struktur sosial, sehingga jiwa dan pikiran yang menonton merespons secara positif.
Tentu saja, penggerak pembangunan di Aceh masih meraba-raba apa di balik “merinding” pemirsa yang dapat dituangkan dalam strategi pembangunan. Tarian tersebut adalah akumulasi dari sistem etika, nilai, moral, agama dan pengetahuan yang terdapat di Aceh yang mampu memberikan energi kepada siapa pun penikmatnya. Hanya saja, pemerintah Aceh belum punya perangkat mengambil energi tersebut dalam spirit pembangunan.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/adnan-ganto-bicara-dalam-diskusi_20180914_015334.jpg)








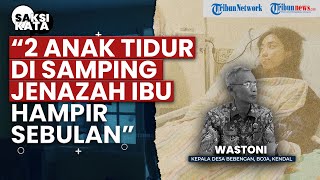
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Periskila-Dina-Kali-Kulla-SPd-MSc-2025.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Dr-Ainal-Mardhiah-S-Ag-MAg-Dosen-Pascasarjana-UIN-Ar-Raniry-Banda-Aceh.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Guru-Besar-Bidang-Geologi-Kelautan-USK-Prof-Muhammad-Irham.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Prof-Dr-dr-Rajuddin-SpOGK-SubspFER-17-11.jpg)