Serambi MIHRAB
Seni Budaya Sufi
MUSIK dan tarian Sufi seperti digelar di panggung terbuka Tamansari, Banda Aceh, awal Oktober ini, hanyalah
MUSIK dan tarian Sufi seperti digelar di panggung terbuka Tamansari, Banda Aceh, awal Oktober ini, hanyalah sebagian kecil dari budaya dan kehidupan kaum Sufi. Ini bukan kali pertama kesenian sufi hadir di Aceh. Jauh sebelumnya grup musik dengan genre serupa sudah berkali-kali digelar di bumi Serambi Mekkah ini. Sebut saja grup band Debu, misalnya, yang sebagian besar personalnya berasal dari Amerika Serikat, sudah pernah bersenandung dan membuat decak-kagum warga Aceh, di Taman Budaya Banda Aceh.
Bagi kaum Sufi, berkesenian itu adalah sebagai sarana dakwah, mengajak manusia untuk mengenal Tuhan, mengagungkan dan mengungkapkan rasa cintanya kepada Sang Pencipta. Para walisongo yang mendakwahkan Islam di tanah Jawa dan jagad Nusantara dulu, menggunakan sarana ini untuk mengenalkan Islam. Demikian pula ulama-ulama besar Aceh seperti Hamzah Fanshuri, Nuruddin Ar-Raniry, Abdurrauf As-Singkili, Syamsuddin As-Sumatrany dan para penerus mereka, kerap memasukkan unsur budaya dan berkesenian dalam dakwah-dakwahnya.
Gerak tubuh dan rentang tangan yang diiringi musik marawis (rebana), yang sering kita saksikan dalam kesenian Sufi, bukanlah ungkapan atau gerak yang tak bermakna. Tari dengan formasi dan gerakan berputar-putar (Sufi Whirling Dervishes), misalnya, yang kini telah mendunia itu tidak lain adalah adalah penggambaran bumi dan roda kehidupan yang selalu berputar. Bergerak dinamis dan berputar pada sumbunya, yang diartikan sebagai ungkapan cinta agung makhluk kepada al-Khaliknya. Cinta kepada sang Pencipta, Allah Swt, adalah inti dari ajaran, budaya dan kehidupan kaum Sufi.
Gerakan ‘zuhud’
Paham/aliran Sufi (Sufisme) atau Tasawuf adalah satu ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihan akhlak, membangun dhahir dan batin serta untuk memporoleh kebahagian yang abadi. Ini pada awalnya merupakan gerakan zuhud (menjauhi hal-hal yang bersifat duniawi) yang dalam perkembangan berikutnya melahirkan tradisi mistisme Islam, termasuk tarekat yang kita kenal sekarang. Pemikiran Sufi muncul di Timur Tengah pada abad ke-8, sekarang tradisi ini sudah tersebar ke seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia dan lebih khusus lagi Aceh.
Beberapa sumber perihal etimologi Sufi, menyebutkan bahwa kata Sufi ini berasal dari suf, yang dalam bahasa Arab berarti wol. Kata suf ini merujuk kepada jubah sederhana yang sering terlihat dikenakan oleh para asetik Muslim. Namun tidak semua Sufi mengenakan jubah atau pakaian dari wol. Ada juga yang berpendapat bahwa sufi berasal dari kata saf, yakni barisan dalam shalat. Sementara teori etimologis yang lain menyatakan bahwa akar kata dari Sufi adalah safa, yang berarti kemurnian. Hal ini menaruh penekanan pada Sufisme pada kemurnian hati dan jiwa.
Teori lainnya menyebutkan bahwa tasawuf berasal dari kata theosofie (bahasa Yunani) artinya ilmu ketuhanan. Banyak pendapat yang pro dan kontra mengenai asal usul ajaran tasawuf, apakah ia berasal dari luar atau dari dalam agama Islam sendiri. Berbagai sumber mengatakan bahwa ilmu tasauf sangat lah membingungkan. Sebagian pendapat mengatakan bahwa paham tasawuf merupakan paham yang sudah berkembang sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasulullah (Qardhawi, Hakekat Tasawuf).
Konon, pada sekitar abad ke-8 Masehi, orang-orang yang baru memeluk agama Islam di Irak dan Iran, hidupnya tetap bersahaja, jauh dari kemewahan dan kesenangan duniawi. Mereka terdorong oleh kesungguhannya untuk mengamalkan ajarannya, yaitu berendah-rendah diri dan berhina-hina diri terhadap Tuhan. Mereka selalu mengenakan pakaian yang pada waktu itu termasuk sangat sederhana, yaitu pakaian dari kulit domba yang masih berbulu. Itulah sebabnya maka pahamnya kemudian disebut paham sufi, sufisme atau paham tasawuf. Sementara orang yang penganut paham tersebut disebut orang sufi.
Sebagian pendapat lagi mengatakan bahwa asal usul ajaran tasawuf berasal dari zaman Nabi Muhammad SAW. Berasal dari kata “beranda” (suffa), dan pelakunya disebut dengan ahl al-suffa. Mereka dianggap sebagai penanam benih paham tasawuf yang berasal dari pengetahuan Nabi Muhammad saw. Pendapat lain menyebutkan tasawuf lahir seiring dengan munculnya pertikaian antarumat Islam pada zaman Khalifah Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, khususnya karena faktor politik.
Pertikaian antarumat Islam karena karena faktor politik dan perebutan kekuasaan ini terus berlangsung di masa khalifah-khalifah sesudah Usman dan Ali. Munculah masyarakat yang bereaksi terhadap hal ini. Mereka menganggap bahwa politik dan kekuasaan merupakan wilayah yang kotor dan busuk. Mereka melakukan gerakan ‘uzlah , yaitu menarik diri dari hingar-bingar masalah duniawi yang seringkali menipu dan menjerumuskan. Lalu munculah gerakan tasawuf yang dipelopori oleh Hasan Al-Bashiri (abad ke-2 Hijriyah). Kemudian diikuti oleh figur-figur lain seperti Shafyan al-Tsauri dan Rabi’ah al-‘Adawiyah (Solihin, M Anwar, M Rosyid. Akhlak Tasawuf, 2005).
Syariat dalam perspektif faham kaum Sufi atau tasawuf, digambarkan dalam bagan “4 tingkatan spiritual umum, yaitu syariat, tarekat (tariqah), hakikat, dan makrifat. Sebuah tingkatan menjadi fondasi bagi tingkatan selanjutnya, maka mustahil mencapai tingkatan berikutnya dengan meninggalkan tingkatan sebelumnya. Sebagai contoh, jika seseorang telah mulai masuk ke tingkatan (kedalaman beragama) tarekat, hal ini tidak berarti bahwa ia bisa meninggalkan syariat. Yang mulai memahami hakikat, maka ia tetap melaksanakan hukum-hukum maupun ketentuan syariat dan tarekat.
Tarekat (tariqah) berarti “jalan” atau “metode”, dan mengacu pada aliran kegamaan tasawuf atau sufisme dalam Islam. Ia secara konseptual terkait dengan hakikat atau “kebenaran sejati”, yaitu cita-cita ideal yang ingin dicapai oleh kaum Sufi. Seorang penuntut ilmu agama akan memulai pendekatannya dengan mempelajari hukum Islam, yaitu praktik eksoteris atau duniawi Islam, dan kemudian berlanjut pada jalan pendekatan mistis keagamaan yang berbentuk tariqah. Melalui praktik spiritual dan bimbingan seorang pemimpin tarekat, calon penghayat tarekat akan berupaya untuk mencapai hakikat atau kebenaran sejati itu.
Kesenian Sufi
Kembali ke soal musik dan tarian Sufi, Kementerian Agama (Kemenag) RI sendiri pada 2011 lalu, pernah menggelar Festival Internasional Musik Sufi (International Festival for Mystical Music) yang diikuti oleh 126 negara, di Jakarta. Festival yang baru pertama kali digelar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara itu, ditujukan untuk menumbuhkan minat masyarakat terhadap musik sufi sebagai bagian kesenian bernuansa islami.
Event tersebut juga dimaksudkan untuk menciptakan semangat toleransi dan ukhuwah islamiyah antarnegara yang berbeda tradisi dan budaya dengan mengeksplorasi keseniannya masing-masing yang bernafaskan Islam itu. Ajang ini mampu memberikan informasi tentang kesenian musik Sufi sebagai sarana dakwah yang waktu itu memang belum banyak diketahui masyarakat Indonesia.
Terbukti, dakwah melalui kesenian lebih efektif dari pada jalur formal, seperti ceramah atau tausiyah. Setidaknya, ini terlihat dalam dakwah Wali Songo yang menggunakan seni untuk menyebarkan syiar Islam, yang kini telah menyebar ke seluruh penjuru Nusantara.
Di sini terlihat bahwa dengan seni, dakwah jadi lebih personal dan langsung bisa dirasakan masyarakat. Kekhasan musik sufi yang beragam bentuknya, seperti tarian dan nyanyian sufi adalah sebagai ekspresi keragaman menuju pendekatan Ilahi. Musik, memiliki fungsi penting dalam perjalanan spiritualitas manusia.
Oleh sebab itulah, baik Festival Internasional Musik Sufi maupun berbagai even lokal yang berlangsung di daerah, termasuk yang berlangsung di Tamansari, Banda Aceh itu, diharapkan menjadi titik kebangkitan kesenian Islam, yang mampu menyuguhkan nilai seni spiritual tertinggi dalam mendekatkan diri kepada sang Pencipta. (dari berbagai sumber/asnawi kumar)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Relawan-TBM-RUMAN-Aceh-mendata-koleksi-bacaan-khusus-untuk-pojok-keacehan.jpg)








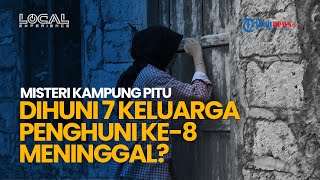
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/SERAMBI-RUN.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/workshop-Kreatif-Digital-dan-AI-Aman-Ruman-Aceh.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Juara-3-Essay-Competition-UI-SDGs-Summit-2025.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/pemuda-di-Meulaboh-diedukasi-tentang-cara-meningkatkan-potensi-diri.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Mhd-Al-Amin-Nasution-memberikan-pemaparan-saat-Pengabdian-Kepada-Masyarakat-di-Malaysia.jpg)