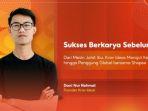Opini
Identitas Aceh, Suci dalam Debu
Bangsa Aceh itu adalah ‘anak singa’, bukan keturunan biri-biri yang kapan saja dapat dibeli, disembelih...
Namun, kegemilangan tersebut, tiba-tiba redup dan terhempas oleh kencangnya badai ideologi kolonialisme yang diperagakan oleh kolonial Eropa, yaitu ketika kuasa Eropa terlibat dalam pertarungan kepentingan politik, ekonomi dan keamanan di Selat Malaka dan Sumatera, pascaperang Eropa tamat 1815 yang melibatkan Prancis, Inggris, Spanyol, dan Belanda. Sejarawan mencatat bahwa konflik internasional ini berpengaruh kepada Aceh, karena posisi Aceh merupakan penentu kestabilan keamanan di Selat Melaka dan Sumatera (Lem Kam Hing, 1995).
Memasuki abad ke-20, posisi Aceh mulai terhimpit oleh dua kekuatan, yaitu munculnya kuasa Eropa yang menanam benih ideologi nasionalisme dan demokrasi kepada anak jajahannya dan sikap politik Eropa yang mengisolasi dari peta politik internasional, karena dinilai Aceh telah kehilangan sahabat setia, seperti Turki dan Inggris. Hal ini terbukti kemudian bahwa kedua masalah inilah yang melilit hingga Aceh tidak dapat lagi membebaskan diri dari perangkap itu.
Lebih dari itu, Aceh dikepung, disembelih dan dilapah bersama-sama oleh kuasa Eropa dan anak-anak wathan yang telah terpengaruh oleh ajaran nasionalisme dan demokrasi Barat. Seiring dengan itu, identitas kebangsaan Aceh tenggelam ke dasar lautan, yang hampir-hampir tidak dapat dikenali lagi wujudnya. Aceh menghilang dari pentas politik internasional dan nama Aceh pun tidak lagi bergetar di dada masyarakat Melayu.
Cermin sejarah
Berangkat dari fenomena sosial-politik dan sejarah inilah, Hasan di Tiro (1925-2010) bangkit bersaksi di depan cermin sejarah Aceh dengan menyatakan kemerdekaan Aceh pada 4 Desember 1976. Keputusan politik ini sebenarnya untuk menghadirkan identitas kebangsaan Aceh yang telah menghilang, menghidupkan jiwa-jiwa yang mati agar bangkit membangun mimpi-mimpi tentang fragmen-fragmen identitas Aceh yang sudah tenggelam diangkat ke permukaan, agarianya hidup bersemi dalam kehidupan bangsa Aceh, karena identitas kebangsaan yang tersimpan dalam fragmentasi masa lalu Aceh yang tenggelam itu, bukan saja telah terjadi proses kehancuran; tetapi juga terjadi kristalisasi yang terjadi di kedalaman laut, di mana ia tenggelam dan merusak apapun yang pernah hidup.
Beberapa hal yang “menanggung perubahan laut” dan bertahan hidup dalam bentuk-bentuk dan wajah baru yang terkristalisasi, yang tetap kebal terhadap elemen-elemen itu dan mereka hanya menanti penyelam mutiara yang pada suatu hari akan mendatangi mereka dan membawanya ke dunia kehidupan --sebagai “fragmen-fragmen pemikiran”, sebagai sesuatu “yang kaya dan asing”-- dan mungkin sebagai Urphae-nomene yang abadi (Maurizio Passerin d’Entéves dalam Filsafat Politik Hannah Arendt, 1982).
Memandang semua itu, ketika si penyelam (Hasan Tiro) itu hadir dan berjuang untuk menghidupkan tradisi berpikir dan identitas kebangsaan Aceh yang mati dibunuh oleh penjajah; disambut hangat di Aceh dan di gelanggang politik internasional. Dunia mesti sadar bahwa “isu Aceh itu berbeda dengan isu yang terjadi di Pulau Jawa, sebab Aceh memiliki hubungan internasional, terutama dengan Turki, Inggris dan Amerika.” (Paul Van Veer, 1985). Dan, Hasan Tiro berorasi, “Bangsa Aceh itu adalah ‘anak singa’, bukan keturunan biri-biri yang kapan saja dapat dibeli, disembelih, dan dilapah oleh algojo-algojo”.
Oleh sebab itu, fragmentasi masa silam tidak hanya sekadar untuk diingat, “melainkan mendidik, agar kita tidak terjerumus ke dalam kejumudan dan memenjarakan jiwa. Manusia historis perlu mengubah jiwanya kepada kesadaran supra-historis, mempunyai keyakinan dan harapan akan masa depan, yang memandang kebahagiaan itu selalu berproses dan disempurnakan pada setiap waktu.” (Frederich Nietzsche, filosuf asal Jerman). Wallahu a’lam bissawab.
* Dr. Yusra Habib Abdul Gani, SH., Direktur Institute for Ethnics Civilization Research, Denmark. Email: yusragani@gmail.com