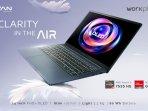Opini
Identitas Aceh, Suci dalam Debu
Bangsa Aceh itu adalah ‘anak singa’, bukan keturunan biri-biri yang kapan saja dapat dibeli, disembelih...
Oleh Yusra Habib Abdul Gani
WAJAH ketulusan politik dan identitas kebangsaan Aceh yang diperagakan lewat hubungan internasional, regional, termasuk format kebijakan politik dalam negeri, hanya dapat dikenali dalam catatan sejarawan yang kemudian dipakai menjadi referensi. Identitas kebangsaan Aceh serupa itu, tidak dikenal dalam realitas politik yang disaksikan sekarang.
Belakangan ini kita baru tahu dan sadar, kalau Aceh sebuah bangsa yang memiliki tamadun berteraskan Islam, pernah menawarkan identitas kebangsaan Aceh melalui ketulusan politik kepada kekhalifahan Osmaniyah Turki, sambil menyerahkan bungong jaroe berupa lada dan bendera Aceh. Saat berlabuh di pelabuhan Ankara, diplomat Aceh mengibarkan bendera Turki di atas geladak kapal Aceh, sebagai isyarat mau bersahabat, sekaligus menyatakan tunduk dan meminta diikut-sertakan menjadi satu negara di bawah perlindungan kekhalifahan Turki. Peristiwa ini berlaku pada 1520.
Diplomat Aceh menunggu lebih dari sebulan lamanya dalam kapal, sebelum diterima oleh penguasa Turki. Tawaran identitas kebangsaan Aceh akhirnya diterima dan membuahkan hubungan persahabatan antara kedua negara, dan terus kekal hingga meletus perang antara Belanda-Aceh pada 1873.
Turki kemudian membalas tawaran Aceh dengan mengirim perlengkapan senjata perang untuk menghadapi kekuatan Belanda, setelah Sultan Ibrahim Alaidin Mansur Syah (1838-1870) mengirim surat secara resmi kepada penguasa Turki. Meriam yang diberi oleh pemerintah Turki dengan nama Lada Sicupak, kini disimpan dalam Museum Militer di Bronbeek, Arnhem, Nederlands.
Dari sudut pandang moral politik dan hubungan internasional; tawaran identitas kebangsaan Aceh bersulam ketulusan hati (common sense) kepada pemerintah Turki adalah merupakan sebuah tradisi terhormat dalam sejarah perjalanan tamadun manusia.
Identitas kebangsaan
Tradisi memperkenalkan dan menawarkan identitas kebangsaan dengan ketulusan politik yang demikian, sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah, ketika mengirim sepucuk surat kepada Raja Rum dengan menyebut “Dari Muhammad Rasulullah/Hamba Allah, kepada Harikal ‘Adhim ar-Rum” pada kepala surat.
Pemberian gelaran harikal ‘adhim merupakan simbol identitas Islam yang sangat mulia. Selanjutnya Baginda menulis “... Aku menyeru engkau dengan seruan Islam. Islamlah! Niscaya engkau selamat. Allah memberi pahala kepadamu dengan dua jenis. Pertama, kepada engkau. Kedua, rakyat engkau. Jika engkau berpaling, maka engkau menanggung dosa rakyatmu.” (Teks lengkap tersimpan di Museum di Istanbul, Turki).
Pangeran Maurits van Nassau juga mengamalkan tradisi menawarkan identitas kebangsaan Belanda melalui surat yang dikirimnya kepada Sultan Alaudin Ali Riayat Syah IV (1589-1604) dengan menyebut “Sri baginda yang mulia dan yang Maha berkuasa”. Surat tersebut ditutup dengan mengucap “Kami cium tangan Sri Baginda” (Yusra Habib Abdul Gani, 2008, hlm. 169).
Maurits bahkan mengadu kepada Sultan Aceh prihal penderitaan bangsanya di bawah jajahan Spanyol. Belanda respek dan simpati dengan sikap politik Aceh yang telah memberi pengakuan (recognation) bahwa Belanda adalah negara merdeka, di saat Belanda masih merupakan satu dari 17 provinsi di bawah jajahan Spanyol.
Namun, ketulusan politik Belanda tercoreng, apabila Belanda menganggap telah melakukan kesalahan karena telah mengakui bahwa Aceh sebagai sebuah negara merdeka melalui Traktat London 1824. Bahkan memprovokasi segelintir uleebalang hingga nekad mengibarkan bendara Belanda di Idi, Aceh Timur, dan menolak membayar pajak kepada pemerintah Aceh.
Peristiwa ini berlaku, justeru setelah perjanjian persahabatan antara Belanda-Aceh ditandatangani pada 1857. Tragisnya, Inggris yang menandatangani Perjanjian Raffles 1819, terpengaruh dan sanggup mengkhianati Aceh lewat Perjanjian Sumatera 1871. Inggris membatalkan Perjanjian itu pada 1871 dan Aceh membatalkannya pada 1 Mei 1873. (Anthony Reid, 2007, hlm 150.). Padahal Ratu Inggris pernah menawarkan identitas kebangsaannya kepada Aceh, yang diutarakan melalui surat diplomatik kepada Sultan Iskandar Muda (1607-1636).
Jenderal de Beaulieu juga pernah menawarkan identitas kebangsaan Prancis dengan ketulusan politik melalui sepucuk surat dari kepala negara Prancis yang diserahkannya kepada Sultan Iskandar Muda. Surat tersebut dibalas dengan tulisan bertinta emas, yang antaranya menyebut, “berhubungan dengan tawaran, apakah saya memerlukan sesuatu dari Prancis, saya sampaikan melalui Kapten Jenderal de Beaulieu sebuah laporan untuk menunjukkan betapa besar penghargaan saya, dan saya katakan pula jika Allah mengarahkan surat ini dengan selamat, saya mengharapkan jawaban dengan kapal-kapal yang bakal datang dengan muatan barang dagangan...” (Yusra Habib Abdul Gani, 2008, hlm. 164).
Betapa pentingnya moralitas dan identitas kebangsaan ini, nampak dari prilaku seorang uleebalang di Aceh Timur, di mana pedagang Prancis pernah menitipkan barang dagangannya selama jangka masa dua tahun lamanya, tanpa mengalami kerusakan apa pun, sebab dijaga dengan amanah (Anthony Reid, 2007).
Fragmen-fragmen identitas kebangsaan Aceh dan ketulusan politikterhadap sesama masyarakat Islam maupun non-muslim yang mengagumkan ini terlaksana karena Aceh dihormati sebagai sebuah negara merdeka. Kekaguman bangsa luar terhadap Aceh, masih tetap menyerah hingga abad ke19.
Namun, kegemilangan tersebut, tiba-tiba redup dan terhempas oleh kencangnya badai ideologi kolonialisme yang diperagakan oleh kolonial Eropa, yaitu ketika kuasa Eropa terlibat dalam pertarungan kepentingan politik, ekonomi dan keamanan di Selat Malaka dan Sumatera, pascaperang Eropa tamat 1815 yang melibatkan Prancis, Inggris, Spanyol, dan Belanda. Sejarawan mencatat bahwa konflik internasional ini berpengaruh kepada Aceh, karena posisi Aceh merupakan penentu kestabilan keamanan di Selat Melaka dan Sumatera (Lem Kam Hing, 1995).
Memasuki abad ke-20, posisi Aceh mulai terhimpit oleh dua kekuatan, yaitu munculnya kuasa Eropa yang menanam benih ideologi nasionalisme dan demokrasi kepada anak jajahannya dan sikap politik Eropa yang mengisolasi dari peta politik internasional, karena dinilai Aceh telah kehilangan sahabat setia, seperti Turki dan Inggris. Hal ini terbukti kemudian bahwa kedua masalah inilah yang melilit hingga Aceh tidak dapat lagi membebaskan diri dari perangkap itu.
Lebih dari itu, Aceh dikepung, disembelih dan dilapah bersama-sama oleh kuasa Eropa dan anak-anak wathan yang telah terpengaruh oleh ajaran nasionalisme dan demokrasi Barat. Seiring dengan itu, identitas kebangsaan Aceh tenggelam ke dasar lautan, yang hampir-hampir tidak dapat dikenali lagi wujudnya. Aceh menghilang dari pentas politik internasional dan nama Aceh pun tidak lagi bergetar di dada masyarakat Melayu.
Cermin sejarah
Berangkat dari fenomena sosial-politik dan sejarah inilah, Hasan di Tiro (1925-2010) bangkit bersaksi di depan cermin sejarah Aceh dengan menyatakan kemerdekaan Aceh pada 4 Desember 1976. Keputusan politik ini sebenarnya untuk menghadirkan identitas kebangsaan Aceh yang telah menghilang, menghidupkan jiwa-jiwa yang mati agar bangkit membangun mimpi-mimpi tentang fragmen-fragmen identitas Aceh yang sudah tenggelam diangkat ke permukaan, agarianya hidup bersemi dalam kehidupan bangsa Aceh, karena identitas kebangsaan yang tersimpan dalam fragmentasi masa lalu Aceh yang tenggelam itu, bukan saja telah terjadi proses kehancuran; tetapi juga terjadi kristalisasi yang terjadi di kedalaman laut, di mana ia tenggelam dan merusak apapun yang pernah hidup.
Beberapa hal yang “menanggung perubahan laut” dan bertahan hidup dalam bentuk-bentuk dan wajah baru yang terkristalisasi, yang tetap kebal terhadap elemen-elemen itu dan mereka hanya menanti penyelam mutiara yang pada suatu hari akan mendatangi mereka dan membawanya ke dunia kehidupan --sebagai “fragmen-fragmen pemikiran”, sebagai sesuatu “yang kaya dan asing”-- dan mungkin sebagai Urphae-nomene yang abadi (Maurizio Passerin d’Entéves dalam Filsafat Politik Hannah Arendt, 1982).
Memandang semua itu, ketika si penyelam (Hasan Tiro) itu hadir dan berjuang untuk menghidupkan tradisi berpikir dan identitas kebangsaan Aceh yang mati dibunuh oleh penjajah; disambut hangat di Aceh dan di gelanggang politik internasional. Dunia mesti sadar bahwa “isu Aceh itu berbeda dengan isu yang terjadi di Pulau Jawa, sebab Aceh memiliki hubungan internasional, terutama dengan Turki, Inggris dan Amerika.” (Paul Van Veer, 1985). Dan, Hasan Tiro berorasi, “Bangsa Aceh itu adalah ‘anak singa’, bukan keturunan biri-biri yang kapan saja dapat dibeli, disembelih, dan dilapah oleh algojo-algojo”.
Oleh sebab itu, fragmentasi masa silam tidak hanya sekadar untuk diingat, “melainkan mendidik, agar kita tidak terjerumus ke dalam kejumudan dan memenjarakan jiwa. Manusia historis perlu mengubah jiwanya kepada kesadaran supra-historis, mempunyai keyakinan dan harapan akan masa depan, yang memandang kebahagiaan itu selalu berproses dan disempurnakan pada setiap waktu.” (Frederich Nietzsche, filosuf asal Jerman). Wallahu a’lam bissawab.
* Dr. Yusra Habib Abdul Gani, SH., Direktur Institute for Ethnics Civilization Research, Denmark. Email: yusragani@gmail.com