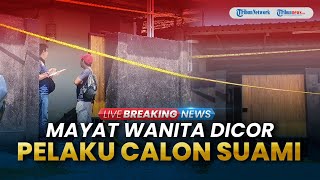Opini
Budaya Pop "Hasanah"
Beberapa bulan terakhir terjadi tren cukup menghebohkan di dunia fashion Aceh. Namun, fenomena ini tidak berhubungan dengan fashion
Oleh Teuku Kemal Fasya, Dosen Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh
Beberapa bulan terakhir terjadi tren cukup menghebohkan di dunia fashion Aceh. Namun, fenomena ini tidak berhubungan dengan fashion perempuan atau sosialita yang berharga mahal nan modern, seperti tas, abaya, atau sepatu.
Tren itu ialah munculnya fenomena massal menggunakan kupiah meukeutop atau kopiah yang digunakan Teuku Panglima Polim dan last emperor of Aceh, Sultan Muhammad Daudsyah di masa lalu. Tentu pada masa kini, kopiah yang digunakan tidak menjulang seperti era akhir abad 19 atau awal abad 20 itu. "Stupa"nya dipangkas sehingga lebih nyaman dan fungsional saat digunakan bersantai, kegiatan resmi, atau salat. Kopiah ini diproduksi oleh pengrajin tradisional asal Aceh Besar dan Pidie.
Di pesisir timur Aceh, muncul pula model kopiah serupa dengan menggunakan motif pintu (pinto) Aceh dan ornamen tipikal Samudera Pasai. Namun baik model Aceh Rayeuk dan Pasee, keduanya menggunakan motif etnografis "Sumutrah", yaitu mengeksploitasi penggunaan warna merah, kuning, dan hijau, dengan kombinasi warna hitam dan putih secara instrumental.
Menurut Rahmi Fajri, seorang pemuda yang menjual kopiah ini, gerakan penggunaan kupiah Aceh lahir dari sekelompok akademisi yang ingin menggugah kegemilangan masa lalu Aceh dengan bergaya vintage. Tapi demi melihat bagaimana industri ini berkembang, akademisi yang dianggap sebagai pelopor kupiah meukeutop itu bukan tokoh sentral komersialisasi, karena mereka tak ikut kaya raya seperti Mark Zuckerberg dan Eric Yuan dari facebook dan zoom. Mereka masih menjadi sosok sederhana, hanya menjadi pengiklan sosial.
Kini kelompok yang dianggap sebagai pencetus itu seperti Dr. Teuku Muttaqin Mansur dan kawan-kawan sedang berjuang untuk memunculkan gerakan satu juta kupiah Aceh. Kopiah ini pun mulai megah di pasar nasional karena diproduksi oleh pengrajin di pulau Jawa dengan daya edar di kota-kota besar.
"Cultuur volk"
Apa yang terjadi dalam fenomena kupiah meuketop itu dikenal sebagai budaya populer di dalam industri massal. Sebenarnya Aceh sudah cukup terlambat jika melihat bagaimana upia karanji dari Gorontalo yang telah populer lebih dulu setelah digunakan Gus Dur dan Sandiaga Uno, atau kupiah jangang khas Banjar yang terbuat dari akar-akar yang terdapat di hutan Kalimantan. Para turis suka sekali dengan bahan alam non-plastik ini. Apa yang dilakukan oleh tokoh elite itu tak lain mengangkat cultuur volk: budaya dari rakyat kebanyakan, dari sendal-sendal kehidupan sosial-ekonomi yang beralas di mana-mana.
Namun berkembangnya kupiah Aceh di tahun resesi akibat Covid-19 patut disyukuri. Kupluk ini tidak lagi dianggap sebagai simbol pakaian kerajaan dan uleebalang, yang dipakai pada momen resmi dan adat, serta sangat selektif dan berbiaya mahal. Kini kopiah itu mampu diproduksi dan dijual dengan harga murah. Rata-rata para reseller menjual dengan harga Rp. 80-90 ribu. Beberapa pusat kerajinan pakaian di Jawa bisa memproduksi lebih murah, sehingga harga jual terpangkas 10-30 persen dari harga produksi di Aceh.
Demikianlah budaya populer ini berkembang dengan pesat karena pola mimicry. Tidak perlu memahami filosofi orang Aceh untuk bisa memproduksi songkok itu. Cukup dengan skill lihat, teliti, replikasi, dan produksi! Bisa saja ada sentuhan inovatif, tapi sebagian besar hidup dari budaya menjiplak. Seperti masyarakat konsumtif di era sekarang, tidak perlu membeli produk apple, iphone, atau Samsung yang mahal dan tidak kompatibel dengan banyak gadget lainnya. Cukup membeli produksi buatan Tiongkok, Taiwan, atau India. Harga lebih bersaing dan terjual semudah kacang rebus di musim hujan.
Tentu dalam sejarah budaya pop, apa yang dilakukan oleh komunitas penyuka kupiah vintage ini tidak seperti kritik budaya populer sebagai budaya massal, yaitu didorong oleh delusi komersialisme yang mengagungkan konsumerisme - seperti diungkapkan oleh sosiolog Dominic Strinati. Ada siasat politik makna yang muncul di situ.
Hal ini berbeda dengan kegemaran para ibu kelas menengah dan sosialita yang larut dalam racun lain budaya pop seperti mengonsumsi tas dan parfum mahal, atau juga kelas menengah laki-laki yang sedang tergila-gila dengan sepeda mahal, plus harga tak masuk akal, yang lepas dari aspek fungsional dan meledak dalam ketahanan belanja rutin. Model budaya pop seperti itu tidak melakukan pertentangan apapun terhadap industri pasar, cenderung terbungkam, ilusif, melemahkan nalar intelektual, dan menjadi pasif (Strinati, 2007 : 17).
Seperti budaya pop yang hadirnya pertama sekali bersinergi dengan seni pop, hadirnya mengkritik segala hal yang dianggap budaya tinggi, klasikal, avant-garde, elitis, dan priyayisme. Perkembangan seni pop yang dimulai di Inggris juga bagian dari mendobrak aristokratisme seni yang dikuasai elite ekonomi dan bangsawan. Budaya pop juga menjadi jalan perlawanan atas budaya elitis yang mengontrol nilai dan asumsi estetis untuk kalangan sangat terbatas dan protokoler itu.
Pop hasanah
Perkembangan kupiah meukeutop ini memberikan penanda baru dalam lingkungan sosial-budaya-religius, paling tidak di Aceh.
Penanda pertama ialah penggunaan pakaian adat yang sering dihubungkan dengan lingkaran kaum adat aristokrat mulai luntur, namun tidak bobot identitas sosialnya semakin mengental. Sebenarnya Serambi Indonesia telah memulai mendekonstruksi posisi kupiah meuketop ini dengan hadirnya sosok Gam Cantoi, tokoh karikatural rekaan Sampe Edward. Dulu hadirnya sosok jenaka ini selalu menarik perhatian pembaca koran ini. Sayang, dengan meninggalnya Sampe Edward, tokoh Gam Cantoi ini pun ikut terkubur. Kupiah meuketop bisa digunakan siapapun sehingga mendekonstruksi makna elitis dan eksklusifnya menjadi volksgeist : semangat kerakyatan yang bisa digunakan baik oleh pegawai honorer hingga rektor.
Penanda kedua ialah identitas kebudayaan yang dihadirkan melalui narasi atau gambar di beragam media melahirkan sifat "kepengarangan baru" (new authorship) tentang narasi dan nilai kepahlawanan. Di tengah tergilingnya kebanggaan atas politik Aceh, yang nyatanya tidak maju-maju, meskipun dilabeli demokrasi lokal khas Aceh, narasi yang dihasilkan oleh kupiah meukeutop ini luar biasa heroik. Banyak netizen yang melihat saya memakai kopiah ini tertarik bukan saja pada aspek fashionnya, tapi juga sejarah sang pengguna. Orang menyebut-nyebut nama Teuku Panglima Polim, Teuku Umar, Sultan Muhammad Daudsyah ketika menggunakan peci ini.
Penanda terakhir ialah pada aspek religiusitas. Pengguna kopiah ini mampu "mendemokratisasi" kesadaran teologis banyak orang di Aceh tentang selubung keislaman yang cenderung monolitik. Sang pengguna kupiah Aceh ikut membuka ruang narasi teologis yang lebih longgar bahwa simbol Islam itu tak musti harus berjubah atau bergamis, keffiyah, bercelana cingkrang yang serba Arabesque.
Berkupiah meuketop lebih khas islami dan etnografis Aceh dibandingkan orang-orang Aceh yang bergaya Arab. Hal ini sebenarnya sudah dicontohkan oleh Gus Dur yang memakai upia karanji, Soekarno yang memakai kopiah pengrajin asal Gresik, atau blangkon HOS Tjokroaminoto. Tentu apa yang mereka gunakan juga tidak asli Indonesia, tapi ada ruang estetika dan sejarah yang membuatnya menjadi Nusantara.
Boleh dikatakan, kupiah meukeutop ini meskipun disebut bagian dari budaya pop, termasuk budaya pop hasanah. Lebih banyak manfaatnya secara sosial-budaya dan ekonomis dibandingkan mudaratnya.