Opini
Kebijakan Pembangunan Aceh dan Realita Implementasi Lapangan
Syariat harus lebih ditunjukkan dalam pembangunan sistem pendidikan yang unggul dan
Kedua konteks lokal yang tidak homogen. Aceh bukanlah monolit. Terdapat keragaman sosio-ekonomi dan kultural yang signifikan antara masyarakat pesisir di Aceh Barat dengan petani di dataran tinggi Gayo, atau masyarakat perkotaan di Banda Aceh dengan pedalaman di Aceh Tenggara.
Sebuah kebijakan seragam tentang, misalnya, pemberdayaan ekonomi syariah, bisa saja tidak aplikatif di semua konteks ini. Pendekatan "one-size-fits-all" tanpa mempertimbangkan karakteristik lokal yang spesifik berisiko menghasilkan penolakan atau implementasi yang hanya di permukaan.
Ketiga kapasitas kelembagaan dan keuangan. Meskipun Aceh menerima Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang besar, kapasitas menyerap dan mengelola dana tersebut kerap menjadi masalah. Isu keterlambatan penyaluran, inefisiensi, dan potensi kebocoran anggaran masih menjadi momok. Kapasitas infrastruktur juga menjadi kendala.
Program e-government atau digitalisasi layanan berbasis syariat, misalnya, akan sulit dijalankan di daerah-daerah dengan jaringan internet yang masih lemah.
Keempat dinamika politik dan kepentingan elit lokal. Panggung politik lokal di Aceh adalah medan tarik-ulur kepentingan yang intens. Syariat Islam, sayangnya, tidak jarang menjadi alat legitimasi politik bagi elit tertentu.
Sebuah kebijakan pembangunan bisa didorong atau dihambat bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan efektivitasnya, tetapi pada seberapa besar ia dapat memberikan "political gain" dan memperkuat basis dukungan.
Tarik-menarik antara kelompok yang lebih menekankan aspek simbol-formalistik dengan kelompok yang ingin mendorong substansi keadilan sosial dalam syariat juga mewarnai dinamika ini.
Aktor-Aktor di Panggung Implementasi Aceh
Wilayatul Hisbah (WH): Sebagai polisi syariat, WH adalah aktor unik dalam drama implementasi di Aceh. Namun, peran mereka seringkali dibatasi pada penegakan aturan yang bersifat hukum dan pidana, sementara peran mereka sebagai "pembina" masyarakat menuju kesejahteraan yang merupakan esensi syariat, masih terbatas.
Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah: Mereka adalah ujung tombak. Budaya birokrasi yang hierarkis dan kurang inovatif sering menjadi penghambat. Motivasi mereka dalam mengimplementasikan kebijakan seringkali lebih didorong oleh perintah atasan daripada pemahaman mendalam tentang filosofi syariat dalam pembangunan.
Kepala Daerah dan DPR Aceh: Political will (kemauan politik) dari gubernur dan bupati/walikota adalah kunci. Jika seorang kepala daerah memiliki komitmen kuat untuk menyelaraskan pembangunan ekonomi dan sosial dengan nilai syariat yang substantif, maka kebijakan akan mendapatkan sumber daya dan perhatian yang memadai.
Ulama dan Cendikia: Sebagai pemegang otoritas moral dan intelektual, peran ulama dan lembaga pendidikan sangat strategis. Mereka seharusnya menjadi penjaga gawang (gatekeeper) yang memastikan implementasi kebijakan tidak menyimpang dari maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Menuju Implementasi yang Bermakna
Untuk mempersempit jarak antara cita-cita syariat dan realita pembangunan, beberapa prinsip perlu dipegang: Pertama reorientasi prioritas: Pemerintah Aceh perlu melakukan reorientasi prioritas dari pendekatan yang terlalu simbolik dan represif menuju pendekatan yang substantif dan membangun.
Syariat harus lebih ditunjukkan dalam pembangunan sistem pendidikan yang unggul dan berkarakter, sistem kesehatan yang terjangkau, pemberantasan korupsi, dan penciptaan lapangan kerja yang halal dan adil.













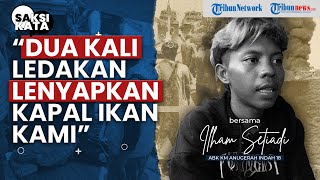





Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.