Opini
Kebijakan Pembangunan Aceh dan Realita Implementasi Lapangan
Syariat harus lebih ditunjukkan dalam pembangunan sistem pendidikan yang unggul dan
Oleh: Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK dan Ketua Dewan Pakar ICMI Orwil Aceh
SETIAP kali wacana pembangunan nasional digaungkan dari Jakarta, Aceh berdiri dengan kekhasannya yang paling mencolok: otonomi khusus yang di dalamnya bersemayam kewenangan untuk menerapkan syariat Islam.
Sejak disahkannya UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan diperkuat dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, provinsi ini telah menempuh jalan pembangunannya sendiri, dengan syariat Islam sebagai pedoman hidup.
Namun, perjalanan dari teks peraturan yang sarat nilai ilahiah menuju realita pembangunan di lapangan menyisakan sebuah pertanyaan besar: sejauh mana kebijakan pembangunan yang berlandaskan syariat ini benar-benar terimplementasi dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat?
Dualisme Kebijakan: Antara Pembangunan Fisik dan Penegakan Identitas
Dalam teorinya, kebijakan pembangunan di Aceh tidak boleh lepas dari nilai-nilai syariat Islam. Ini adalah "jiwa" yang seharusnya menjiwai setiap program, dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pengentasan kemiskinan.
Qanun-qanun (peraturan daerah) yang diterbitkan kerap kali memiliki dua tujuan sekaligus: mencapai target pembangunan fisik sekaligus memperkuat identitas keislaman.
Namun, dalam praktiknya, terjadi ketegangan dan kerap kali pemisahan antara kedua hal ini. Kebijakan pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, dan puskesmas seringkali berjalan dalam logika teknis-administratif yang serupa dengan daerah lain.
Sementara itu, aspek "syariat" lebih banyak diwujudkan dalam kebijakan yang bersifat regulatif dan simbolis, seperti penerapan jam malam bagi wanita non-mahram, kewajiban berbusana muslim, dan operasirazia maksiat.
Ketika Teks Suci Bertemu Realita Sosial-Ekonomi
Implementasi kebijakan pembangunan berbasis syariat di Aceh menghadapi tantangan yang kompleks, yang menyebabkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan.
Pertama kompleksitas birokrasi dan "Salah Urus" prioritas. Rantai birokrasi di Aceh tidak kalah berlikunya. Sebuah kebijakan dari Banda Aceh harus menempuh perjalanan panjang ke kabupaten/kota, lalu ke kecamatan, dan akhirnya ke gampong (desa).
Pada setiap tahap ini, terjadi proses interpretasi. Sumber daya dan perhatian politik seringkali lebih terkonsentrasi pada aspek-aspek syariat yang terlihat (visible), seperti operasi penertiban, karena hasilnya cepat dilihat dan politically rewarding.
Sementara itu, implementasi nilai-nilai syariat dalam pembangunan yang subtantif seperti memerangi korupsi (sebagai bentuk melawan ghulul), menjamin transparansi (amanah), dan memastikan keadilan distributive seringkali terabaikan.
Kapasitas SDM aparatur yang terbatas dan beban administrasi yang tinggi memperparah kondisi ini, membuat mereka fokus pada "mengejar laporan" daripada menyelami esensi kebijakan.
Kedua konteks lokal yang tidak homogen. Aceh bukanlah monolit. Terdapat keragaman sosio-ekonomi dan kultural yang signifikan antara masyarakat pesisir di Aceh Barat dengan petani di dataran tinggi Gayo, atau masyarakat perkotaan di Banda Aceh dengan pedalaman di Aceh Tenggara.
Sebuah kebijakan seragam tentang, misalnya, pemberdayaan ekonomi syariah, bisa saja tidak aplikatif di semua konteks ini. Pendekatan "one-size-fits-all" tanpa mempertimbangkan karakteristik lokal yang spesifik berisiko menghasilkan penolakan atau implementasi yang hanya di permukaan.
Ketiga kapasitas kelembagaan dan keuangan. Meskipun Aceh menerima Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang besar, kapasitas menyerap dan mengelola dana tersebut kerap menjadi masalah. Isu keterlambatan penyaluran, inefisiensi, dan potensi kebocoran anggaran masih menjadi momok. Kapasitas infrastruktur juga menjadi kendala.
Program e-government atau digitalisasi layanan berbasis syariat, misalnya, akan sulit dijalankan di daerah-daerah dengan jaringan internet yang masih lemah.
Keempat dinamika politik dan kepentingan elit lokal. Panggung politik lokal di Aceh adalah medan tarik-ulur kepentingan yang intens. Syariat Islam, sayangnya, tidak jarang menjadi alat legitimasi politik bagi elit tertentu.
Sebuah kebijakan pembangunan bisa didorong atau dihambat bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan efektivitasnya, tetapi pada seberapa besar ia dapat memberikan "political gain" dan memperkuat basis dukungan.
Tarik-menarik antara kelompok yang lebih menekankan aspek simbol-formalistik dengan kelompok yang ingin mendorong substansi keadilan sosial dalam syariat juga mewarnai dinamika ini.
Aktor-Aktor di Panggung Implementasi Aceh
Wilayatul Hisbah (WH): Sebagai polisi syariat, WH adalah aktor unik dalam drama implementasi di Aceh. Namun, peran mereka seringkali dibatasi pada penegakan aturan yang bersifat hukum dan pidana, sementara peran mereka sebagai "pembina" masyarakat menuju kesejahteraan yang merupakan esensi syariat, masih terbatas.
Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah: Mereka adalah ujung tombak. Budaya birokrasi yang hierarkis dan kurang inovatif sering menjadi penghambat. Motivasi mereka dalam mengimplementasikan kebijakan seringkali lebih didorong oleh perintah atasan daripada pemahaman mendalam tentang filosofi syariat dalam pembangunan.
Kepala Daerah dan DPR Aceh: Political will (kemauan politik) dari gubernur dan bupati/walikota adalah kunci. Jika seorang kepala daerah memiliki komitmen kuat untuk menyelaraskan pembangunan ekonomi dan sosial dengan nilai syariat yang substantif, maka kebijakan akan mendapatkan sumber daya dan perhatian yang memadai.
Ulama dan Cendikia: Sebagai pemegang otoritas moral dan intelektual, peran ulama dan lembaga pendidikan sangat strategis. Mereka seharusnya menjadi penjaga gawang (gatekeeper) yang memastikan implementasi kebijakan tidak menyimpang dari maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Menuju Implementasi yang Bermakna
Untuk mempersempit jarak antara cita-cita syariat dan realita pembangunan, beberapa prinsip perlu dipegang: Pertama reorientasi prioritas: Pemerintah Aceh perlu melakukan reorientasi prioritas dari pendekatan yang terlalu simbolik dan represif menuju pendekatan yang substantif dan membangun.
Syariat harus lebih ditunjukkan dalam pembangunan sistem pendidikan yang unggul dan berkarakter, sistem kesehatan yang terjangkau, pemberantasan korupsi, dan penciptaan lapangan kerja yang halal dan adil.
Kedua penguatan kapasitas dan integritas aparatur. Pelatihan bagi aparatur tidak hanya soal teknis administrasi pembangunan, tetapi juga tentang pemahaman filosofi syariat yang rahmatan lil 'alamin dalam konteks pemerintahan. Penguatan nilai integritas (amanah) dan anti-korupsi adalah bagian tak terpisahkan dari penegakan syariat.
Ketiga partisipasi publik yang inklusif. Sosialisasi kebijakan harus berbentuk dialog, bukan monolog. Masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marjinal, harus dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Ini sejalan dengan prinsip syura (musyawarah) dalam Islam.
Keempat sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis outcome: Monev tidak boleh hanya mengejar output, seperti jumlah operasi razia. Tetapi harus fokus pada outcome: apakah kemiskinan berkurang? Apakah angka stunting turun? Apakah keadilan sosial semakin terwujud? Indikator keberhasilan pembangunan berbasis syariat harus diarahkan pada peningkatan kualitas hidup manusia Aceh secara nyata.
Syariat sebagai Jiwa, Bukan Hanya Simbol
Implementasi kebijakan pembangunan di Aceh adalah sebuah ujian besar. Ia menguji apakah syariat Islam mampu menjadi kekuatan transformatif yang tidak hanya mengatur cara berpakaian dan berperilaku, tetapi lebih mendalam lagi, mampu membangun peradaban yang adil, makmur, dan bermartabat. Saat ini, seringkali yang terjadi adalah ketegangan: syariat hadir lebih kuat sebagai identitas simbolik, sementara pembangunan berjalan dalam logika teknisnya sendiri.
Untuk itu, dibutuhkan keberanian para "penerjemah" kebijakan di Aceh mulai dari gubernur hingga kepala gampong untuk tidak hanya paham teks qanun, tetapi juga menghayati jiwa dan tujuan syariat.
Dengan mengedepankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan untuk semua sebagai esensi dari syariat, maka jarak antara ekspektasi mulia di Banda Aceh dan realita yang berdebu di lapangan dapat dipersempit. Hanya dengan demikian, syariat Islam akan benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam, termasuk di tanah Serambi Mekah ini.

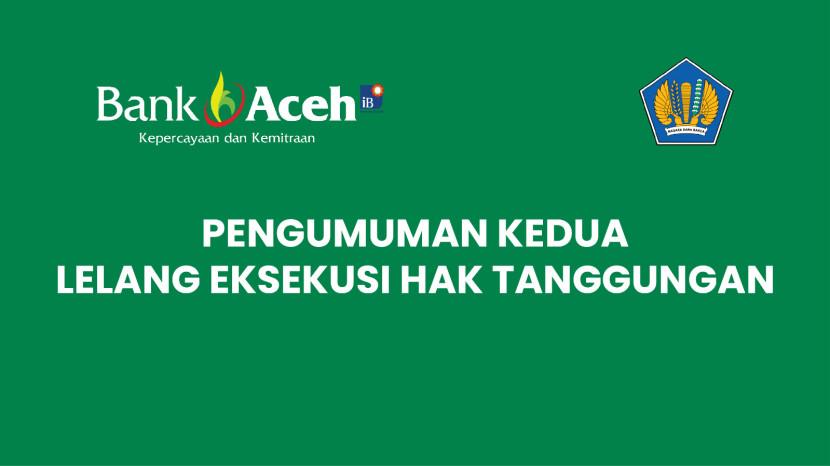













![[FULL] Puja-Puji Trump ke Prabowo, Pakar: Indonesia Ukir Sejarah Jadi Bagian Perdamaian Timur Tengah](https://img.youtube.com/vi/fJn8tji_3J8/mqdefault.jpg)





Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.