Opini
Dayah Manyang, Peradaban Aceh untuk Indonesia
agaimana tidak, ada ide yang diadopsi dari Aceh. Sebaliknya, ada gagasan yang didistorsi atau tepatnya dibatasi, dan ada juga kesepakatan yang belum d
Muhibuddin Hanafiah, Tenaga pengajar pada Prodi PAI FTK UIN Ar-Raniry
SEJAK zaman dahulu, sebelum kemerdekaan hingga kini pasca kesepakatan damai, hubungan Aceh dengan pemerintah pusat tergolong aneh. Bagaimana tidak, ada ide yang diadopsi dari Aceh. Sebaliknya, ada gagasan yang didistorsi atau tepatnya dibatasi, dan ada juga kesepakatan yang belum dipenuhi.
Di antara yang diadopsi sebut saja antara lain adalah cikal bakal wahana transportasi udara nasional, Garuda Indonesia Airways (GIA) yang notabene hasil sumbangan emas masyarakat Aceh. Demikian juga lahirnya Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) yang notabene dari model Badan Perencana Pembangunan Daerah Aceh (Bappeda). Begitu juga hadirnya Ma’had Aly di pesantren, cikal bakalnya adalah Dayah Manyang di Aceh.
Sementara itu di antara yang didistorsi (dikerdilkan) wewenangnya oleh pemerintah pusat, sebut saja bidang-bidang keistimewaan Aceh. Kemudian yang diimingi janji-janji akan tetapi sampai sekarang belum juga dipenuhi, sebut saja otoritas Aceh sebagaimana yang termaktub di dalam UUPA. Kendati demikian, Aceh bagai tak pernah henti berkontribusi untuk Indonesia.
Buktinya sejumlah hasil pemikiran strategis masyarakat Aceh sebagaimana disebutkan di atas diadopsi oleh pemerintah pusat. Ma’had Aly merupakan satu dari sekian banyak cikal-bakal dan gagasan hasil olah pikir masyarakat Aceh yang kemudian diadopsi oleh republik, tulisan ini mencoba mengulas tentang Ma’had Aly.
Pesantren dan dayah
Secara bahasa (Arab), Ma’had Aly adalah lembaga pendidikan tingkat tinggi. Sedangkan yang dimaksudkan dengan Ma’had Aly dalam tulisan ini adalah lembaga pendidikan tinggi (setara universitas) yang berada dalam sistem pendidikan pesantren di Indonesia dewasa ini. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam sebuah lingkungan pesantren yang besar dan telah eksis dalam jangka waktu yang lama, di sana terdapat jenjang pendidikan yang relatif lengkap, yaitu mulai dari jenjang Ula (Ibtidaiyah), Wustha (Tsanawiyah), ‘Ulya (‘Aliyah) dan Ma’had Aly (perguruan tinggi).
Nah, Ma’had Aly berarti perguruan tingginya pesantren atau jenjang pendidikan tertinggi di pesantren. Berbeda dengan sebagian pesantren yang lain, di sini terkadang hanya menerima calon santri yang telah lulus dari pendidikan dasar, dan bahkan hanya diterima lulusan pendidikan menengah. Hal ini sangat tergantung jenjang pendidikan yang dibuka pada sebuah pesantren.
Konon lagi sebelum pesantren menganut sistem pendidikan semi formal sebagai adopsian sistem pendidikan formal, maka saat itu santri pesantren belum diklasifikasi dalam format jenjang ataupun kelas, tetapi lebih pada tingkatan kemampuan dalam menguasai materi atau kitab-kitab tertentu yang telah menjadi pendidikan utama di pesantren.
Di Aceh, penyelenggaraan pendidikan dayah lebih diperuntukkan sebagai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dayah lebih identik dengan lembaga pendidikan orang dewasa atau minimal remaja akhir. Sebab, dalam lingkup pendidikan dalam masyarakat Aceh terdapat sejumlah lembaga pendidikan pra-dayah yang harus dilalui dan dikuasai ilmu pengetahuannya oleh seorang calon santri dayah.
Sebelum diantar ke dayah, anak-anak di Aceh terlebih dahulu telah belajar agama di rumahnya sendiri atau rumah seorang guru (teungku), kemudian melanjutkan pendidikan ke meunasah, kemudian ke level rangkang (balai pengajian khusus). Dan pada masing-masing institusi ini memiliki kurikulum inti tersendiri dengan jenjangnya yang teratur. Jadi sebelum mengecap pendidikan dayah, calon santri telah menguasai ilmu dasar keagamaan seperti telah dapat membaca Alquran dengan benar, telah mengetahui ketentuan-ketentuan peribadatan (fiqh), telah memahami konsep dasar ketuhanan (aqidah), dan telah mahir beberapa praktik ibadah serta telah diajarkan etika interaksi sosial serta telah terbiasa mengamalkan sikap dan perilaku terpuji tersebut.
Tidak sampai di sini saja, pendidikan pra-dayah bukan hanya membekali calon santri luas dan mahir dalam mendalami ilmu agama. Namun yang paling penting lagi adalah calon santri telah melewati tempaan mental dan spiritual yang memadai selama proses belajar pra-dayah berlangsung. Akibatnya, sesampai di dayah mereka telah benar-benar siap beradaptasi dengan sistem dan lingkungan pendidikan dayah yang unik dan dinamis.
Mencermati gambaran pendidikan pra-dayah di atas, terdapat sejumlah perbedaan yang signifikan antara sistem pendidikan pesantren (dominan di pulau Jawa) dengan sistem pendidikan dayah di Aceh. Paling tidak keunikan sistem pendidikan dayah dapat dicermati pada layanan jenjang pendidikan yang dibuka dan persyaratan tidak tertulis mengenai kualifikasi calon santri yang sudah dinyatakan layak untuk mulai belajar di dayah.
Dikarenakan tidak menganut sistem pendidikan berjenjang ataupun kelas, pendidikan dayah tidak terlalu memperhatikan perihal usia calon santri ataupun tamatan lembaga pendidikan tertentu. Masalah administrasi atau dokumen berbasis data yang tercatat dan tersusun rapi pada beberapa dasawarsa terdahulu belum mulai dikenal dan dipedulikan oleh pengelola dayah.
Fenomena ini sudah berbeda disaat sekarang, dimana sejumlah dayah yang sudah merintis komunikasi (berhubungan) dengan pemerintah atau di Aceh ada Dinas Pendidikan Dayah sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Aceh terhadap pendidikan khas Aceh ini. Maka satu per satu, suka atau tidak suka, wajib memperhatikan masalah administrasi dalam mengelola dayah. Mulai dari administrasi lembaga dayah (legalitas), personalia pengurus, tenaga pendidik, pertanggungjawaban keuangan, administrasi karyawan dan bahkan administrasi para santri.
Dayah Manyang
Sejarah kesarjanaan (intelektual) dayah di Aceh telah tercatat bahwa level tertinggi pendidikan di dayah disebut dengan “dayah manyang” atau “rangkang manyang” yang berbeda dengan konsep Ma’had Aly sekarang ini. Konsep Dayah Manyang dalam sistem pendidikan dayah tradisional di Aceh adalah pendidikan dayah setelah selesai belajar di jenjang pendidikan dayah paling tinggi atau setara dengan kelas tujuh atau selevel jami’ah (universitas).
Saat itu pengaturan sistem kelas tidak berdasarkan tahun ajaran, namun lebih pada kemampuan memahami kitab (kurikulum) yang ditentukan pada masing-masing jenjang kelas. Seorang santri dayah bisa menghabiskan waktunya belasan tahun di jenjang pendidikan dayah sampai ke Dayah Manyang. Jadi kelulusan pada suatu jenjang kelas dan untuk bisa berada pada jenjang kelas berikutnya sangat ditentukan pada keberhasilan memahami sejumlah referensi kitab pada jenjang kelas tersebut.
Tolak ukur kemampuan memahami kitab-kitab dimaksud dilakukan melalui ujian lisan di hadapan seorang pengajar (teungku). Uniknya lagi tidak semua dayah di Aceh memiliki jenjang pendidikan Dayah Manyang.
Waktu itu, Dayah Manyang hanya ada pada beberapa dayah besar saja, seperti Dayah Teungku Chiek Pante Geulima, Dayah Teungku Chiek di Cot Kala, Dayah Teungku Chiek Pante Kulu, Dayah Teungku Chiek di Tiro, Dayah Teungku Chiek Meunasah Meucap, Dayah Teungku Chiek di Pasi, Dayah Teungku Chiek Treung Campli dan beberapa lainnya. Keberadaan kelas Dayah Manyang pada sejumlah dayah ini mengantarkan kualitas mendunia kemajuan pendidikan dayah pada masa itu.
Kesejagatan kualitas pendidikan dayah di Aceh tempoe doeloe telah ditulis oleh Qismullah Yusuf dalam kajiannya dari tahun 1965 sampai sekarang, ketika mengkaji biografi 14 ulama, ilmuan dan teknokrat Aceh yang berkarya dan mengimplementasikan ilmu dan teknologinya dari awal tahun 1600-an sampai tahun 1900-an.
Qismullah Yusuf menyatakan bahwa Dayah Manyang telah lahir di Aceh sejak Tuengku Chiek di Pasi kembali dari Hijaz, Baghdad, Damaskus dan Mesir dan mendirikan Dayah Manyang pertamanya di Aceh yang terletak di Keumala sambil membangun irigasi modern pertama di Aceh di awal tahun 1600-an. Tgk Chik di Pasi dengan nama aslinya Tgk Abdussalam telah membangun Dayah Manyang di Waido sebagai pusat pendidikan agama Islam bagi masyarakat sekitar.
Adapun materi pembelajaran yang diajarkan pada Dayah Manyang ketika itu adalah mencakup bidang fiqih, mantiq, tasawuf, Bahasa Arab, ilmu hadits, syair dan ilmu perairan. Irigasi pertama yang dibangun oleh Tgk Chik Dipasi ini adalah irigasi Tiro yang dimulai dari Tiro sampai ke Keumala. Kurikulum Dayah Manyang saat itu terdiri atas mata pelajaran agama dan kemahiran hidup (vocational) dengan berbagai bidang studinya.
Bersamaan dengan beroperasinya irigasi modern pertama di Sumatera ini, beliau mendidik para santrinya tidak hanya ilmu agama, akan tetapi juga ilmu-ilmu sains dan teknologi yang akan membantu para santrinya memfungsikan diri mereka dalam masyarakat.
Berselang antara lima belas sampai dua puluh tahun kemudian, Tgk Chik di Reubee (suami mak ceknya Sultan Iskandar Muda), yang membantu Tgk Chik Dipasi dalam mengerahkan tenaga rakyat untuk membangun irigasi pertama dari Tiro ke Keumala, membangun irigasi kedua yang dimulai dari Keumala sampai ke Garot. Bersamaan dengan proyek irigasi kedua ini, Tgk Chik di Reubee membangun dayah manyangnya di Reubee dan Delima.
Setelah itu beliau belajar di Mekkah dan mendirikan sebuah dayah manyang di Reubee, Pidie. Berdasarkan catatan ini memberikan informasi bahwa pendidikan Islam di Aceh yang digerakkan oleh ulama-ulama besar melalui lembaga dayah (Dayah Manyang) telah berpikir dengan sangat maju sehingga lahir dayah-dayah vokasional sejak abad XV dan XVI M. Sebagai sebuah universitas di dayah, Dayah Manyang memiliki kualifikasi tersendiri.
Kualifikasi itu antara lain memiliki seorang ulama senior yang bernama Teungku Chiek. Seorang Teungku Chiek lazimnya merupakan alumni pendidikan luar negeri seperti dari Timur Tengah (Makkah, Madinah, Kairo atau pusat-pusat universitas Islam level dunia lainnya).
Ma’had Aly
Fenomena pendidikan dayah tempoe doeloe di Aceh relatif berbeda dengan sistem pendidikan beberapa dayah tradisional kekinian, dimana jenjang kelas telah bergeser kepada sistem kelas berdasarkan tahun ajaran (dua semester/kelas per tahun). Perubahan sistem pendidikan dayah tradisional menjadi semi-modern dapat dicermati pada salah satu dayah seperti MUDI Mesra Samalanga.
Dimana dayah MUDI menerima calon santri baru mulai jenjang mu’adalah Aliyah (3 tahun/6 semester) atau jenjang salafiyah 3 tahun (setara dengan aliyah). Mu’adalah Aliyah adalah setara dengan pendidikan pada Madrasah Aliyah (MA) pada sistem pendidikan formal dengan masa studi 3 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan Mu’adalah Aliyah, maka santri yang berprestasi memperoleh pilihan untuk melanjutkan studi pada Ma’had Aly yang berijazah setara dengan pendidikan sarjana S1 yang telah diakui oleh pemerintah.
Sedangkan bagi yang tidak melanjutkan pada jenjang Ma’had Aly akan melanjutkan pendidikan pada jenjang salafiyah (kelas 4) dan ketika tamat dan lulus (setelah belajar selama 3 tahun) santri berhak memperoleh ijazah dayah. Dengan demikian total waktu yang harus dilewati seorang santri untuk menamatkan studi adalah selama 6 tahun pada sistem pendidikan salafiyah dan 7 tahun bagi yang melanjutkan pendidikan ke Ma’had Aly. Durasi waktu yang harus dilalui oleh seorang mahasantri di jenjang pendidikan setara sarjana (Marhalatul Ula) pada Ma’had Aly adalah selama 4 tahun atau 8 semester.
Di balik perbedaan antara Dayah Manyang dan Ma’had Aly dalam sistem pendidikan dayah tradisional kekinian masih ditemukan sisi kemiripannya, yaitu pada kurikulum tambahan. Pada Ma’had Aly selain mempelajari kurikulum inti atau utama para mahasantri juga mulai mendapatkan pelajaran pendukung atau disebut ekstrakurikuler seperti keterampilan berbahasa asing (bahasa Arab dan Inggris), hafalan Alquran, mempelajari metode berdakwah dan muhadharah, latihan seni (suara dan lukis), latihan menulis (jurnalistik), kursus menjahit, budidaya tanaman, praktik ekonomi mikro (interpreuner), dan praktik lapangan dengan mengajar di dayah cabang dan TPQ terdekat dengan lingkungan dayah.
Pembelajaran tambahan ini agak mendekati dengan apa yang pernah diberlakukan pada pendidikan Dayah Manyang pada masa dahulu. Dimana seorang Teungku Chiek yang memimpin Dayah Manyang memperkenalkan kepada mahasantrinya pelbagai keterampilan hidup (vocasional), sehingga Dayah Manyang pada saat itu layak disebut sebagai dayah vokasional.
Namun demikian, Ma’had Aly di Aceh hari ini masih belum sampai pada kaliber Dayah Manyang di masa lalu. Ketika itu Teungku Chiek mampu berkontribusi secara lebih nyata kepada masyarakat sekitar dengan membangun sistem irigasi, mencetak sawah baru dan perkebunan lada, tembakau dan kelapa, membuat tambak ikan.
Semua kreasi para ulama dayah di masa dahulu ini berhasil digerakkan karena terjalin kerja sama yang cukup erat dengan masyarakat. Artinya institusi dayah ketika itu tidak eklusif atau tidak elitis serta menjaga jarak dengan masyarakat. Bagaimana dengan model dayah kita sekarang, kita bisa menilainya sendiri.








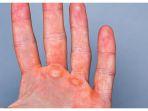






![[FULL] Sengketa Ambalat Malaysia vs RI, Pakar: TNI Tak Boleh Lengah, Jangan Senasib Sipadan Ligitan](https://img.youtube.com/vi/YcKqjph-Pqs/mqdefault.jpg)





Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.