Kupi Beungoh
Visi Aceh Berkelanjutan Tidaklah Sederhana
Sepertinya slogan “Aceh Islami, maju, bermartabat, dan berkelanjutan” terdengar visioner dalam rapat RPJM.
Oleh: Akhsanul Khalis
Salah satu desa di Aceh Timur, aktivitas warganya seketika berubah jadi mimpi buruk.
Bau menyengat menembus rumah-rumah, anak-anak dan orang tua tiba-tiba sesak, muntah, lalu mengungsi ke kantor camat. Warga menduga sumbernya dari sumur minyak perusahaan yang beroperasi tak jauh dari pemukiman.
Di Pidie, kebun ditinggalkan karena gajah liar merusak pisang, cokelat, kopi, hingga padi hutan yang menyempit memaksa satwa keluar, bahkan menelan korban jiwa.
Di daerah lain, sungai keruh tercemar tambang emas ilegal, bantaran terkikis banjir, hutan digunduli atas nama ekonomi rakyat.Data resmi menunjukkan: dalam dua dekade terakhir Aceh kehilangan hampir 700 ribu hektare hutan; konflik gajah dengan manusia mencapai 535 kasus; sejumlah DAS dinyatakan rusak akibat abrasi dan tercemar merkuri.
Potret buram ini menampar wajah cita-cita pembangunan berkelanjutan. Sepertinya slogan “Aceh Islami, maju, bermartabat, dan berkelanjutan” terdengar visioner dalam rapat RPJM. Namun di lapangan yang nyata justru masyarakat teralienasi (terasing), kehilangan ruang hidup akibat kian rapuhnya ekologis.
Baca juga: Menyelamatkan Generasi dari Ancaman Kehamilan Remaja
Menyederhanakan realitas
Masalahnya bukan pada ketiadaan rencana. Hampir setiap pejabat bisa mengutip program ekonomi hijau dengan fasih. Tetapi rencana yang indah itu kandas dalam labirin birokrasi.
Implementasi tersandera prosedur. Dokumen harus lengkap, tanda tangan harus berjenjang, laporan harus rapi dan teratur. Dampak siklus birokrasi yang rigid itu, alhasil semua program kemudian disederhanakan.
Disinilah Tania Li, antropolog Kanada yang dua puluh tahun meneliti model pembangunan Indonesia, menjadi sangat relevan. Ia menyebutkan konsep rendering dalam bukunya The Will to Improve: negara hadir dengan niat memperbaiki, tetapi dalam praktiknya, realitas yang kompleks disederhanakan menjadi persoalan teknis.
Rendering membuat masalah nyata terlihat rapi di atas kertas, tetapi kosong di lapangan.
Tambang menjadi potret paling jelas dari kontradiksi kebijakan pembangunan. Pemerintah kerap menyederhanakan kompleksitas persoalan dengan dalih membuka lapangan kerja. Izin eksploitasi diberikan begitu saja, tanpa kalkulasi jangka panjang.
Akibatnya, air tercemar, tanah kehilangan kesuburan, dan udara dipenuhi debu. Masyarakat di sekitar tambang justru menanggung risiko kesehatan dan lingkungan yang tidak pernah masuk dalam neraca keuntungan perusahaan (eksternalitas negatif).
Akhirnya Kapitalisme bekerja dengan sempurna: keuntungan dimonopoli oleh segelintir modal, sementara kerugian ditanggung jawabkan ke publik.
Ironisnya, situasi tidak jauh berbeda dalam praktik tambang rakyat. Meski lebih kecil skalanya, kehidupan pekerja tambang tetap pas-pasan.
Mereka bergantung pada tengkulak, bekerja keras di lubang-lubang sempit, namun penghasilan yang diperoleh jauh dari kata sejahtera. Artinya, baik dalam tambang industri besar maupun tambang rakyat, janji peningkatan kesejahteraan selalu meleset dari kenyataan.
Pola itu berulang dalam berbagai sektor. Ada program desa iklim, proyek konservasi, penanggulangan banjir, swasembada pangan, hingga penghijauan perkotaan.
Di atas kertas, semua tampak rapi dan menjanjikan. Program itu kemudian direduksi menjadi kelengkapan administrasi dan regulasi.
Mencegah deforestasi dianggap bisa selesai dengan sosialisasi;aksi simbolis tanam pohon, pelatihan teknis, konflik antara manusia dan satwa liar disederhanakan hanya sebagai soal mitigasi, dan kerusakan ekosistem dibungkus dengan jargon rehabilitasi.
Masyarakat jarang diajak bicara sebelum tanah mereka ditambang, hutan dan lahan di belakang rumah dijarah dialihfungsikan demi konsesi. Suara warga tenggelam dalam derap administrasi yang serba top down. Pembangunan hadir sebagai monolog dari atas, bukan dialog dengan masyarakat akar rumput.
Mencermati Kompleksitas
Disinilah masalahnya. Pemimpin di Aceh rata-rata sering merasa tak perlu terlalu repot dengan konseptual atau pun segudang teori, seolah-olah Mereka percaya, turun langsung, melihat dengan mata kepala, lalu memutuskan.
Justru persoalan lingkungan hari ini tak sesederhana itu. Selama ini dibalik kata “keberlanjutan” ada relasi kuasa yang tidak pernah dibicarakan: ada modal yang menggerakkan, siapa yang menentukan arah pembangunan, menikmati hasil, dan siapa menanggung akibat.
Sudah menjadi rahasia publik, visi keberlanjutan akan selamanya terpenjara dalam bahasa teknokratik dan logika investasi pemilik modal. Elinor Ostrom, pakar studi lingkungan dan politik, pernah mengingatkan kita dalam buku utamanya, Governing the Commons (1990), tata kelola sumber daya alam tidak harus tunggal.
Ia menawarkan gagasan polycentric governance tata kelola multi-pusat yang memberi ruang bagi aturan lokal, partisipasi komunitas, dan mekanisme kolaborasi. Pesannya sederhana: jangan biarkan negara atau pasar menjadi satu-satunya pengatur. Libatkan masyarakat, adat, dan komunitas lokal untuk merawat hutan, sungai, dan ruang hidupnya sendiri.
Dari sini, kita belajar bahwa keberlanjutan tidak bisa didekretkan dari kantor meja birokrasi kepala daerah, namun tumbuh dari proses belajar kolektif.
Konflik manusia–gajah, misalnya, tidak akan selesai hanya dengan patroli aparat justru membutuhkan ruang dialog di mana petani, akademisi, dan aparat duduk bersama, mengelaborasikan pengetahuan modern dengan kearifan lokal.
Hal yang sama berlaku di sektor tambang. Perubahan dimulai dari audit menyeluruh atas perizinan. Bukan hanya menghentikan izin baru, tapi juga meninjau ulang izin lama yang menyalahi daya dukung lingkungan. Ukurannya jelas: hutan pulih, sungai bebas logam berat.
Transparansi harus menjadi fondasi. Instrumen seperti KLHS dan AMDAL tidak cukup bila berhenti di meja teknokrat: copy paste dari kajian sebelumnya. Data izin dan dampaknya harus dibuka, diawasi publik. Dengan begitu, warga bukan lagi penonton, melainkan pengawas aktif.
Insentif pun perlu diarahkan dengan cara baru. Skema kompensasi berbasis hasil bisa menjadi pintu masuk: desa yang menjaga hutan seharusnya mendapat manfaat nyata. Ketika menjaga alam menghadirkan pendapatan, bukan sekadar beban moral, maka keberlanjutan berubah menjadi logika ekonomi yang rasional.
Ruang partisipasi juga harus diperluas. Musrenbang jangan lagi menjadi ritual tahunan yang seremonial, harus hidup sebagai forum ekologis, tempat suara warga benar-benar menentukan arah pembangunan. Prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan—layak dijadikan syarat mutlak bagi setiap proyek.
Terakhir, arah belanja publik harus bergeser. Masa depan menuntut investasi di agroforestri, ekowisata berbasis komunitas, serta rehabilitasi daerah aliran sungai. Dampaknya bisa dilihat dari jumlah tenaga kerja non-tambang yang tercipta, dari peningkatan pendapatan rumah tangga desa.
Point of view nya adalah visi keberlanjutan butuh perjalanan panjang. Punya konseptual, jangka waktu, tahap demi tahap, bukan proyek singkat, serta menuntut konsistensi, keberanian, partisipasi kolektif untuk merombak cara kita mengelola lingkungan hidup.
Tidak selesai dalam satu periode kekuasaan. Pakar seperti Ostrom sudah memberi jalan: berbagi kuasa, membangun kolaborasi, dan memberi makna ekonomi pada konservasi. Sisanya, tergantung apakah kita mau berjalan kedepan atau terus berputar dalam lingkaran lama yang kita tahu arahnya selalu menuju krisis.
*) PENULIS adalah Direktur Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Lembaga ESGE Study Center Email: Akhsanfuqara@gmail.com
KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Isi artikel menjadi tanggung jawab penulis.
Baca artikel KUPI BEUNGOH lainnya di SINI
| World Rabies Day: Pengingat Bahaya Penyakit Anjing Gila |

|
|---|
| Mencermati Karya Bakti TNI di Masjid Indrapuri: Menyentuh Sejarah Aceh Sebelum Aceh |

|
|---|
| Tanpa Badan Khusus, Perpanjangan Otsus Aceh Hanya Buang-Buang Dana |

|
|---|
| Dilema Makan Bergizi Gratis |

|
|---|
| Dari APBD ke Pasar Modal: Mengapa Pemerintah Daerah Harus Berani Menerbitkan Obligasi/Sukuk Daerah |

|
|---|



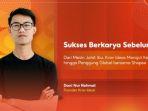





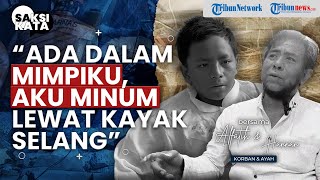




Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.