Opini
Rohingya, Korban Sejarah?
PEMBERITAAN kasus Rohingya muncul diberbagai media. Bahkan, Komisi I DPR RI mendesak Presiden SBY untuk segera membebaskan
PEMBERITAAN kasus Rohingya muncul diberbagai media. Bahkan, Komisi I DPR RI mendesak Presiden SBY untuk segera membebaskan dan memberikan suaka politik terhadap pengungsi etnis muslim Rohingya di Indonesia (Serambi, 26 Juli 2012). Ada apa dengan etnik Rohingya di Myanmar?
Dalam beberapa tahun terakhir, perlakuan kejam, brutal, minoritas dan diskriminatif dialami oleh etnis Rohingya. Kondisi kehidupan mereka benar-benar sangat memprihatinkan. Kekerasan kemanusiaan yang dilakukan oleh etnis lain dan Pemerintah Myanmar benar-benar sudah keterlaluan. Karenanya, banyak warga Rohingya yang terpaksa migrasi keluar dari negerinya untuk menyelamatkan diri.
Etnik Rohingya berbeda dengan etnik-etnik lain yang mendiami wilayah Myanmar. Mereka berkulit gelap (kaum Benggali) dan mayoritas beragama Islam. Sedangkan etnik-etnik lain berkulit kuning langsat dan menganut agama Buddha Therravada. Etnik Rohingya mendiami wilayah Arakan, di bagian Barat dan Utara Myanmar. Mereka merupakan suku asli yang mendiami wilayah tersebut sejak abad ke 8 Masehi. Dulu daerah tersebut merupakan wilayah Kerajaan Arakan yang muslim. Namun pada abad ke-17 Masehi, bangsa Burma menginvasi wilayah tersebut dan mengeksekusi ribuan penduduk Arakan sehingga etnis Rohingya yang tersisa menjadi minim. Saat itu banyak warga Rohingya yang melarikan diri meninggalkan wilayah Arakan.
Kedatangan Inggris
Kedatangan tentara British yang bermaksud menduduki Burma, menimbulkan harapan bagi etnik Rohingya yang tersisa. Sehingga, kaum Rohingya yang dulunya melarikan diri saat invasi bangsa Burma, kembali pulang ke kampung halamannya. Penjajah British mendatangkan imigran Benggali dari wilayah Chittagong yang berbatasan langsung dengan Myanmar bagian barat untuk bekerja sebagai pekerja pertanian dan perkebunan di wilayah Arakan yang subur.
Kebijakan British tersebut memberikan dampak besar kepada populasi bangsa Benggali dan kaum Rohingya di Myanmar yang menjadikan mereka sebagai kaum mayoritas di beberapa kota besar seperti Rangoon (Yangoon), Akyab (Sittwe), Bassein (Pathein), dan Moulmein. Pada masa itu, kaum Burma di bawah penguasaan Inggris merasa tidak berdaya terhadap imigrasi besar-besaran tersebut dan hanya dapat merespons dengan sentimen rasial antara superioritas dan ketakutan.
Keadaan menjadi sulit ketika perang dunia kedua. Inggris yang berusaha mempertahankan eksistensinya di Burma menggunakan pejuang-pejuang Rohingya dan kaum imigran Benggali untuk melawan Jepang dan kaum nasionalis Burma. Namun, pada akhirnya Burma mampu meraih kemerdekaannya pada 1948. Sejak saat itulah konflik dan penderitaan etnik Rohingya kembali terjadi lagi. Terlebih lagi, kebijakan pemerintahan saat itu yang menginginkan populasi yang homogen, yaitu ras indocina yang bewarna kulit sama dan menganut agama yang sama.
Akibat sentimen masa lalu maka kaum Rohingya dimarjinalkan, didiskriminasikan, dan dizalimi. Bahkan, Pemerintah Myanmar tidak memberikan kewarganegaraan kepada warga etnik Rohingya (stateless person), sehingga dapat dikatakan mereka tidak memiliki hak sebagai manusia yang dilindungi oleh negara. Bukan hanya secara legalitas diabaikan, kaum Rohingya juga tidak memiliki hubungan social yang baik dengan etnik-etnik yang lain di Myanmar. Karenanya, seringkali timbul konflik komunal yang berujung pada tindakan-tindakan kejahatan brutal dan tidak berperikemanusiaan.
Sentimen kebangsaan
Konflik yang terjadi antara kaum minoritas Rohingya dengan etnik-etnik lain serta Pemerintah Myanmar merupakan kelanjutan dari sentimen kebangsaan yang berakar dari sejarah kelam mereka. Sehingga, pertikaiannya bukan hanya karena perbedaan warna kulit, bahasa dan kepercayaan semata, namun berasal dari kompleksitas permasalahan yang tidak bisa dengan mudah diselesaikan begitu saja.
Dari perspektif historis, permasalahan Rohingya memiliki persamaan dengan kasus genocide di Rwanda pada tahun 1994. Belgia yang menjajah Rwanda sebelum kemerdekaannya menerapkan kebijakan sistem pemisahan penduduk terhadap dua kaum yang mendiami negeri tersebut: yaitu kaum Hutu dan kaum Tutsi. Kaum Hutu merupakan bangsa asli Rwanda namun memiliki strata sosial lebih rendah. Sedangkan kaum Tutsi merupakan pendatang dari Afrika Timur, memiliki strata social yang lebih tinggi dan menguasai hampir 90% perekonomian Rwanda. Kebijakan pemisahan ini pada akhirnya menimbulkan sentiment akut disertai pembantaian (Genocide) yang dilakukan oleh kaum Hutu terhadap kaum Tutsi. Kaum Hutu bermaksud menguasai Rwanda dari pengaruh kaum Tutsi.
Perbedaan kasus Rwanda dan Myanmar adalah Pemerintah Belgia di Rwanda dengan sengaja menciptakan sistem pemisahan penduduk terhadap kaum pribumi sehingga akan mudah bagi pemerintah jajahan untuk mengatur dan mengelola tanah jajahannya. Sedangkan yang terjadi di Myanmar adalah British meninggalkan Myanmar setelah perang dunia kedua dengan terpaksa melepaskan beberapa tanah jajahannya kepada kaum nationalis tanpa memberikan legalitas perlindungan kepada kaum Rohingya yang banyak membantu British pada perang dunia kedua. Hal ini semakin memberi konstribusi yang besar terhadap krisis kemanusiaan kaum Rohingya hingga sekarang ini.
Permasalahan Rohingya sedemikian kompleks, sehingga pemecahannya bagaikan mengurai benang kusut yang sulit dicari titik pangkalnya. Demokratisasi yang mulai dilakukan junta militer tahun 2010, berhasil membuka tabir tentang keadaan yang sebenarnya terjadi di Myanmar kepada dunia luar. Isu-isu berkaitan HAM Rohingya baru akhir-akhir ini diketahui oleh masyarakat internasional setelah maraknya pemberitaan mengenai kondisi kamp-kamp pengungsian Rohingya yang memprihatinkan di perbatasan Bangladesh dan Thailand.
‘Trending topics’
Adanya boat people (manusia perahu) kaum Rohingya yang melintasi perairan Indonesia dan Malaysia juga menjadi trending topics, akhir-akhir ini yang menjadikan isu Rohingya semakin menginternasional. Namun sayangnya, pada saat pembebasan pejuang HAM Myanmar Aung Saan Suu Kyi dan kedatangan Menlu AS, Hillary Clinton tahun lalu, ternyata tidak menjadikan kasus Rohingya sebagai agenda demokratisasi Myanmar. Walaupun begitu, hemat saya kemajuan signifikan telah dicapai setelah beberapa negara dan forum internasional seperti ASEAN mengangkat isu-isu kaum Rohingya sehingga menarik perhatian publik terhadap krisis kemanusiaan yang tengah terjadi sekarang ini.
Idealnya, pemecahan masalah Rohingya harus pula menjadi fokus perhatian Pemerintah SBY dalam merespons isu-isu internasional. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, “maka dibentuklah Pemerintah Negara Indonesia yang ... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Dengan demikian, membantu Rohingya merupakan kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah RI.
* Danil Akbar Taqwaddin, Lulusan International Affair, University Utara Malaysia.







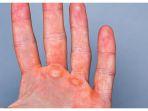

![[FULL] Sengketa Ambalat Malaysia vs RI, Pakar: TNI Tak Boleh Lengah, Jangan Senasib Sipadan Ligitan](https://img.youtube.com/vi/YcKqjph-Pqs/mqdefault.jpg)




