Opini
Kekerasan dan Partisipasi Politik
MESKIPUN hanya terjadi di beberapa kabupaten/kota di Aceh, namun kekerasan politik tampaknya telah berhasil mengirimkan
Oleh Saifuddin Bantasyam
MESKIPUN hanya terjadi di beberapa kabupaten/kota di Aceh, namun kekerasan politik tampaknya telah berhasil mengirimkan pesan yang menakutkan kepada banyak orang. Mungkin memang ada prinsip wait and see (tunggu dan lihat), namun media massa melaporkan bahwa pada hari pertama kampanye di Aceh, banyak jadwal kampanye yang sudah disusun oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) tak dimanfaatkan oleh ke-15 parpol peserta pemilu. Ada pun terhadap kampanye yang dapat dilangsungkan, meskipun disebut sebagai kampanye akbar, ternyata tak terlalu diminati oleh warga masyarakat.
Tentu ada banyak sebab bahwa kampanye hari pertama gagal dilaksanakan, atau dapat dilaksanakan namun tak banyak yang membuat masyarakat tertarik untuk menghadirinya. Sebab-sebab itu misalnya parpol tidak siap dalam hal pendanaan atau logistik, atau tak memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk menangani kegiatan kampanye. Di pihak lain, masyarakat bisa saja sudah jenuh atau memiliki agenda lain yang lebih penting, sehingga memutuskan untuk tidak menghadiri perhelatan politik di ruang terbuka itu. Sikap skeptis parpol dan masyarakat telah bertemu pada muara yang sama.
Namun, beberapa tulisan yang ada, menyajikan eratnya kaitan antara kekerasan dengan partisipasi politik warga masyarakat. Hal ini khususnya ditemukan di negara semisal Afrika Selatan, Zimbabwe, Uganda, Angola, dan beberapa negara lainnya. Karena itu tidak bisa pula dipungkiri kemungkinan-kemungkinan, dalam kasus Aceh, bahwa parpol-parpol atau para calon anggota legislatif (juga warga masyarakat) merasa takut untuk muncul secara terbuka di depan publik, tersebabkan adanya kekerasan-kekerasan politik selama dua-tiga bulan belakangan ini.
Seorang pengurus partai sekaligus caleg mengirimkan SMS, bertanya: “Apakah saya sebaiknya meneruskan kegiatan politik saya, kampanye, dengan kondisi di lapangan seperti sekarang ini?” Di lapangan tenis, beberapa pemain yang berusia 50-an bertanya: “Apakah mungkin pemilu di Aceh dilaksanakan jika kekerasan terus terjadi?” Seorang kepala desa mengatakan: “Situasi sekarang mencekam, seperti saat konflik dulu.” Juga, beberapa partai memutuskan memboikot parade pemilu damai, karena ada berbagai pelanggaran yang terjadi sebelumnya, yang belum diselesaikan secara tuntas: “Untuk apa deklarasi damai itu jika di lapangan terjadi sebaliknya?” atau “menghadiri kampanye? Nggak ah, takut.”
Perasaan khawatir
SMS semacam di atas, dan pertanyaan dan kekhawatiran itu, dapat diperlakukan sebagai sebuah refleksi atas perasaan khawatir, gugup, takut, menghadapi situasi yang di lapangan itu. Kini bahkan jika pun ada kekerasan dengan korbannya adalah politisi dengan motif yang tak ada kaitannya sama sekali dengan politik, kelihatannya masyarakat tetap melihat itu sebagai kekerasan bermotif politik. Dengan kata lain, ada keadaan (kondisi psikologis) yang meresahkan di lapangan. Muncul pula sikap tak terpercaya, sesungguhnya yang dilihat adalah B, dan jelas-jelas B, namun disebut sebagai A, dan dipercaya bahwa itu adalah A. Akal sehat mulai tergerus.
Produksi kekerasan politik itu, dengan kata lain, telah berhasil mengirimkan teror kepada berbagai kalangan. Tak ada satu pun yang bisa menjawab siapa dan ada apa di balik semua ini. Sekarang hanya dapat dijelaskan bahwa teror atau kekerasan itu muncul dalam teorinya yang paling klasik; ketika ada peluang atau kesempatan, maka disanalah kejahatan bermula. Keadaan menjadi tak jelas, siapa melakukan apa dan mengapa.
Terjadinya berbagai bentuk kekerasan politik, baik pada masa pileg maupun pilkada, merupakan sebuah langkah mundur dalam kehidupan berdemokrasi. Langkah mundur ini berimplikasi luas kepada kualitas demokrasi. Sebagian rakyat misalnya mungkin datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), atau memilih tidak ke TPS, atas dasar rasa khawatir mereka kepada kekerasan-kekerasan itu, atau pada pengalaman-pengalaman yang mereka lalui sebelumnya. Orang dibuat menjadi serba salah, seperti makan buah simalakama, “tidak dimakan mati ayah, dimakan mati ibu.”
Rasanya sangat tidak mungkin kekerasan itu terinstitusionalisasi dalam suatu wadah bernama partai politik. Mustahil untuk percaya bahwa ada semacam gerakan prokekerasan politik yang bersifat resmi dari parpol-parpol peserta pemilu, sebab jika benar demikian, maka esensi kehadiran parpol untuk menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan publik (konstituen) menjadi tak tercapai sama sekali. Alih-alih merupakan produksi kekerasan sebuah kebijakan resmi lembaga politik, kekerasan lebih merupakan produk dari perilaku individu-individu yang bisa saja bermotif politik atau tak memiliki motif politik namun menyasar kepada politisi atau lembaga politik.
Namun satu hal sudah jelas, kekerasan-kekerasan merupakan sebuah langkah mundur. Kualitas demokrasi akan turun karena kekerasan tersebut. Demikian pula legitimasi rakyat kepada partai politik dan atau kepada para caleg terpilih, akan lemah, padahal legitimasi itu syarat penting yang melekat kepada kekuasaan. Jika orang-orang yang dipercaya duduk di lembaga pemerintahan dan legislatif adalah orang yang kurang didukung atau kurang dipercayai, atau didukung atau dipercayai karena terpaksa, maka yang akan terjadi adalah kehancuran.
Sesungguhnya, dalam demokrasi modern, perbedaan pandangan dan bahkan perbedaan ideologi, selalu (diminta dan diharapkan) dikelola dengan cara-cara yang demokratis dan bersendikan kepada aturan hukum. Jadi, ketika kemudian ada orang yang menggunakan cara-cara yang melawan norma hukum, dan bahkan juga norma agama, maka ini mencederai demokrasi dan merupakan pertanda kemunduran peradaban. Memang ada budaya (culture), namun minim peradaban (civilization), padahal yang kita tuju adalah tidak hanya cultured melainkan juga civilized (berbudaya dan beradab).
Jalam nirkekerasan
Politik, lembaga politik, atau partai politik adalah suatu keniscayaan di dalam sistem demokrasi perwakilan, selalu ada, dan harus selalu ada. Parpol melalui wakil-wakilnya di parlemen adalah orang yang akan menentukan hitam-putih suatu bangsa dan negara, atau daerah dalam skala yang lebih kecil. Merekalah yang menentukan arah kebijakan pembangunan, mengentaskan kemiskinan, membaguskan kondisi kesehatan dan meninggikan kualitas pendidikan rakyat. Tetapi penting untuk memastikan bahwa semuanya dicapai dengan jalan nirkekerasan.
Solusi yang dapat ditawarkan akan terkait pada pemetaan terkini konflik atau politik kekerasan, siapa saja melakukan apa dan mengapa, yang kemudian bermuara kepada sebuah peta jalan untuk menuju kepada suatu tujuan (pengakhiran kekuasaan). Namun, di luar pemetaan ini, kesadaran kolektif untuk berlaku etis dalam rangka menuju ke sebuah Aceh yang maju --tetapi dicapai dengan cara-cara yang demokratis, harus menjadi mantra kehidupan semua kalangan. Kesadaran itu tak bisa sekadar ditunjukkan pada kegiatan deklarasi pemilu damai, melainkan juga sikap tindak di lapangan. Kesadaran harus dimaknai juga dalam bentuk internalisasi nilai-nilai demokratis, keadaban, dan kepatutan, di dalam organisasi politik. Manajemen konflik juga harus diperkuat; menghilangkan yang kecil, mengecilkan yang besar.
Juga karena politik adalah pembicaraan dan komunikasi, maka aktor-aktor politik perlu selalu berkomunikasi dengan cara yang sehat, tidak bias, dan relevan dengan keadaan yang ada, agar suasana sejuk lahir di dalam masyarakat. Selama ini telah ada imbauan dari pemerintah dan juga dari kalangan parpol, agar semua pihak menahan diri, dan juga desakan agar aparat penegak hukum bekerja maksimal. Ini imbauan yang sangat rasional, sebab penegakan hukum yang cepat tanpa pilih bulu, akan sangat membantu terciptanya pemilu yang aman dan berkualitas. Sebaliknya, kelengahan atau kelambatan dalam penegakan hukum, akan dianggap sebagai peluang untuk melanggar, membuka pintu pada semakin maraknya kekerasan.
Pengawasan oleh masyarakat juga sesuatu yang sangat penting. Warga masyarakat mesti ikut serta membantu menyejukkan suasana, tidak berlaku provokatif, dan juga memberikan informasi kepada penegak hukum. Sikap apatis yang ekstrem hanya akan membuat bunga-bunga kekerasan semakin mekar di pohonnya. Ketika buah itu matang, partisipasi politik pun akan terganggu.
* Saifuddin Bantasyam, Dosen Fakultas Hukum dan pengasuh mata kuliah Komunikasi Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala, Direktur Pusat Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik Unsyiah. Email: saifuddin_bantasyam@yahoo.com
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Dr-H-Herman-MADosen-STAIN-Teungku-Dirundeng-Meulaboh.jpg)






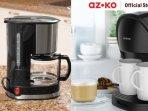

![[FULL] Jokowi All Out ke PSI, Pakar: Presiden ke-7 Dizalimi Jadi Pemantik 'Gajah' Lolos ke Senayan](https://img.youtube.com/vi/IdFiX3D3cco/mqdefault.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Mulkan-Fadhli.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Humam-Hamid-tanggapi-Benny-K-Harman.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Risman-A-Rahman-4-pulau-kembali.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Jasman-J-Maruf-adalah-Profesor-Manajemen-di-FEB-USK.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Prof-Dr-dr-Rajuddin-SpOGK-SubspFER-17-11.jpg)