Opini
Quo Vadis Hutan Aceh?
DI tengah memuncaknya semangat berinvestasi sebagai stimulan mendorong pertumbuhan pembangunan, seiring lahirnya Perpres
Oleh Hanif Sofyan
DI tengah memuncaknya semangat berinvestasi sebagai stimulan mendorong pertumbuhan pembangunan, seiring lahirnya Perpres No.39 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal khususnya Asing, telah mendorong Pemerintah Aceh membuka keran seluas-luasnya bagi laju investasi. Termasuk kemungkinan membuka areal hutan dan tambang menjadi konsesi baru investasi yang peluangnya terbuka melalui agroindustri. Meskipun masih berlanjutnya kebijakan Jeda Tebang (Moratorium Logging), nyatanya hutan-hutan Aceh kandas oleh kepentingan yang bersembunyi di balik kekuasaan para “raja-raja kecil” di kabupaten/kota sejalan dengan masih diberlakukannya otonomi dan desentralisasi di daerah.
Dengan realitas model otonomi kebijakan pengelolaan yang demikian, dikuatirkan dorongan investasi yang massif di tingkat kabupaten/kota, akan memunculkan dampak baru, utamanya dalam skema tata kelola tambang dan pembukaan serta alih fungsi hutan bagi pengembangan agroindustri. Konsistensi komitmen pemerintah dari provinsi hingga kabupaten diperlukan untuk mempertahankan Aceh sebagai provinsi pioneer yang mengusung konsep green province sejak diinisiasi oleh Plt Gubernur Aceh Azwar Abubakar serta pemberlakukan moratorium logging yang ditetapkan sejak 6 Juni 2007 oleh Irwandi Yusuf.
Mengapa kekuatiran ini timbul? Sesungguhnya realitas ini sangat beralasan, berbagai fakta yang terpampang menyajikan peta degradasi hutan Aceh. Dalam kurun waktu 50 tahun menyebabkan luas tutupan hutan Aceh dan Sumatera mengalami penurunan mencapai 40 persen, babak ini dimulai pascarehab-rekon tsunami. Sekalipun ditimpali dengan kebijakan donasi kayu, seperti yang pernah digagas WWF (World Wide Fund for nature), nyatanya kebutuhan pasar akan kayu tak pernah surut, justru membesar menciptakan demand-supply yang makin menggeroti saldo hutan Aceh menjadi makin kritis.
Gagasan sertifikasi kayu yang terus dijalankan dengan tujuan agar kehendak pasar untuk mendapatkan kayu terkontrol dengan lisensi, dalam realitasnya juga dipenuhi permainan terselubung untuk mendapatkan kayu ilegal dengan harga miring. Ini membuat respon pasar akan kayu ilegal murah berkualitas makin mencorong.
Kegagalan sistematis
Ada kegagalan yang secara sistematis beruntun menjadi malapetaka bagi hutan Aceh dan hutan Indonesia umumnya. Pertama, moratorium gagal mengerem laju deforestasi hutan; Kedua, meningkatnya jumlah penduduk menjadi salah satu alasan kuat, dan; Ketiga, permintaan global terhadap kayu sebagai bahan baku pulp, kertas dan kelapa sawit, mendorong illegal logging makin marak dan sistematis. Namun inti sebenarnya dari sebagian besar kerusakan hutan (deforestasi), karena sistem politik dan ekonomi yang menganggap sumber daya hutan sebagai pendapatan, sehingga dapat diekploitasi untuk kepentingan politik dan personal.
Sekalipun komitmen dibangun dalam konteks tindakan preventif, namun realitas hari ini, menimbulkan kekuatiran yang cukup beralasan. Apalagi banyak pihak yang pro lingkungan meragukan komitmen pemerintah karena ganjalannya cukup kentara, kepentingan politik, alasan pembiayaan pembangunan yang membutuhkan dana besar, ditimpali pro kontra antar kelompok dalam konflik horizontal yang tidak kentara.
Bukti paling kongkrit dan mutakhir adalah kasus perambahan 500 hektar hutan lindung menjadi lahan kebun kentang di kawasan Desa Nosar Baru di Kecamatan Permata, dan Desa Bener Pepanyi di Kecamatan Bandar, Bener Meriah. Berada pada ketinggian 2.200-2.400 meter di atas permukaan laut yang tidak dapat terdeteksi oleh Kesatuan Pengamanan Hutan (SPH) dan Dinas Kehutanan Bener Meriah (Serambi, 12/7/2014).
Fakta terbaru skala nasional yang cukup mengerikan dan merupakan indikasi umum tingkat kerusakan dalam satu dasawarsa ini, 6 juta Hektare (Ha) hutan Indonesia sepanjang 2000-2012 gundul. Terutama di Sumatera, termasuk kawasan hutan moratorium izin hutan yang dibiayai Norwegia. Dan angka kerusakannya lebih tinggi dari Brazil (Tempo, 4/6/2014). Hasil ini dipaparkan oleh Jurnal Nature Climate Change (edisi 29/6/2014), tepatnya bahwa 6,02 juta Ha hutan primer rusak parah (kawasan hutan yang murni dan penuh dengan kekayaan keanekaragaman hayati).
Kerusakan ini meningkat sekitar 47.600 Ha per tahun hingga saat ini. Sekitar 40%nya kerusakan pembukaan hutan tersebut terjadi di kawasan taman nasional, hutan lindung dan area moratorium hutan. Catatan ini meneguhkan kembali Indonesia sebagai negara tercepat hancurkan hutan. Dan laju deforestasi tersebut tertinggi berada di Sumatera, kemudian diikuti Kalimantan, lalu Papua.
Musabab yang dianggap paling bertanggung jawab adalah persoalan lemahnya penegakan hukum dan praktik korupsi di jajaran pemerintahan. Disinyalir pembukaan lahan besar tidak dilakukan oleh pengusaha kecil, namun dilakukan para pengembang lahan agroindustri besar. Jika lahan di dataran rendah habis, maka alternatif yang kemudian dipilih adalah lahan gambut yang kasusnya sempat menimbulkan malapetaka besar kebakaran dan hilangnya primata khas, orang utan di wilayah gambut Rawa Tripa di Nagan Raya setahun lalu.
Potret buram
Potret buram ini setali tiga uang dengan berbagai kasus degradasi yang bermunculan secara simultan di Aceh. Fakta yang patut menjadi perhatian bahwa sepanjang 2006 saja, luas hutan di kawasan Sumatera dan Aceh yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta Ha dari 120.35 juta Ha kawasan hutan di Indonesia dengan laju deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,83 juta Ha pertahun (SIEJ, 10/6/2014). Hutan terus mengalami degradasi sebagai bagian dari efek domino kerusakan hutan yang melanda wilayah Sumatera secara keseluruhan.
Berbagai fakta tersebut mestinya menjadi catatan penting bagi penyelenggaraan dan penumbuhan iklim investasi di Aceh. Karena bukan tidak mungkin kerusakan secara massif yang terjadi di Riau paling mutakhir pada akhirnya akan merembet dengan cepat ke Aceh. Terutama paska dibukanya peluang AIP (Aceh Investment Promotion) I, 20 Mei 2014 lalu. Investasi tanpa kendali yang ketat, bisa jor-joran jika orientasinya hanya ingin meraup untung tanpa pertimbangan daya dukung dan krusialnya kebutuhan pendanaan pembangunan disertai tata kelola dan skala prioritas.
Komitmen green province dan moratorium logging yang telah mati suri harus diperbaharui, dimatangkan kembali dalam kerangka membangun Aceh sebagai daerah investasi baru yang menjanjikan. Jika tidak, akan membuat hutan kita menjadi martir untuk memenuhi harapan memenuhi syarat equilibrium --keseimbangan kebutuhan pembangunan dan pelestarian hutan sekaligus. Tantangannya bagi pemerintah Aceh adalah dalam mematangkan komitmen membangun Aceh tanpa merusak, gagasan pembangunan berkelanjutan (sustainability development).
Maka solusi bijaksana dalam konteks Aceh, disamping kebijakan moratorium logging, green province serta sistem pemberian izin yang diperketat, sekalipun skema kebijakan masih mengacu pada pemberlakuan UU otonomi dan desentralisasi daerah. Melihat berbagai peluang dan ancaman, kita harus super ekstra hati-hati dalam mendorong tumbuhnya iklim investasi. Dengan mendorong berbagai sektor yang produktif seperti halnya agroindustri melalui pemanfaatan berbagai lahan tidur yang tidak produktif, bukan dengan membuka lahan baru. Tidak sekadar mengejar diversifikasi, namun juga intensifikasi. Reformasi birokrasi, reformasi kebijakan dan komitmen good governance (pemerintahan bersih), menjadi tumpuan dan harapan terakhir atas masa depan tambang dan hutan-hutan kita.
Hanif Sofyan, Pegiat Aceh Environmental Justice. Email: acehdigest@gmail.com
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Dr-H-Herman-MADosen-STAIN-Teungku-Dirundeng-Meulaboh.jpg)






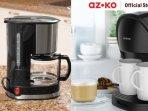

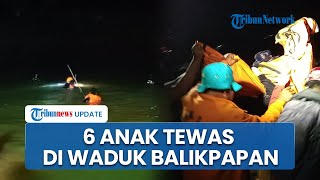
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Mulkan-Fadhli.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Humam-Hamid-tanggapi-Benny-K-Harman.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Risman-A-Rahman-4-pulau-kembali.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Jasman-J-Maruf-adalah-Profesor-Manajemen-di-FEB-USK.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Prof-Dr-dr-Rajuddin-SpOGK-SubspFER-17-11.jpg)