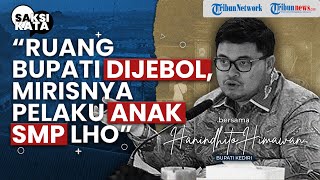Kupi Beungoh
Ekonomi Gampong Bakongan: Pasar dan Adab Baru Global Agribisnis Sawit (X)
Tidak dapat dibantah fenomena produksi kelapa sawit dalam 20 tahun terakhir telah menyita cukup banyak perhatian.
Oleh: Ahmad Humam Hamid*)
MENGGUNAKAN kata-kata adab dalam konteks konsumsi pangan Aceh sebenarnya lebih berkonotasi kepada cara menyajikan dan cara makan makanan.
Yang paling sering disebut misalnya ketika makan, jangan menggunakan tangan kiri, atau ketika mengunyah makanan jangan keluar bunyi yang besar dari mulut, atau jangan bicara ketika makan.
Semua adab makan Aceh itu tidak ada urusannya dengan adab konsumsi minyak nabati global, khususnya minyak sawit, yang kini telah menjadi bagian terbesar dari konsumsi minyak nabati terbesar di dunia.
Yang dimaksud dengan adab dalam konteks minyak nabati global adalah serangkaian perilaku produksi dan konsumsi yang berpedoman kepada prinsip berkelanjutan.
Pesan intinya adalah motto global kehidupan berkelanjutan manusia.
Hal ini cukup beralasan, karena dunia semakin mengakui tentang ancaman kehidupan saat ini yang digempur dari berbagai kegiatan ekonomi yang merusak lingkungan, dan budidaya sawit, termasuk salah satunya.
Motto itu berpijak kepada keselamatan planet, keuntungan ekonomi dan keuangan, dan kesejahteraan manusia.
Dengan demikian, apa yang hendak dicapai adalah sebuah rambu-rambu yang mampu membendung, paling kurang meminimalisir, potensi destruktif lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat dari agribisnis kelapa sawit.
Baca juga: Ekonomi Gampong: Bakongan, Barsela, Reaganomics, dan Kekeliruan Sri Mulyani (I)
Baca juga: Ekonomi Gampong Bakongan: Menanam Jagung di Kebun Sawit, Tesis Denys Lombard Benar di Trumon (IX)
Kompleksitas Dilema Sawit
Tidak dapat dibantah fenomena produksi kelapa sawit dalam 20 tahun terakhir telah menyita cukup banyak perhatian, terutama di kawasan episentrum budidayanya, di Asia Tenggara.
Headline berbagai media, dan tulisan ilmiah di berbagai jurnal akademik mengambarkan keparahan di dua negara ASEAN, Indonesia dan Malaysia, dalam hal deforestrasi, kabul asap lintas negara, dan kepunahan keanekaragaman hayati.
Tidak berhenti dengan ancaman lingkungan, agribisnis sawit oleh perusahaan juga telah membuat perlakuan tidak adil terhadap penduduk lokal, perambahan tanah komunal dan konflik agraria.
Disamping itu juga, sangat sering diberitakan tentang praktek ketenagakerjaan perusahaan sawit yang tidak patuh terhadap standar perburuhan formal yang berlaku.
Tidak hanya protes dan berbagai perlakuan yang diberikan terhadap agribisnis ini baik oleh negara pengimpor produk sawit, ilmuwan, masyarakat konsumen, LSM lingkungan internasional, dan saingan yang terdesak dari keluarga minyak nabati itu sendiri.
Terhadap semua realitas itu, sampai tingkat tentu saja benar adanya.
Berbagai tuduhan ada yang benar dan tidak kurang pula berlebihan, dan itu sudah dan sedang terjadi.
Baca juga: Dasar Hukum Potong Timbangan Kelapa Sawit di Pabrik Rugikan Petani Rp 54 Miliar Setahun
Baca juga: Perusahaan Kelapa Sawit di Nagan Bantu Bangun Rumah Warga Kurang Mampu
Pilihan Realistis dan Kompromi
Fakta yang ada saat ini menunjukkan bahwa dalam 25 tahun terakhir ini, 5 persen hutan tropis dunia telah dikonversi menjadi kebun sawit.
Kegiatan itu dikerjakan oleh perusahaan maupun petani yang tersebar di paling kurang 7 negara, dimana Indonesia dan Malaysia berada pada ranking tertinggi.
Dalam perjalanannya, tidak kurang sejumlah ilmuwan memberi label sawit sebagai kejahatan, bahkan kriminal kemanusiaan.
Mereka lupa bahwa tanaman ini adalah anugerah Tuhan terbesar untuk mayarakat kawasan tropis yang jika dikerjakan dengan benar akan memberikan banyak sekali manfaat.
Kelapa sawit dapat peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan industri pengolahan dan lanjutannya, dan berbagai ikutan lainnya yang mempercepat pembangunan.
Kalimat kunci yang mesti dipertanyakan terhadap semua protes keras terhadap sawit adalah, peluang apa yang terbuka kepada masyarakat kawasan tropis yang umumnya berstatus negara berkembang, seandainya budidaya sawit dihentikan?
Jika sawit dilihat sebagai anugerah Tuhan kepada masyarakat tropis, apa yang mesti dilakukan sehingga peluang sawit untuk menjadi punca bala kemanusiaan dapat dicegah?
Sebuah strategi alternatif yang kemudian muncul terhadap polarisasi itu adalah mencari strategi dan teknik budidaya sawit yang dapat memberikan manfaat optimal, dengan sangat sedikit memberikan kerugian lingkungan, ekonomi, dan nonekonomi.
Strategi itu adalah rumusan kompromi aspirasi dan ekspektasi yang membawa sebanyak mungkin pemangku kepentingan terhadap sawit mulai dan konsumen rumah individu dan tangga, sampai dengan petani dan masyarakat lokal, dengan kata kunci “keberlanjutan”.
Ada banyak penjelasan tentang kata keberlanjutan, namun yang paling awal memulai konsep ini datang dari sebuah organisasi nirlaba RSPO- Roundtable on Sustainable Palm Oil.
Lembaga menyatukan berbagai aktor pemangku kepentingan yang berurusan dengan kelapa sawit.
Lembaga ini berfungsi sebagai pemberi sertifikat kepada produk sawit dalam perdagangan internasional.
Acuan yang dijadikan itu adalah prinsip pertanian dan industri keberlanjutan. Pedoman tentang keberlanjutan di rumuskan dengan berbagai alat ukur yang mesti dipenuhi, sehingga layak di sebut sebagai adab baru komoditi kelapa sawit.
Baca juga: Kelapa Sawit ‘Penyelamat’ Perekonomian Warga Subulussalam Saat Pandemi, Begini Penjelasan Apkasindo
Adab Baru Budi Daya dan Agribisnis Sawit
Apa yang membuat unik tentang adab baru itu adalah ide itu awalnya datang dari produsen raksasa barang-barang kebutuhan rumah tangga global, Unilever pada tahun 2004.
Inisiatif itu kemudian juga mendapat dukungan dari LSM lingkungan internasional WWF, dan sebagaian ilmuwan.
Kepeloporan Unilever yang juga didukung oleh WWF dan sejumlah perusahaan kelapa sawit Malaysia bagaimanapun adalah sebuah keberuntungan untuk negara-negara produsen sawit yang sangat terganggu dengan kampanye buruk sawit itu.
Bayangkan saja LSM sekelas Green Peace, Rainforest, Friend of the Earth, dan cukup banyak lagi yang menentang budidaya kelapa sawit, dengan segala alasan lingkungan dan sosial ekonomi yang buruk.
Tanpa kehadiran RSPO- dengan segala kelebihan dan kelemahannya, dipastikan negara-negara produsen sawit, seperti Indonesia dan Malaysia akan sangat kelabakan melayani kampanye hitam itu.
Untuk diketahui Unilever adalah salah satu dari 10 produsen terbesar barang kebutuhan sehari-hari global setelah Nestle, Procter&Gamble, dan PepsiCo, dengan penjualan lebih dari 50 miliar US dollar per tahun.
Selanjutnya sekitar 50 persen dari barang-barang kebutuhan sehari-hari rumah tangga dijual di supermarket adalah produk yang menggunakan minyak sawit.
Di tengah gempuran boikot konsumen akibat kampanye tentang sisi buruk agribisnis sawit terhadap lingkungan, dan sosial ekonomi petani dan kondisi lokal, jika hal itu berlanjut akan mengancam tidak hanya petani, akan tetapi juga perusahaan-perusahaan besar sekelas Unilever.
Dengan laba kotor perusahaan besar produsen kebutuhan sehari-hari seperti Unilever, sekitar 66 persen (Chain Reaction Research 2021), dapatlah dibayangkan berapa besar kerugian atau kehilangan peluang laba yang akan diperoleh, seandainya tidak dilakukan langkah-langkah balasan untuk mengimbangi kampanye buruk tentang produk sawit di negara-negara Eropa dan AS.
Parahnya lagi kampanye itu bukan hanya berhubungan dengan alasan-alasan ilmiah yang dapat dicari solusinya.
Kampanye buruk tentang sawit itu juga telah bercampur dengan perang dagang yang dilancarkan oleh kelompok minyak nabati lain yang diproduksi di AS dan Eropa yang semakin kalah bersaing harga dengan minyak sawit.
Komitmen sertifikası sawit yang diajukan oleh RSPO, kemudian disambut oleh negara-negara produsen.
Indonesia mengajukan ISPO, dan Malaysia mengajukan MSPO, yang prinsip intinya tetap saja sawit yang berkelanjutan, dengan keragaman di sana-sini.
Sebenarnya isi prinsip-prinsip ISPO itu sendiri sudah ada dalam berbagai produk hukum nasional, yang dalam pelaksanaannya sering tidak dipatuhi dilapangan.
Lebih dari itu pemerintah juga kadang membiarkan berbagai pelanggaran.
Sertifikasi yang dikeluarkan oleh RSPO tidak lain dari pengakuan lembaga itu bahwa produk sawit yang dikonsumsi konsumen itu telah memenuhi sejumlah prinsip yang terukur dan terkumpul dalam 5 pinsip dasar.
Prinsip-prinsip itu adalah, bahwa produk sawit yang akan dibeli oleh Unilever tidak berasal dari kawasan deforestratsi, terutama dari kawasan yang tinggi kenekaragaman hayati tinggi.
Larangan penggunaan lahan gambut juga menjadi salah satu prinsip RSPO yang penting.
Prinsip-prinsip lainnya adalah prinsip keadilan bagi pekerja dan atau masyarakat terkait.
Yang juga tidak kalah pentingnya adalah prinsip dorongan untuk pembangunan dan kesejahteraan petani sawit, termasuk peningkatan peran perempuan.
Hal lain yang paling mendasar juga adalah penerapan prinsip transparansi, yakni semua produk sawit itu harus transparan sepanjang rantai pasok, dapat diteliti asal masal dan perlakuannya, termasuk peluang pengaduan yang juga disedikan.
Prinsip itu kini RSPO yang disposnsori itu kini semakin dugunakan secara luas.
Produsen papan atas berbagai produk makanan dan rumah tangga Nestle-Swiss, dan PepsiCo juga telah mengunakan prinsip RSPO dalam membeli produk sawit untuk industri mereka.
Ini artinya berbagai ancaman dan kampanye hitam tentang produk sawit, telah semakin terimbangi dengan sertifikasi yang dterapkan oleh perusahaan raksasa pemakai produk sawit untuk komoditi indutsri mereka.
Pasar menjadi semakin ketat dalam menggunakan prinsip-prinsip yang semakin ketat dan terukur.
Itu artinya budidaya sawit yang akan mendapat sambutan pasar adalah budidaya yang menganut prinsip-prinsip RSPO.
Dan itu adalah adab baru yang mesti diikuti oleh pelaku budidaya sawit, baik petani, maupun perusahaan.(*)
*) PENULIS adalah Sosiolog, Guru Besar Universitas Syiah Kuala.
KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.