Opini
Penguasa dan Parade Keangkuhan
Kasus yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Pidie Jaya menjadi potret getir dari krisis etika kekuasaan yang kian menampakkan wajah
Oleh: Khairil Miswar, Penulis buku Islam Mazhab Hamok
DALAM masyarakat yang sedang berusaha menegakkan peradaban politik yang sehat, setiap tindakan pejabat publik tidak lagi sekadar urusan pribadi, melainkan menjadi cermin moral bagi rakyat yang diwakilinya. Seorang pejabat publik, dengan segala simbol dan perangkat kekuasaannya, selalu membawa konsekuensi sosial.
Ia bukan hanya representasi politik, tetapi juga representasi moral dari tatanan yang berlaku. Karena itu, ketika seorang pejabat bertindak di luar nalar kepantasan, maka yang tercederai bukan hanya nama baik pribadi, tetapi juga nilai-nilai publik yang hidup dalam masyarakat.
Kasus yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Pidie Jaya menjadi potret getir dari krisis etika kekuasaan yang kian menampakkan wajah aslinya, krisis yang memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi moral pejabat publik di hadapan godaan arogansi.
Apa yang terjadi di Pidie Jaya baru-baru ini semakin menambah kegelisahan kita. Seorang pejabat publik yang semestinya menjadi teladan dan pengayom justru tampil sebagai simbol keangkuhan, satu sikap yang membuat setan dikutuk, Qarun terkubur di dasar bumi, dan Fir’aun tenggelam di Laut Merah. Sikap yang dilandasi oleh rasa superioritas itu, dalam sejarah umat manusia, selalu menjadi pemicu lahirnya penindasan dan kolonialisme.
Max Weber menyebut fenomena ini sebagai rusaknya “dominasi legal-rasional” (birokrasi). Legitimasi kekuasaan yang bersandar pada kerangka aturan rasional dan etis seketika runtuh saat kekuasaan berubah menjadi panggung ego pribadi.
Pejabat publik pun berhenti menjadi pelayan rakyat yang impersonal, dan bertransformasi menjadi penguasa angkuh yang sibuk mengutamakan gengsi dan amarah. Dan, sayangnya, sikap itulah yang baru-baru ini dipertontonkan oleh seorang oknum pejabat publik di Pidie Jaya.
Dalam tayangan video yang beredar di media sosial, tampak seorang oknum pejabat yang disebut-sebut sebagai Wakil Bupati Pidie Jaya melakukan tindakan kekerasan, atau dengan bahasa halusnya, membogem seorang laki-laki yang disebut sebagai kepala dapur MBG di sebuah kecamatan.
Dari tayangan yang kemudian viral dan diliput media nasional, terlihat pula bahwa selain melakukan pemukulan, oknum tersebut juga sempat memarahi beberapa orang di lokasi kejadian. Bahkan, ironisnya lagi, ia juga sempat memaki seorang perempuan dengan kefasihan yang nyaris sempurna.
Merujuk pada teori Michel Foucault (1975), fenomena ini, dalam bahasa yang lebih sederhana, dapat dibaca sebagai bentuk “demontrasi kekuatan”, di mana kekerasan verbal dan fisik menjadi instrumen untuk menegaskan hierarki sosial dan mempertahankan dominasi. Dengan kata lain, tubuh dan kata digunakan bukan lagi sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai sarana kontrol.
Tindakan demikian bukan saja mencoreng wajah Pidie Jaya yang tahun ini konon menjadi tuan rumah MTQ Provinsi Aceh, tetapi juga menampar wajah Aceh yang telah lebih dari dua dekade menjalankan formalisasi syariat Islam.
Perilaku itu adalah bentuk paling purba dari ekspresi kekuasaan, yang mengingatkan kita pada tindakan agresif aparat militer di masa lalu, masa ketika kekuasaan dijalankan bukan dengan akal sehat, melainkan dengan senapan dan peluru.
Dalam perspektif sosiologi kekuasaan, seperti dijelaskan Pierre Bourdieu (1991), kekerasan semacam ini merupakan manifestasi dari symbolic violence, kekerasan yang tampak sepele, tetapi sesungguhnya berfungsi melestarikan struktur dominasi melalui bahasa, gestur, dan tindakan sehari-hari. Bourdieu mengingatkan bahwa kekuasaan yang tak terdidik akan selalu berusaha menegaskan eksistensinya dengan cara paling kasar, karena hanya di sanalah ia merasa diakui.
Pasca insiden tersebut, media sosial dipenuhi beragam komentar. Mayoritas publik mengutuk tindakan itu sebagai manifestasi premanisme. Namun, tidak sedikit pula yang mencoba memberikan pembelaan naif terhadap tindakan “barbarian” itu, sebagian dilatari oleh kesamaan basis politik dengan pelaku.
Di sisi lain, pembelaan-pembelaan kecil juga muncul dari kekecewaan terhadap kualitas pelayanan MBG yang dianggap tidak layak. Fenomena ini menunjukkan bagaimana moral publik sering kali tersandera oleh loyalitas politik.
Antonio Gramsci (1971) menyebut kondisi ini sebagai bentuk hegemoni, yakni ketika kesadaran masyarakat dimanipulasi untuk membenarkan tindakan elite yang sebenarnya bertentangan dengan kepentingan publik. Loyalitas politik yang berlebihan menumpulkan nurani, membuat sebagian orang lebih rela membela kekuasaan daripada membela kebenaran.
Tidak lama setelah kejadian, oknum Wabup Pijay tampak melontarkan permintaan maaf melalui sebuah video singkat. Dalam tayangan itu, ia berbicara dengan nada rendah, memohon maaf kepada korban. Namun, publik tidak serta-merta luluh.
Sebagian besar netizen tetap menuntut pertanggungjawaban hukum. Yang menarik, muncul pula sebagian kecil pihak yang bersikap “sok bijak”, menganggap permintaan maaf pelaku sebagai sikap heroik yang patut diapresiasi, bahkan dikenang sebagai keluhuran budi.
Mereka berharap korban memaafkan pelaku sebagai bentuk kesabaran dan kebersihan hati. Sikap ini tampak mulia di permukaan, tetapi dalam konteks kekuasaan dan kekerasan, ia justru memperlihatkan bagaimana moralitas publik mudah direduksi menjadi sentimentalitas.
Kita tentu tidak menegasikan nilai luhur dari sikap memaafkan. Namun, dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh pejabat publik, apalagi yang disebut-sebut sebagai perilaku berulang, pemaafan menjadi tidak relevan dalam konteks sosial.
Ia hanya berfaedah secara personal bagi korban, tetapi tidak memberikan efek edukatif bagi publik. Dalam jangka panjang, sikap semacam ini berpotensi menormalisasi kekerasan sebagai bagian dari kebudayaan kita.
Emile Durkheim (1893) mengingatkan bahwa solidaritas sosial akan rapuh ketika pelanggaran moral tidak lagi dipandang sebagai ancaman terhadap tatanan kolektif, tetapi sekadar urusan pribadi. Maka, pemaafan yang tidak pada tempatnya justru mengikis rasa keadilan sosial dan menempatkan hukum sebagai pilihan sekunder yang tidak pernah sungguh-sungguh ditegakkan.
Jika dibiarkan, praktik ini akan membentuk budaya politik yang permisif terhadap kekerasan. Dalam jangka panjang, masyarakat akan terbiasa melihat pejabat memperlakukan warga secara tidak bermartabat tanpa merasa perlu marah.
Inilah yang disebut Erich Fromm sebagai proses hilangnya kepekaan moral, yaitu ketika masyarakat kehilangan kemampuan untuk merasakan jijik terhadap tindakan yang seharusnya tercela. Artinya, kekerasan yang terus diabaikan akan menjadi banal, sesuatu yang diterima begitu saja. Hannah Arendt bahkan menyebut fenomena ini sebagai “banalitas kejahatan”, yaitu saat keburukan menjadi rutinitas, dan pelakunya bahkan tidak lagi merasa bersalah.
Karena itu, penegakan hukum, terutama terhadap pejabat publik yang dipilih melalui proses demokratis, harus ditegakkan tanpa kompromi. Ini bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan rasa keadilan sosial dan meneguhkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Kita bisa membayangkan, jika posisi dalam kasus itu terbalik: pelaku adalah rakyat jelata dan korban adalah seorang wakil bupati, hampir dapat dipastikan proses hukum akan berjalan secepat buraq melintasi langit.
Perbedaan perlakuan ini menyingkap apa yang oleh Bourdieu disebut sebagai field of power, yaitu arena sosial di mana hukum, politik, dan ekonomi saling bertarung untuk memperebutkan legitimasi moral dan simbolik. Dalam arena itu, hukum kerap menjadi alat bagi yang berkuasa, bukan payung bagi yang lemah.
Karena itu pula, publik harus terus menuntut agar hukum tidak tunduk kepada jabatan. Negara hukum tidak boleh memberi ruang bagi kekuasaan yang bersifat feodal. Kekuasaan sejatinya adalah amanah, bukan hak istimewa.
Ketika kekuasaan kehilangan orientasi etisnya, maka rakyat berhak untuk bersuara dan menegur, sebab demokrasi tidak pernah memberi izin kepada siapa pun, termasuk penguasa, untuk melakukan parade keangkuhan.(*)









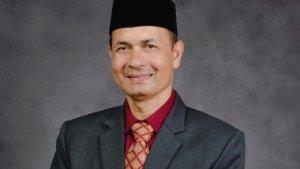











Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.