Opini
Aceh: Otsus Rasa Merdeka
Namun, di balik itu, Aceh pun menuntut pengakuan yang lebih tinggi atas identitas, martabat, dan hak-haknya.
Dr Fuadi Mardhatillah MA, Pengasuh MK Filsafat UIN Ar-Raniry, dan Anggota Dewan Pembina The Aceh Institute
ACEH selalu menjadi daerah yang unik dalam sejarah panjang Indonesia. Sejak masa kesultanan, Aceh memiliki tradisi politik, hukum, dan agama yang kuat. Rasa kemerdekaan yang tertanam di hati orang Aceh bukanlah sekadar ilusi, melainkan buah dari sejarah panjang perjuangan mempertahankan marwah. Ketika Republik Indonesia berdiri, Aceh dianggap sebagai wilayah yang memberikan legitimasi moral dan material bagi lahirnya negara. Namun, di balik itu, Aceh pun menuntut pengakuan yang lebih tinggi atas identitas, martabat, dan hak-haknya.Tuntutan itu menemukan momentum baru setelah penandatanganan MoU Helsinki (2005) dan lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006. Di sinilah titik balik yang menarik: Aceh memperoleh otonomi khusus (Otsus), tetapi rasa merdeka itu tetap menggantung. Pertanyaannya, apakah UUPA dapat dibaca ulang, secara hermeneutika ma‘rifati, untuk menghidupkan kembali cita rasa kemerdekaan Aceh dalam bingkai NKRI?
Secara formal, UUPA adalah instrumen hukum. Namun secara batin, ia adalah teks yang lahir dari sejarah panjang pertarungan politik, darah, dan doa orang Aceh. Hermeneutika ma‘rifati mengajarkan bahwa teks hukum tidak boleh hanya dibaca literal, melainkan harus ditafsirkan dengan menyelami ruh yang melahirkannya. UUPA bukan sekadar “aturan teknis”, tetapi “amanah sejarah” yang merekam kompromi antara tuntutan merdeka orang Aceh dan kebutuhan negara menjaga kedaulatan.
Dengan cara pandang ini, UUPA dapat dilihat sebagai “jembatan makna”: negara seakan memberi, tetapi sesungguhnya ia mengakui “hak historis” Aceh yang tak bisa dihapuskan. Membaca UUPA dengan kacamata ma‘rifati berarti mencari dimensi spiritual dari politik hukum. Aceh tidak sekadar diatur, melainkan diberi ruang untuk mengekspresikan jatidiri Islaminya, tradisinya, bahkan memproyeksikan dirinya sebagai laboratorium perdamaian dan syariat di dunia modern.
Rasa merdeka
Bila diteliti cermat, UUPA menyimpan banyak peluang legal yang sebenarnya bisa dipakai untuk menghadirkan “rasa merdeka” Aceh, tetapi hingga kini luput dimanfaatkan secara maksimal. Beberapa di antaranya: Pertama, Kewenangan Internasional Terbatas. UUPA membuka peluang Aceh untuk menjalin kerja sama luar negeri dalam bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, hingga investasi. Namun, potensi ini belum digarap dengan visi geopolitik Aceh sebagai “Serambi Mekah” yang strategis. Dengan tafsir progresif, Aceh dapat menjadi pintu gerbang dunia Islam di Asia Tenggara.
Kedua, Peran Partai Politik Lokal. Aceh satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberi hak membentuk partai politik lokal. Namun, partai-partai lokal masih sibuk pada perebutan kursi kekuasaan, bukan pada pelembagaan aspirasi rakyat. Padahal, bila ditata dengan visi, partai lokal dapat menjadi wadah artikulasi “suara Aceh” yang otonom dan bermartabat.
Ketiga, Pengelolaan Sumber Daya Alam. Secara normatif, UUPA memberikan kewenangan lebih besar kepada Aceh dalam mengelola minyak, gas, dan sumber daya laut. Sayangnya, praktiknya masih dominan dikendalikan pusat. Dengan pendekatan ma‘rifati, Aceh perlu menafsir ulang pasal-pasal ini sebagai “amanah kesejahteraan”, bukan sekadar bagi hasil.
Keempat, Simbol-Simbol Kekhususan. UUPA mengakui bendera, lambang, dan himne Aceh. Namun pelaksanaannya masih terbentur politik nasional. Padahal, simbol ini bukan ancaman, melainkan identitas kultural. Bila dikelola bijak, ia menjadi energi kohesi, bukan pemisahan. Kelima, Keadilan Syariat. Aceh diberi kewenangan melaksanakan syariat Islam. Namun penerapannya sering direduksi pada hukum formil (qanun jinayat). Padahal, syariat juga menyangkut keadilan sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Ruang tafsir ini masih terbuka luas untuk dihidupkan.
Mirip protektorat
Secara diam-diam, Aceh berada dalam posisi unik yang mirip dengan “protektorat” dalam hukum internasional. Sebuah wilayah yang berdaulat secara kultural-historis, tetapi berada dalam lindungan negara besar. Pusat memberi ruang lebih, tetapi tetap membatasi garis kemerdekaan penuh. Konsep protektorat ini bisa dipandang negatif—Aceh seolah masih “diatur dari atas”. Namun, bila dilihat dengan hermeneutika ma‘rifati, ia justru bisa dimaknai sebagai strategi hikmah: sebuah jalan tengah agar identitas Aceh tetap hidup tanpa harus berpisah dari NKRI. Dengan posisi ini, Aceh bisa membangun rasa merdeka dari dalam: melalui syariat, budaya, pendidikan, hingga hubungan internasional terbatas. Jadi, meskipun bukan negara berdaulat penuh, Aceh tetap dapat tampil sebagai “negeri berdaulat di dalam negeri”.
Pertanyaan penting: bagaimana menghadirkan “rasa merdeka” itu dalam praksis? Jawabannya ada pada tiga langkah strategis: Pertama, Tafsir Progresif UUPA. Alih-alih menunggu pusat, Aceh harus menafsir ulang pasal-pasal UUPA dengan semangat kreatif. Apa yang sudah diberikan harus dijabarkan maksimal, bukan hanya dikunci dalam teks.
Kedua, Konsolidasi Politik Lokal. Partai lokal harus bertransformasi dari “alat rebut kursi” menjadi “rumah aspirasi rakyat Aceh”. Mereka harus mampu menyalurkan energi sejarah ke dalam kebijakan modern yang mensejahterakan. Ketiga, Diplomasi Budaya dan Syariat. Aceh perlu membangun citra global sebagai model Islam damai, terbuka, dan adil. Dengan demikian, Aceh tidak hanya dikenal karena konflik masa lalu, tetapi karena kontribusi pada dunia Islam kontemporer.
Keempat, Ekonomi Kemandirian. Sumber daya Aceh harus benar-benar dikelola untuk rakyat, bukan hanya elite. Dengan ekonomi yang kuat, rasa merdeka akan lebih terasa, sebab kemerdekaan sejati lahir dari kemandirian. UUPA bukan sekadar dokumen hukum. Ia adalah prasasti sejarah yang memuat kompromi, doa, dan harapan orang Aceh. Dengan membacanya melalui hermeneutika ma‘rifati, kita menyadari bahwa di balik pasal-pasal kaku, tersimpan peluang besar untuk menghadirkan “rasa merdeka” yang menjadi identitas Aceh.
Aceh bukan hanya daerah dengan otonomi khusus, melainkan sebuah protektorat yang diberi kesempatan untuk tetap berbeda, tetap unik, dan tetap bermartabat. Tinggal bagaimana orang Aceh sendiri menjabarkan peluang itu, mengisinya dengan visi, dan menjaga ruh perjuangan agar tidak hilang dalam permainan politik sesaat.
Merdeka bagi Aceh bukan sekadar berdiri sendiri sebagai negara, melainkan kemampuan untuk menghidupkan jatidiri, mengelola kekayaan dengan adil, dan menunjukkan pada dunia bahwa Aceh adalah negeri yang bermarwah. Di situlah letak “Otsus rasa merdeka”—sebuah rasa yang lahir dari tafsir, sejarah, dan keberanian untuk mengisi ruang yang sudah ada.
Opini Hari Ini
Penulis Opini
Serambi Indonesia
Serambinews.com
Serambinews
Aceh Otsus Rasa Merdeka
Dr Fuadi Mardhatillah MA
| Saat Pemimpin tak Hadir di Tengah Bencana: Dilema Etika Antara Hak Personal & Tanggung Jawab Publik |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/bencana-0okl.jpg)
|
|---|
| Aceh sebagai Pintu Gerbang Perdagangan Internasional, Mengaspirasi Pembangunan Dubai |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/apridarrr.jpg)
|
|---|
| Nasib Aceh jika Kepala Daerah Dipilih DPRD |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Ketua-KIP-Kota-Banda-Aceh-Yusri-Razali-03.jpg)
|
|---|
| Menata Standar Pendidikan Menuju Ekosistem yang Lebih Bermakna |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Sekolah-Darurat-27738.jpg)
|
|---|
| Dampak Bencana dan Antisipasi Perubahan RPJMA 2025-2029 |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Weri-2025.jpg)
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Fuadi-Mardhatillah.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Dr-Ainal-Mardhiah-SAg-MAg-Relawan-Banjir-Bandang-Aceh.jpg)

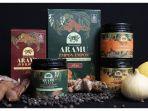






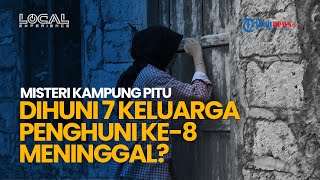
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Ketua-KIP-Kota-Banda-Aceh-Yusri-Razali-03.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/T-A-SAKTI-II.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Jafar-Insya-Reubee-Pemerhati-Pembangunan-Aceh-berdomisili-di-Negeri-Selangor-Kerajaan-Malaysia.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/humam-hamid-sosiolog-aceh-4.jpg)