Opini
Berapa Potensi Emas Aceh Sebenarnya?
Lonjakan harga emas dunia tahun 2025, yang menembus kisaran USD 2.350–2.450 per troy ounce (WGC, 2025), menjadi salah satu pemicunya.
Muhammad Hardi ST MT, Inspektur Tambang Ahli Madya Kementerian ESDM dan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia PD Aceh
DALAM beberapa tahun terakhir, berbagai wilayah di Aceh kembali dipenuhi aktivitas tambang emas ilegal, mulai dari Pidie, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tengah, hingga Gayo Lues. Fenomena ini tidak hadir tanpa sebab. Lonjakan harga emas dunia tahun 2025, yang menembus kisaran USD 2.350–2.450 per troy ounce (WGC, 2025), menjadi salah satu pemicunya. Level ini merupakan rekor tertinggi dalam sejarah perdagangan emas modern. Di Aceh sendiri, harga emas meningkat tajam hingga lebih dari Rp 7.000.000/mayam (November 2025), sehingga juga mendorong masyarakat memburu logam mulia ini secara masif.
Aktivitas tambang emas ilegal, yang bagi sebagian masyarakat tampak menguntungkan dalam jangka pendek semakin menguat dan bersamaan meningkatnya izin eksplorasi resmi pada 2024–2025, terlihat dari diterbitkannya 13 IUP Eksplorasi Emas dengan luas lebih >24.000 ha (DESDM Aceh, 2025). Kondisi harga dan munculnya izin baru memperkuat persepsi bahwa Aceh memiliki kandungan emas yang sangat besar. Karena itu, muncul kembali pertanyaan mendasar: Berapa Sebenarnya Potensi Emas Aceh Berdasarkan Kajian Ilmiah dan Data Eksplorasi Modern?
Diskusi mengenai potensi emas Aceh semakin menghangat setelah pernyataan Gubernur Aceh, Mualem, dalam forum internasional di Zhengzhou, Tiongkok (Oktober, 2025) menyebut potensi emas Aceh “mencapai 6 kali lebih besar dari Papua.” Pernyataan tersebut tidak dapat dipahami sebagai klaim matematis, tetapi lebih sebagai bentuk optimisme pemimpin terhadap masa depan perekonomian Aceh.
Meski demikian, dalam ilmu pertambangan modern, perlu disadari bahwa potensi berbeda jauh dari cadangan. Jurnal Economic Geology,2018 mencatat bahwa “mineral potential is a geological possibility, not an economic certainty,” atau potensi mineral adalah kemungkinan geologi, bukan kepastian ekonomi. Karena itu, optimisme harus ditopang oleh data eksplorasi yang sahih/rinci, sistematis, dan dilakukan pengujian laboratorium standar internasional sebelum disebut cadangan. Karena itu, evaluasi ilmiah diperlukan agar optimisme tidak menjauh dari realitas.
Sejarah emas Aceh
Secara historis, Aceh sudah lama dikenal salah satu kawasan penghasil emas di Nusantara. Catatan Tarich Atjeh dan Nusantara (Zainuddin,1961) menjelaskan bahwa Kerajaan Peureulak, Samudera Pasai dan Aceh Darussalam menjadikan emas sebagai komoditas strategis. Wilayah seperti Alue Meuh, Geumpang, Tutut serta Sungai Pasai dikenal pusat aktivitas penambangan emas.
Pada masa Sultanah Tajul Alam Syafiatuddin Syah (1641–1675), emas Aceh bahkan diperdagangkan ke Persia, India, Arab, Tionghoa hingga Inggris.
Sejarah ini menguatkan bahwa Aceh berada di jalur mineralisasi emas yang telah dimanfaatkan berabad-abad. Namun sejarah tidak dapat menjadi dasar pengukuran cadangan tanpa verifikasi eksplorasi modern.
Kajian Ore Geology Reviews (2020) mengemukakan bahwa Aceh berada dalam sabuk magmatik ”gold copper metallogenic belt of global significance”, suatu kesatuan geologi skala besar menghasilkan deposit porfiri dan epithermal dari Sumatera hingga Papua. Kondisi ini membuat Aceh secara geologi sangat prospektif, namun sebagaimana standar ilmiah tetap membutuhkan pembuktian eksplorasi rinci sistematis.
Jika menilik data eksplorasi resmi, hingga November 2025 baru 2 lokasi blok Aceh yang sumber daya emasnya terverifikasi secara internasional. Pertama, Miwah Gold Project di Pidie, yang telah merilis memiliki resource sebesar 3,14 juta ounce (2012). Kedua adalah Beutong Copper-Gold Project di Nagan Raya, yang berdasarkan memiliki sumber daya 2,4 juta ounce emas ditambah mineral tembaga signifikan (JORC,2018). Kedua blok emas Aceh ini menggunakan standar internasional NI 43-101 dan JORC dalam eksplorasinya. Jika digabungkan, total sumber daya emas Aceh terverifikasi mencapai 5,54 juta ounce. Di luar 2 blok tersebut, beberapa wilayah seperti Woyla, Linge, Gayo Lues, dan Aceh Barat menunjukkan indikasi geologi yang menjanjikan, tetapi hingga November 2025 belum memiliki estimasi sumber daya/cadangan terverifikasi nasional maupun internasional, sehingga secara teknis belum dapat dihitung sebagai cadangan emas Aceh.
Pada level nasional, data KESDM (2024–2025) menunjukkan Indonesia memiliki 2.600 ton cadangan dan sumber daya emas, setara ±83,6 juta ounce. Sebagian besar berasal dari Papua, khususnya Tambang Grasberg dan underground PT Freeport Indonesia. Dokumen resmi PT Freeport Indonesia (2024) menyebutkan 24 juta ounce cadangan terbukti dan 82 juta ounce sumber daya. Jika dibandingkan, emas Aceh yang terverifikasi (5,54 juta ounce), setara dengan sekitar 6–7 persen dari potensi Papua atau sekitar 6,6 % total cadangan emas nasional. Perbandingan ini bukanlah bentuk pengecilan, melainkan penempatan yang proporsional berdasarkan data eksplorasi yang telah tersedia. Dengan kata lain, pandangan optimistis pemimpin terhadap prospek Aceh dapat dipahami sebagai dorongan agar investasi eksplorasi emas dilakukan lebih serius.
Arah kebijakan
Pemerintah Aceh melalui kewenangannya telah menerbitkan 13 IUP eksplorasi emas 2 tahun terakhir dengan total luas ±24.000 ha. Namun seluruhnya masih berada pada tahap eksplorasi awal dan belum menghasilkan sumber daya maupun cadangan terverifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan izin tidak serta merta berbanding lurus dengan penemuan cadangan siap tambang. Jurnal Society of Economic Geologists,2019 menekankan bahwa deposit kelas dunia sering bermula dari estimasi awal yang kecil. Artinya, potensi Aceh tetap terbuka, namun butuh strategi eksplorasi kuat berkelanjutan.
Melihat kondisi tersebut, arah kebijakan mineral Aceh harus disusun dengan prinsip kehati-hatian dan orientasi jangka panjang. Pertama, Pemerintah Aceh melakukan seleksi ketat perusahaan eksplorasi, memastikan hanya perusahaan dengan rekam jejak global dan komitmen teknis dan lingkungan memadai yang diberi izin.
Kedua, Penguatan pengendalian ruang, agar aktivitas tambang tidak mengancam kawasan lindung dan daerah rawan bencana. Penelitian Tata Ruang UNDIP (Hardi, 2015) menegaskan bahwa pengendalian ruang pertambangan harus berbasis geologi, mitigasi risiko, dan konsistensi kebijakan ruang. Ketiga, Kewajiban advanced exploration terutama melakukan deep drilling, agar potensi mineralisasi epithermal/porfiri dapat dibuktikan secara ilmiah, bukan sekedar lembaran IUP saja. Hanya eksplorasi yang dapat mengonversi potensi menjadi sumber daya, dan sumber daya menjadi cadangan siap tambang. Keempat, Penertiban tambang emas ilegal melalui kombinasi penegakan hukum, pemberdayaan ekonomi, transformasi ke IPR serta edukasi lingkungan yang konsisten dari pemerintah.
Pada akhirnya, jawaban pertanyaan “berapa potensi emas Aceh sebenarnya” hanya dapat diperoleh melalui eksplorasi ilmiah terukur, tata kelola ruang yang disiplin dan keseriusan semua stakeholder. Bahwa Aceh memiliki sekitar 5,54 juta ounce sumber daya emas terverifikasi ini masih jauh dari fase produksi berskala besar. Angka awal tersebut dapat berkembang bila potensi mineral di seluruh Aceh dieksplorasi secara profesional. Optimisme masa depan tambang emas Aceh tentu penting. Namun optimisme ini perlu dibangun di atas fondasi ilmiah yang kuat, seleksi perusahaan yang kredibel dan komitmen tegas penertiban tambang ilegal.
engan tata kelola yang baik, Aceh berpeluang mengubah potensi menjadi cadangan siap diproduksi menjadi kesejahteraan masyarakat. Mengembalikan Aceh bukan hanya sebagai tanah emas dalam catatan sejarah, tetapi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi modern dan berkelanjutan.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Sekjend-PERHAPI-Aceh_Muhammad-Hardi_2025.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Humam-Hamid-Whoosh.jpg)







:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/M-Zubair-SH-MH.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Faizal-Adriansyah-RM-2025.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Abdul-Manan-BARU-LAGIi.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/apridarrr.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Akmal-Abzal-OKE.jpg)

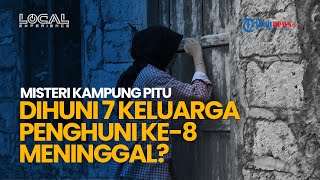
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Prof-M-Shabri-Abd-Majid-Prof-Bidang-Ilmu-Ekonomi-USK-Banda-Aceh.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Dr-Ainal-Mardhiah-SAg-MAg-Relawan-Banjir-Bandang-Aceh.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Bundaran-Simpang-Lima-Kota-Banda-Aceh_2026.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Ketua-KIP-Kota-Banda-Aceh-Yusri-Razali-03.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/T-A-SAKTI-II.jpg)