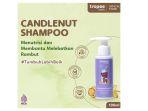Opini
‘Budaya Smong’ belum Sampai ke Palu?
DUKA kembali menyapa Indonesia. Gempa bumi berkekuatan 7,4 Skala Richter (SR) yang disertai gelombang tsunami
Oleh Sara Masroni
DUKA kembali menyapa Indonesia. Gempa bumi berkekuatan 7,4 Skala Richter (SR) yang disertai gelombang tsunami setinggi 5 meter menyapu Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat (28/9) lalu. Ini seakan mengulang kenangan pahit 14 tahun silam, ketika bencana serupa meluluh-lantakkan wilayah pesisir Aceh pada 26 Desember 2004 lalu. Bencana tersebut tidak saja menghilangkan harta benda, namun juga nyawa orang-orang tersayang ikut tersapu bersama ganasnya si gelombang raksasa itu.
Semua elemen masyarakat menyampaikan duka yang mendalam. Ucapan turut belangsungkawa terus berdatangan, baik dari sesama masyarakat bumi Pertiwi maupun dari negara sahabat. Hingga H+1 pascabencana, kondisi kota yang dipimpin Pasha Ungu (wakil walikota setempat) itu pun mencekam. Laporan BNPB sudah 384 orang meninggal dihantam amukan gelombang raksasa itu (Serambinews.com, 29/9/2018).
Angka tersebut kemudian terus bertambah, karena belum terdata seluruhnya. Jaringan komunikasi putus, listrik padam, mobil, bangunan, hingga sebuah kapal ikut melintang di tengah jalan akibat terseret arus tsunami.
Angka yang menyentuh ratusan akibat amukan gelombang besar ini bukanlah jumlah yang sedikit. Data itu baru data sementara yang dirilis oleh BNPB dan sepertinya akan terus bertambah selama beberapa hari ke depan. Kenapa masih tetap tinggi angka korban tsunami di Indonesia, padahal kita sudah pernah mengalami bencana yang sama. Satu jawabannya, kita belum belajar dari pengalaman.
‘Smong’ di Simeulue
Masih ingat dengan kata smong? Ya, mungkin sebagian masyarakat kita sudah lupa atau bahkan ada yang sama sekali belum mendengar kata tesebut. Smong berasal dari bahasa Simeulue, sebuah pulau sekaligus sebagai satu kabupaten di Aceh. Smong dalam bahasa lokal yang berarti imbauan agar masyarakat segera lari ke bukit setelah gempa terjadi, karena sebentar lagi air laut akan naik atau pasang, (Wardhani, 2011: 7).
Sebelum air naik saat tsunami 2004 lalu, masyarakat Simeulue sudah mengetahui bahwa gelombang besar akan datang. Mereka membaca tanda-tanda itu melalui surutnya air laut pascagempa dan ikan yang berserakan dipantai akibat kejadian tersebut. Penulis yang kebetulan masyarakat Simeulue, ingat betul bagaimana seorang paman saat itu memanggil para anak-anak yang mencoba mengumpul ikan berserakan pascagempa di pantai, agar segera naik ke gunung. Masyarakat Simeulue hampir di setiap desa tahu bahwa air surut pascagempa pertanda akan terjadi smong atau tsunami.
Diceritakan para orang-orang tua di sana, kejadian yang sama di Simeulue terjadi se-abad yang lalu, tepatnya 1907. Namun kearifan lokal membuat pengetahuan masyarakat di sana tentang mitigasi kebencanaan terus tersampaikan dari generasi ke generasi. Alhasil, hanya menewaskan 7 orang saja akibat amukan gelombang besar itu di sana (dalam sumber lain disebutkan 8 orang). Hal ini berbanding jauh dengan jumlah korban di berbagai daerah di Aceh (khususnya Banda Aceh dan Aceh Besar) yang menewaskan hampir 200 ribu orang.
Sekarang terjadi lagi bencana yang sama di Palu dan itu hanya selang 14 tahun pascatsunami Aceh. Belum sampai seperempat abad, tapi kita telah gagal menjadikan pengalaman kelam tentang tsunami Aceh dan mengembangkannya sebagai pengetahuan kebencanaan. Pengalaman tsunami 2004 lalu belum bisa diproyeksi menjadi sebuah keilmuan atau lebih ekstrem lagi dikelola menjadi budaya dan kearifan lokal, sebagaimana yang dipraktikan masyarakat Simeulue. Itulah kenapa penulis memberi judul artikel ini “Budaya Smong belum Sampai ke Palu?”.
Masyarakat Simeulue menuangkan pengalaman bencana tsunami melalui hikayat dan senandung yang dinyanyikan oleh para orang tua di sana ketika mengayun atau menidurkan bayinya. Sehingga pengetahuan tentang kebencanaan tidak hilang bahkan terlupakan walau bencana yang sama telah terjadi hampir se-abad lamanya. Menjadikan pengetahuan sebagai kearifan lokal. Ya, ini mungkin harus ditiru dan diaplikasikan daerah lain, agar angka korban jiwa akibat bencana tsunami dapat ditekan ke depan.
Manusia memang tidak bisa melawan takdir Allah Swt. Tetapi ingat, kita diberi kesempatan mengubah nasib atau keadaan jika kita berusaha dan berupaya mengubahnya (QS. Ar-Ra’d: 11). Untuk itu, berikut beberapa tawaran dari penulis agar pengetahuan kebencanaan ke depan bisa terus disampaikan dari generasi ke generasi.
Pertama, jadikan peringatan tsunami Aceh sebagai hari libur nasional dan diperingati secara nasional pula. Tanggal kejadian tsunami Aceh bisa jadi patokan, karena memang paling banyak memakan korban. Tujuannya agar menjadi pengingat bagi kita semua setiap tahunnya, sehingga mitigasi (perencanaan pengelolaan pengurangan risiko bencana) baik pra, sedang, maupun pascabencana dapat selalu tersampaikan dari generasi ke generasi.
Saat peringatan itu layaknya peringatan HUT RI yang di dalamnya ada berbagai lomba, kompetisi hingga cerdas cermat yang mengarah pada pengetahuan tentang sejarah tsunami untuk dijadikan pengingat ke depan.
Kedua, mengkampanyekan pengetahuan tsunami lewat karya. Ini bisa saja dengan membuat game online yang berbasis pengetahuan kebencanaan atau dengan membuat lagu dan hikayat sebagaimana yang dipraktikan masyarakat Simeulue tentang mitigasi tradisional mengurangi risiko bencana tsunami yang mengalir dan bermetamorforsis ke dalam budaya dan kearifan lokal.
Dan, ketiga, pengetahuan tentang kebencanaan khususnya tsunami, dimasukan saja ke dalam materi pelajaran Geografi (jurusan IPS) dan Fisika (jurusan IPA) kepada siswa SMP dan SMA sederajat. Pengetahuan ini dirasa sejalan dengan cabang ilmu kedua mata pelajaran tersebut, karena masih dalam satu rumpun keilmuan yang sama.