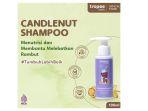Opini
IPAL Kota Banda Aceh
PEMBANGUNAN Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kota Banda Aceh telah dibahas oleh Pemko Banda Aceh
(Akibat Lupa Sejarah)
Oleh Izarul Machdar
PEMBANGUNAN Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kota Banda Aceh telah dibahas oleh Pemko Banda Aceh dan Kementerian PU sejak lima tahun lalu (Serambi, 20/9/2012). IPAL yang akan dibangun berupa sistem terintegrasi (off-site system) dengan satu sistem pengolahan limbah untuk setiap kawasan (zona).
Dari perencanaan awal, seluruh kawasan Banda Aceh akan terkoneksi dengan sistem perpipaan air limbah (sewerage system). Sistem perpipaan mirip dengan perpipaan PDAM. Pipa air limbah ini hanya membawa air limbah cair domestik dari dapur, kamar mandi, dan toilet. Pipa tidak dianjurkan terkoneksi dengan limbah cair medis, limbah industri, atau bengkel.
Sistem IPAL Kota Banda Aceh dibagi dalam empat zona, yang masing-masing memiliki unit pengolahan limbah tersendiri. IPAL di Gampong Pande yang sedang mejadi polemik saat ini merupakan IPAL untuk Zona-2, yang perencanaan awalnya akan mengolah sumber-sumber limbah cair penduduk dari sebagian Kecamatan Meuraxa, Kutaraja, Baiturrahman, Banda Raya, dan sebagian Kecamatan Kuta Alam. IPAL terintegrasi ini nantinya diharapkan meniadakan septic tank individu.
Kelebihan sistem terintegrasi dibandingkan dengan septic tank individu, di antaranya terjaminnya hasil olahan limbah, mengurangi pencemaran air bawah tanah (banyak septic tank bocor karena pengaruh gempa dan tidak terdeteksi karena bangunan berada di bawah tanah), mengurangi kasus water-borne diseases (penyebaran penyakit dari air), meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan, dan mengefektifkan area tanah (bayangkan luas area satu septic tank sekitar 3 meter persegi dikali dengan ribuan septic tank yang ada).
Pengolahan limbah secara terintegrasi bukanlah metode baru dalam perencanaan pengembangan suatu wilayah. Di negara-negara maju seperti Inggris, metode ini telah ada pada akhir abad ke-19. Di Jepang sendiri, sistem pengolahan limbah cair domestik telah dibangun pada 1884 di area Kanda, Tokyo. Saat itu, Aceh masih sibuk berperang dengan Belanda. Di Indonesia sendiri, ada 12 kota besar yang telah membangun sistem terintegrasi (Status and Challenges of Sewage Treatment System in Indonesia, Machdar, 2012). Tetangga kita, Kota Medan telah memulai sistem ini sejak 1980-an yang dikenal dengan nama Medan Urban Development Project.
Melihat dari sejarah ini, apa yang Pemko Banda Aceh lakukan saat ini untuk membangun IPAL memang terasa sangat terlambat. Tapi ini tidak menjadi halangan, karena kalau dibandingkan dengan kota-kota di kabupaten Aceh lainnya, Banda Aceh sudah bangun dari tidur dalam hal perbaikan sanitasi.
Lupa sejarah (pertama)
Dari sisi desain unit pengolahan limbah, strategi dalam memilih jenis IPAL Kota Banda Aceh termasuk kategori mengulangi kesalahan sejarah yang sama apa yang dialami oleh kota-kota lain di Indonesia. Diketahui bahwa, umumnya proses pengolahan limbah domestik secara terintegrasi di Indonesia menggunakan sistem aerobik (aplikasi mikroba memerlukan oksigen), seperti kolam aerasi (aerated lagoon atau aerated pond), activated sludge, dan rotating biological contactor. Kegagalan sistem ini disebabkan tidak sanggupnya pengelola (pemerintah kota) menyediakan biaya energi listrik untuk aerator. Akibatnya, banyak kolam aerasi dibiarkan begitu saja atau tanpa aerasi yang cukup, sehingga limbah tidak terolahkan dengan sempurna. Ciri-ciri kolam pengolahan limbah kekurangan aerasi adalah timbulnya bau yang menyengat.
Coba baca kembali berita Serambi, sejarah lima tahun yang lalu itu (20/9/2012), dalam pertemuan dengan Pemko Banda Aceh dan Kementerian PU, di sana disebutkan IPAL Kota Banda Aceh direncanakan akan terdiri dari sistem anaerobik bukan aerobik. Biaya operasional sistem anaerobik (aplikasi mikroba tanpa oksigen) relatif lebih murah, karena tidak menggunakan peralatan aerator, produksi lumpur yang rendah (mengurangi biaya pengolahan lumpur), dan sistem ini menghasilkan gas metana (sumber energi).
Tetapi, coba lihat apa yang kita lakukan sekarang. Desain IPAL Kota Banda Aceh menggunakan sistem Aerated Lagoon (kolam aerasi) yang terdiri dari dua unit kolam aerasi dan dua kolam maturasi. Selain lupa sejarah, ini jelas mengulangi sejarah yang sama dialami oleh kota lain di Indonesia, yang gagal mengelola IPAL. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa master plan awal bisa berubah?
Dari sisi konsultan perencana, mengopy desain yang telah ada lebih mudah dari pada membuat desain baru, apalagi tidak ada kompetensi di sana. Karena sistem aerobik telah ada di tempat lain, maka tinggal di-copy paste tanpa melihat keberlangsungan (sustainable) pengelolaan dari sistem yang ditiru.
Dari sisi pemko, mungkin lupa akan sejarah tentang komitmen pendahulu yang telah menetapkan sistem yang cocok untuk daerah ini. Membangun memang sedikit lebih mudah, apalagi dana berasal dari APBN. Tetapi merawat suatu bangunan yang telah ada lebih sulit, apalagi sumber pendanaan pemko yang pro-limbah masih di urutan ke sekian.
Lupa sejarah (kedua)
Dari awal perencanaan sistem IPAL Kota Banda Aceh telah disarankan untuk melakukan Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) secara komprehensif sebelum konstruksi dilaksanakan. Amdal di sini sangat penting guna mengidentifikasi dan mengantisipasi dampak lingkungan yang diakibatkan pembangunan proyek. Pekerjaan pemasangan perpipaan IPAL saat ini mirip seperti pada proyek drainase pada 2010 (Project: Flood Protection & Urban Drainage, Banda Aceh). Proses pembangunan drainase saat itu begitu meresahkan karena sangat mengganggu aktivitas masyarakat, baca (lagi) sejarah (Serambi, 20/12/2010).
Rusaknya situs yang diklaim sebagai bagian sejarah Aceh di Gampong Pande, karena penggalian proyek IPAL telah menimbulkan kegaduhan dan saling tuding. Padahal kalau mau dilihat, proyek ini tidak lahir dengan sendirinya. Ada proses panjang dan melibatkan beberapa sektor di Pemko Banda Aceh. Parahnya lagi, kalau sudah masuk orang politik, tanpa pikir panjang terus menyimpulkan proyek harus dihentikan tanpa mempertimbangkan untuk apa proyek itu dibuat dan manfaatnya. Mencari “kambing hitam” bahwa IPAL salah lokasi atau menghentikan proyek, ini tentu bukan penyelesaian yang diharapkan.