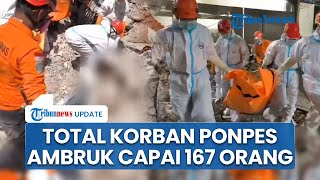Kupi Beungoh
Pendekatan Militer sebagai Resolusi Konflik di Papua, Tidakkah Pemerintah Belajar dari DOM Aceh?
Dua konten dalam satu konteks yang sama dituturkan oleh dua orang yang turut melewati konflik dan resolusi konflik di Aceh.
Oleh: Ulta Levenia
MENTERI Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan bahwa tidak ada negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 17 Desember 2018.
Selain itu Wiranto menegaskan bahwa tidak akan ada negosiasi antara pemerintah dengan OPM, karena posisi antara negara dan kelompok kriminal tersebut berbeda.
Respon Wiranto ini terkait dengan kasus penembakan sejumlah pekerja PT Istaka Karya pada 2 Desember 2018 di Nduga.
Pada kesempatan lain, Jusuf Kalla berargumen bahwa permasalahan yang diangkat oleh OPM tidak jelas dan tidak nyata.
Karena Pemerintahan Jokowi-Kalla telah menguncurkan dana lebih dari Rp 100 triliun per tahun untuk pembangunan infrastruktur.
Kalla juga menyinggung bahwa nilai yang dikucurkan Pemerintah Pusat ke Papua tidak sebanding dengan sumbangsih saham PT. Freeport Indonesia ke pemerintahan pusat.
Dua konten dalam satu konteks yang sama dituturkan oleh dua orang yang turut melewati konflik dan resolusi konflik di Aceh.
Baca: Jusuf Kalla Diusulkan Menjadi Ketua Juru Damai Papua
Baca: Jusuf Kalla Tanggapi Soal Survei 41 Masjid Terpapar Radikalisme: Ini Studi yang Memprihatinkan
Pada tahun 2013, Wiranto menyebutkan bahwa pada masa Presiden Habibie dirinya menginjakkan kaki di Aceh dan memberikan saran untuk menghentikan operasi militer di Aceh.
Untuk diketahui, kala itu Aceh berstatus sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).
Sedangkan Jusuf Kalla, merupakan key actor yang berperan dalam penandatanganan MoU Helsinki yang menandai berakhirnya konflik bersenjata di Aceh.
Peace Talks
Jika Wiranto mengusulkan DOM Aceh dihentikan, serta Jusuf Kalla yang berupaya mencapai kesepakatan dengan perundingan, maka muncul pertanyaan, apakah tindakan yang melibatkan dua tokoh ini di Aceh tidak dapat diterapkan di Papua?
Pertama, kembali pada respon Wiranto terhadap tindakan OPM yang dinilai harus ditindak tegas tanpa negosiasi.
Baca: Beberkan Perkembangan Terbaru KKB, Wiranto: Kita Tahu Kekuatan Mereka, Tinggal Selesaikan Aja
Baca: Buru Kelompok Bersenjata di Pedalaman Papua, Brimob Hancurkan Markas KKB yang Baru Dibangun
Permasalahan “posisi” non-state and state actors antara negara dan kelompok kriminal (separatis) yang bertujuan untuk memisahkan diri dengan menguasai sebagian wilayah yang secara konstitusional dan diakui oleh internasional merupakan permasalahan umum yang selalu ada pada upaya resolusi konflik.
Oleh karena itu, biasanya diskusi perdamaian (peace talks) antara non-state actors and state actors selalu dilakukan melalui pihak ketiga atau third party yang menjadi jembatan penghubung kepentingan kedua pihak yang berkonflik.
Hal ini terbukti dengan kasus proses perdamaian antara GAM dan Indonesia, MNLF/MILF dan Filipina, LTTE dan Srilanka, dan contoh lainnya.
Baca: Dipimpin Abunawas, Delegasi Moro Islamic Liberation Front (MILF) Belajar Implementasi Damai ke Aceh
Namun pemerintah selalu berdalih bahwa organisasi yang akan menjadi lawan diskusi mereka adalah organisasi kriminal, sipil bersenjata, hingga teroris, untuk menghindari label insurgents atau intermittent insurgents.
Label terhadap organisasi ini sangatlah dinamis.
Pada awal tahun 2000, merebaknya organisasi radikal di dunia, menempatkan GAM, MILF, MNLF, Taliban, dan lainnya sebagai organisasi teroris.
Pelabelan ini berdampak pada pendekatan koersif bersifat militeristik pemerintah terhadap organisasi yang dianggap sebagai teroris.
Lalu, pada tahun 2010 ditemukan 18% dari organisasi yang dikategorikan sebagai teroris melakukan diskusi perdamaian dengan pemerintah.
Karenanya, pendekatan ini terbukti tidak efektif untuk menuntaskan dan menghilangkan resistensi kelompok tersebut.

Misalnya, kebijakan keras mantan Presiden Filipina Joseph Estrada yang mengumumkan all out war melawan MILF, tidak terbukti berhasil menghapuskan organisasi tersebut dari tanah Filipina Selatan.
Kemudian akhirnya pemerintah dan organisasi separatis tersebut berunding dan melakukan proses gencatan senjata (ceasefire).
Proses ini tidak serta merta selesai dalam waktu singkat, hingga saat ini MILF masih menjalani proses ceasefire dengan pemerintah Filipina.
Berbeda dengan kasus Aceh yang proses gencatan senjata cepat dilakukan pascapenandatanganan MoU Helsinki.
Menurut amatan penulis, kondisi istimewa ini karena faktor bencana alam yang mendesak elit-elit GAM untuk “menyerahkan senjata” demi rakyat Aceh.
Kembali ke kasus Papua, penulis melihat respons Wiranto yang mengumumkan penanganan OPM tanpa diskusi, diikuti pengerahan lebih kurang 500 pasukan gabungan TNI-Polri untuk membasmi OPM, merupakan contoh bahwa Wiranto tidak belajar dari kasus Aceh.

Baca: BangsaMoro dan Pattani Belajar Damai ke Aceh
Baca: Myanmar Belajar Damai ke Aceh
Hal ini juga menunjukkan Wiranto telah menurunkan level OPM di bawah GAM, sehingga tidak pantas untuk dibuka ruang diskusi.
Namun apa indikator pantas dan tidak pantasnya suatu organisasi dibukakan ruang diskusi?
Yang paling utama adalah dukungan internasional atau atensi internasional terhadap organisasi tersebut.
Jika dibandingkan dengan GAM, OPM lebih minim dukungan internasional, walaupun kekerasan militer dan pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Aceh juga terjadi di Papua, tanpa memandang jumlah korban, adalah indikator eskalasi pelanggaran.
Temuan Amesty Internasional pada tahun 2018, terdapat 95 korban dari 69 kasus pembunuhan di luar hukum yang tercatat atau terpantau di Papua.
Minimnya akses internasional terhadap kasus di Papua, karena hingga tahun 2015 pemerintah melarang jurnalis asing untuk mendatangi Papua, meskipun kemudian di buka tetap harus memiliki izin tertentu dan diawasi oleh aparat keamanan.
Saat ini, dukungan, relasi, dan atensi aktor internasional dan OPM masih tergolong minim.
Hal ini juga dengan ukuran dan momen yang mendukung, artinya dukungan, relasi, dan atensi baik antara OPM atau Indonesia dan kelompok internasional merupakan hubungan dinamis berjangka.
Selama Indonesia masih mampu menjaga dominasi spektrum hubungan internasional dengan negara-negara yang berpotensi mampu memberikan dukungan terhadap internasionalisasi isu Papua, maka atensi internasional masih terpaku pada perspektif penanganan extra-ordinary crime yang diterapkan terhadap OPM.

Baca: Kirim Surat Terbuka ke Jokowi, Kelompok Bersenjata Papua: Tuan Presiden, Perang Tidak Akan Berhenti
Kemudian, mengulas respon Jusuf Kalla yang menuturkan bahwa, jika OPM menuntut kemerdekaan karena merasa dieksploitasi oleh pemerintahan Indonesia dan PT. Freeport Indonesia, maka hal tersebut adalah salah.
Nyatanya pemerintahan Jokowi-Kalla memulai proyek infrastruktur besar-besaran dengan menggelontorkan APBN sebesar Rp 100 triliun yang mana pada pemerintahan sebelumnya tidak pernah dilakukan.
Sedangkan PT Freeport Indonesia hanya menyumbang sekitar Rp 10 triliun kepada pemerintah pusat.
Pada perspektif Pemerintah Indonesia, pendekatan pertumbuhan ekonomi akan efektif mengurangi resistensi rakyat Papua untuk merdeka.
Namun kenyataannya hal ini adalah hal ini merupakan upaya yang terlambat tetapi tidak sia-sia.
Pembangunan infrastruktur dengan tujuan pertumbuhan ekonomi di Papua dinilai oleh OPM bukanlah untuk rakyat Papua (pribumi) dan dinyatakan tidak akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Papua.
Hal ini beberapa kali diulang-ulang oleh juru bicara OPM Sebby Sambom.
Sambom tidak sepenuhnya salah, dan pemerintah tidak sepenuhnya benar.
Sambom menyatakan hal tersebut dengan berdasarkan kenyataan bahwa lahan-lahan dan sumber daya yang menjadi fondasi perekonomian rakyat Papua pada umumnya dikuasai oleh pendatang.
Karena pendatang ini memiliki kapabilitas tinggi dengan modal, akses, dan kemampuan (skill) untuk memanfaatkan anggaran pertumbuhan ekonomi Papua oleh pemerintah beserta infrastruktur yang mendukungnya.
Kondisi tersebut akan membuat rakyat Papua menjadi masyarakat nomor 2 sebagai pekerja yang tidak memiliki asset, yang berujung pada dependensi rakyat Papua kepada pendatang.
Hal ini kemudian menjadi indikator yang melatarbelakangi OPM untuk menolak segala bentuk negosiasi dengan pemerintah pusat selain kemerdekaan Papua.
Namun di sisi lain, Pemerintah Indonesia tidaklah salah melakukan pembangunan infrastruktur, karena memang kewajiban pemerintah membangun Papua dan memanfaatkan APBN maupun APBD.
Seharusnya Belajar dari Aceh
Kesimpulannya, entah dengan kesiapan militer apa yang dimiliki oleh OPM menghadapi operasi militer TNI-Polri yang dikerahkan pemerintah Indonesia.
Tetapi seharusnya pemerintah belajar dari kasus pemberontakan di Aceh maupun negara lain yang memiliki nuansa serupa, bahwa pendekatan militeristik tidak akan pernah menjadi resolusi konfik yang tepat.
Tindakan militer tidak akan membunuh keinginan OPM untuk memerdekakan diri dari Indonesia.
Kemudian, mengingat biaya kemanusian (humanity costs) yang tinggi dengan penerapan operasi militer menghadapi OPM karena organisasi tersebut berbaur dengan masyarakat sipil, maka pendekatan militer kemudian menjadi ancaman faktual Hak Asasi Manusia (HAM).

Selanjutnya optimalisasi pembangunan infrastruktur juga perlu diiringi dengan pembangunan sosial dengan kebijakan afirmasi dan menjaga aset-aset milik pribumi untuk tidak dapat dimiliki atau dieksploitasi oleh imigran.
Berhubung dengan sumber daya alam Papua yang dibutuhkan oleh pelaku ekonomi, maka perihal ini dapat dirumuskan dengan kebijakan yang adil, tanpa mengurangi pertumbuhan perekonomian di Papua.
*) PENULIS adalah Peneliti Centre of Terrorism and Radicalism Studies (CTRS)
KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.