Kupi Beungoh
Jalan Terjal Gubernur Aceh 2024-2029 : Aceh-Jakarta, Paradigma Aceh Pungo, Jawa Sopan - Bagian XX
Dalam kluster jarak kekuasaan rendah pembicara dan lawan bicaranya tahu bahwa kata-kata itu berarti persis seperti apa yang mereka katakan.
Ahmad Humam Hamid *)
Berbeda dengan Indonesia, Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam, negara-negara Eropah, Afrika, AS, dan sejumlah kawasan Asia tergolong memiliki jarak kuasa rendah.
Di negara-negara dalam kluster jarak kekuasaan rendah, Hofstede memberikan ciri yang sebaliknya, menekankan kesetaraan, komunikasi lebih informal, dan individu merasa nyaman menantang otoritas.
Komunikasi dalam kluster ini mungkin terasa lebih mudah terlibat dalam dialog terbuka.
Dalam kluster jarak kekuasaan rendah pembicara dan lawan bicaranya tahu bahwa kata-kata itu berarti persis seperti apa yang mereka katakan.
Sebaliknya dalam budaya jarak kekuasaan tinggi, makna kata-kata diambil dari konteks proses komunikasi yang berjalan. Dalam kluster ini, kata-kata sangat berpeluang tidak pernah berarti seperti apa yang dikatakan.
Saya pernah berdiskusi dengan beberapa orang yang dekat, dan bahkan sangat dekat dengan ketiga gubernur Aceh itu- Hasymi, Muzakir, dan Ibrahim tentang pola komunikasi mereka dengan “Aceh” dan “Jakarta.”
Mereka bertiga tahu benar “medan” yang dihadapi. Kapan harus dan bagaimana bertindak dalam dua lapangan dan tantangan yang berbeda.
Tanpa harus menggunakan indikator dan skala Hofstede, untuk pengukuran jarak kekuasaan di Aceh, sepertinya Aceh masuk dalam kategori kluster jarak kekuasaan yang rendah.
Apa ukurannya? Budaya egaliter Aceh tidak memberi jarak kekuasaan yang terlalu tinggi kepada penguasa mempunyai persoalan tersendiri pula.
Tak jarang yang diperintah, bahkan rakyat sekalipun berani melawan penguasa dengan menantang mulai dări yang cara sopan, atau bahkan juga kasar sekalipun.
Hal ini dapat dimengerti,karena ada akar sejarah panjang tentang”kepemilikan” Aceh.
Ambil saja contoh, ketika Sułtan Mohamad Daud berdamai dan “menyerah” kepada Belanda pada 1903, Aceh tetap melawan, karena para raja kecil, dan hulu balang mengambil alih.
Bersamaan dengan para hulubalang, para Ulama juga ikut berperang. Ketika Jenderal Van Huestz berhasil “memaksa” para hulu balang pada 1904 untuk menanda tangani plakat “korte verklaring”-perdamaian pendek pada 1904, rakyat tidak setuju.
Mereka tetap melawan. Ada perlawanan kelompok di hampir semua tempat di Aceh, dan sangat sering ada perlawanan individu, hanya karena ingin mati terhormat dan syahid.
Salah satu akar utama egaliter masyarakat Aceh berasal dari fakta sosiologis ini, yang menyatakaan, “kami rakyat” tidak berbeda jauh dari ‘kalian” para elitę kekuasaan dań ułama, ketika kami dihadapkan dengan kehormatan dan agama.
Apa artinya ini semua ? Ingatan bawah sadar rakyat Aceh yang kemudian mengumpal menjadi fakta kultural adalah, bahwa Aceh ini milik semua, ada rakyat dan ada elit, tanpa pemeringkatan yang menononjol kecuali “sedikit” tanda dan rasa hormat kepada pemimpin.
Refleksi akar egaliter Aceh menjadikan komunikasi dalam melaksanakan pemerintahan harus dilakukan dengan cara Aceh.
Secara kultural ini adalah komunikasi konteks rendah. Yang dimaksud adalah model komunikasi yang bersifat langsung, apa adanya, lugas tanpa berbelit-belit atau yang biasa kita kenal dengan cara bicara blak-blakan. Tepatnya bicara “to the point” dan tidak ada basa-basi.
Memang, sekalipun untuk ketiga mereka, model komunikasinya dapat digeneralisasikan , namun setiap mereka mempunyai keunikan tersendiri.
Muzakir dan Ibrahim mempunyai banyak kemeripan dalam hal sopan santun, dan ketika saatnya keras, dan kasar. Hasymi jarang bahkan tidak menggunakan kata, dan bahkan ekspresi, tetapi ia akan bertindak dengan sangat lugas dan tegas.
Dalam komunikasi konteks rendah, pada kepemimpinan Aceh, tak jarang melekat istilah “tungang” yakni komunikasi tahan banting dengan menggunakan jargon-jargon yang merefleksikan kasar, dan bahkan sangat kasar.
Sang pemimpin tidak pernah menyembunyikan apa yang dimaksudkannya kepada bawahannya, ataupun kepada rakyatnya. Lagee crah meunan beukah- sampaikan asli apa adanya, adalah rangkuman istilah blak-blakan.
Komunikasi pemimpin Aceh yang disebut “tungang”, bahkan menggunakan istilah “aceh pungo”- aceh gila, “pue yang katem kutem,”- apa yang kau mau aku mau- “ pat kapreh”, -dimana kau tunggu “ pue galak kah, get na brok chit lee?- kau boleh suka apapun, cara baik ada, cara buruk pun tak kurang.
Semua istilah itu dapat dimengerti, karena kadang bahasa isyarat tak cukup, dan ketika sampai pada sebuah titik tertentu dinyatakan dengan lugas, baik dalam kata , nada, maupun ekspresi.
Menariknya, Hasymi ,Muzakir dan Ibrahim memang sangat sopan dan bersahaja, tetapi ketika sampai pada sebuah titik, berbagai kata, nada, bahasa tubuh akan benar-benar eksplosif.
Namun harap diingat, semua itu hanya berlaku di Aceh dalam konteks Aceh.
Mereka perkasa, bahkan sangat perkasa dengan kompetensi komunikasi Acehnya yang mumpuni. Semua keperkasaan dan “tungang” dalam komunikasi mereka di Aceh dengan sangat sadar mereka tanggalkan ketika mereka mendarat di Jakarta.
Mereka sangat sadar akan status mereka baik sebagai kepala daerah, maupun sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Mereka tahu apa arti “relasi kekuasaan” antara yang diatas dan yang dibawah.
Pada masa itu mereka- Hasymi, Muzakir, dan Ibrahim- belum membaca buku-buku hebat yang menjelaskan perspektif kebudayaan dalam kekuasaan dan relasi kekuasan nasional yang secara “defacto” hanya dapat dimengerti dalam konteks “budaya jawa”.
Walaupun ketiga mereka adalah pembelajar ulung, kecuali Ibrahim, kedua pendahulunya Hasymi dan Muzakir tak mendengar dań punya kepustakaan canggih untuk pengetahuan komunikasi lintas budaya, apalagi dalam konteks komunikasi politik dan kekuasaan di Indonesia.
Namun, baik Hasymi, Muzakir, dan Ibrahim, seakan telah membaca keniscayaan bahasa, komunikasi, dan kekuasaan simbolis, dalam ineteraksinya dengan “Jakarta”.
Seakan mereka telah membaca dan menghayati deskripsi Piere Bourdieu,sosiolog kondang Perancis dalam buku Language and Symbolic Power (1993) tentang bahasa, “pasar lingusitik” dan kekuasaan.
Kalau saja mereka masih hidup hari ini, mereka akan sangat terkejut , karena apa yang mereka praktekkan ketika para gubernur Aceh itu berurusan dengan “Jakarta” dahulu justeru ditulis dengan baik oleh Bourdieu, sosiolog kondang Perancis yang menggunakan istilah “pasar bahasa” yang seperti pasar lainnya, tidak pernah menjadi “pasar bebas” karena ada hubungan kekuasaan didalamnya.
Ketika para gubernur itu berurusan dengan Sukarno, maupun Suharto, mereka tahu benar stadar dan alokasi kata dan kalimat yang berlaku dalam “pasar bahasa” kekuasaan itu, terutama bila dikaitkan dengan budaya dominan dalam kekuasaan.
Ketika Muzakir dan Ibrahim berkomunikasi dengan pak Harto, mereka sangat paham bahwa kesopanan tidak hanya terletak dalam kalimat dan kata, namun sikap dan perilaku non bahasa jauh lebih penting.
Mereka mungkin tak pernah tahu ada istilah “kramanisasi,” sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Benedict Anderson (1990) , profesor ilmu politik dan sejarah Universitas Cornel.
Anderson menggambarkan bahwa ada ” stratifikasi bahasa” yang sangat canggih dalam praktek politik, pemerintahan, bahkan pembangunan di Indonesia. Secara tak sadar mereka melakukan persis seperti apa yang diuraikan oleh Anderson itu.
Kita tidak tahu apakah ketiga mereka sadar atau tidak, bahasa Indonesia, yang berasal dari bahasa melayu lisan-bicara, yang di oleh Hamzah Fansuri di “jadikan bahasa tulisan dalam perjalaannya telah mengalami evolusi.
Hal itu terjadi karena berkaitan dengan sebuah negara kebangsaan dengan keragaman budaya yang luar biasa.
Sadar atau tidak ketiga mereka -Hasymi, Muzakir, dan Ibrahim, yang berasal dan memerintah dalam budaya rendah jarak-kekuasaan dan egaliter telah mampu beradaptasi dengan “Jakarta,” dalam penggunaan bahasa Indonesia-melayu yang telah berevolusi.
Ketika mereka berinteraksi dengan Jakarta, secara perlahan dan sadar mereka mulai terbiasa berpindah dari bahasa egaliter dan demokratis yang umumnya dipraktekkan sebelum Indonesia merdeka dan di Aceh, menjadi bahasa Indonesia dengan “tuturan tingkat rendah” dan “tuturan tinggi,” seperti yang terdapat dalam bahasa Jawa.
Hasymi, Muzakir, dan Ibrahim yang hidupnya antara sekolah, belajar, dan pembelajar, sangat beruntung mempunyai kekayan intelektual yang membuat mereka sangat paham tentang hubungan bahasa, kekuasaan, dan politik, seperti yang disinggung oleh Bourdieu.
Karena kesadaran itu, setiap komunikasi mereka yang berurusan dengan “Jakarta,” mereka menggunakan sumber daya lingusitik mereka dalam “pasar bahasa” yang tak bebas.
Mereka menyesuaikan kata, kalimat, dan bahasa tubuh mereka dengan tuntutan lingkungan “Jakarta” yang menurut deskripis Hofstede (1983) di dominasi oleh budaya jarak kekuasaan tinggi.
Disinilah mereka dengan sangat sadar mempraktekkan cara -cara penggunaan bahasa bervariasi menurut pertimbangan lingkungan, utamanya stratifikasi.
Karena hubungan yang mereka perankan adalah hubungan “aceh” dan “jakarta” berada dalam ranah kekuasaan dan politik, mereka sangat sadar dimana kata-kata, kalimat, dan bahasa tubuh, adalah karakter simbolis dimana kekuasaan dipertaruhkan.
Penguasaan prinsip itulah yang menjadi modal besar mereka dalam berinteraksi dengan presiden dan para pembantunya.
Apakah dengan demikian, pemimpin Aceh harus menjadi “jawa”? Jawabanya ya, namun ada tambahannya, menjadi “Jawa yang sopan”, berlaku dan hanya berlaku di Jakarta.
Bagaimana kalau sang gubernur kembali ke Aceh? Seperti halnya ketika pesawat mendarat di Jakarta, begitu langkah pertama mereka menginjak bumi Cengkareng, sang gubernur segera berobah menjadi “ Jawa Sopan,” hal yang sama juga harus terjadi di Aceh.
Ketika pesawat mendarat di lapangan terbang Iskandarmuda, segera sang gubernur kembali menjadi Aceh, dan dimana perlu wajib menjadi “Aceh pungo.”
Bagaimana seandainya perilaku “Aceh Pungo” dibawa ketika berinteraksi dengan Jakarta. Ketika pertanyaan itu diajukan oleh seorang yang “beriman” tentang kehebatan dan kedigdayaan Aceh, maka jawabannya sangat sederhana.
Kalau perilaku “Aceh Pungo” dibawa dalam interaksi dengan “Jakarta” maka hasılnya adalah “puleh pungo”.
Apakah anda tak percaya? Lihat saja perilaku gubernur dan DPRA ketika berinteraksi dengan “jakarta” semenjak berlakunya UUPA no 11 tentang otonomi khusus. Bukankah mayoritas dari mereka “puleh pungo” ?
*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar USK
KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.
Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI
| Dibalik Kerudung Hijaunya Hutan Aceh: Krisis Deforestasi Dan Seruan Aksi Bersama |

|
|---|
| MQK Internasional: Kontestasi Kitab, Reproduksi Ulama, dan Jalan Peradaban Nusantara |

|
|---|
| Beasiswa dan Perusak Generasi Aceh |

|
|---|
| Menghadirkan “Efek Purbaya” pada Penanganan Stunting di Aceh |

|
|---|
| Aceh, Pemuda, dan Qanun yang Mati Muda |

|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Sosiolog-dan-Guru-Besar-USK_Prof-Ahmad-Humam-Hamid_2024.jpg)







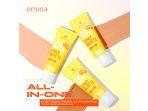







Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.