Opini
Konflik Manusia dan Satwa di Aceh
BERDASARKAN data dari BKSDA Aceh yang terpublikasi melalui Mongabay 27 Desember 2023, dari 2019 hingga Oktober 2023
Dede Suhendra, Pegiat Lingkungan Hidup
BERDASARKAN data dari BKSDA Aceh yang terpublikasi melalui Mongabay 27 Desember 2023, dari 2019 hingga Oktober 2023, jumlah konflik manusia dan satwa khususnya Gajah Liar (Elephas Maximus Sumatranus) mencapai 583 konflik. Rinciannya 2019: 106 konflik, 2020: 111 konflik, 2021: 145 konflik, 2022: 136 konflik dan 2023: 85 konflik.
Data di atas, bisa disimpulkan bahwa konflik manusia dan Gajah Sumatera terjadi setiap tahun di Provinsi Aceh, walaupun berfluktuasi naik dan turun. Hal lain konflik terjadi pada wilayah yang sama, pola dan modelnya juga sudah bisa dipetakan.Begitu pula dengan instrumen hukum yang sudah ada, dari yang terbaru seperti Undang-Undang-Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Salah satu perubahannya terkait dengan sanksi pidananya yang semakin berat. Lainnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di Aceh sendiri ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh hingga Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Satwa Liar.
Di tingkat tapak sudah pula dikembangkan berbagai upaya mulai dari penggunaan teknologi seperti, power fencing (pagar kejut Listrik), penanaman tanaman sebagai barrier serta penataan berbasis kawasan koridor.
Faktanya konflik masih tetap terus terjadi setiap tahunnya di Aceh. Tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa terus berlangsung sementara berbagai upaya juga telah dilakukan? Apakah upaya-upaya tersebut belum cukup? Atau apakah upaya-upaya tersebut tidak tepat? Berbagai pertanyaan ini sesungguhnya tidak hanya ditujukan pada situasi di Aceh tetapi secara umum di Indonesia.
Mengubah cara pandang
Cara pandang yang salah adalah penyebab konflik tetap terus terjadi. Lebih jauh cara pandang yang salah ini berhubungan dengan posisi antara manusia dan satwa serta berbagai komponen makhluk hidup lainnya. Selama ini, dalam melihat konflik manusia dan satwa liar, selalu dilihat dari sisi kebutuhan atau kepentingan manusia. Sementara satwa dianggap musuh, pengganggu, hama dan pendatang yang mengganggu keberadaan manusia sehingga kemudian perlu diusir, dikeluarkan bahkan ada juga yang menyebutnya diberantas. Selain itu ada kata-kata yang sering muncul “mana lebih penting manusia atau satwa”.
Inilah yang kemudian sering disebut dengan cara pandang Antroposentrisme, dimana manusia dianggap menjadi titik sentral dalam hubungannya dengan makhluk hidup lainnya seperti satwa, tumbuhan dan komponen ekologi lainnya. Pendekatan ini kemudian menjadikan manusia sebagai penguasa, bahkan pemilik sumber daya alam yang bisa digunakan untuk sesuka hati. Melakukan kegiatan ekonomi pada wilayah tertentu untuk alasan kebutuhan sumber kehidupan sering dilakukan tanpa mempertimbangkan dan tidak memperdulikan bahwa lahan yang dikelola adalah jalur satwa. Akibat dari cara pandang yang salah, maka posisinya satwa harus terpinggirkan. Inilah cara pandang yang salah dan saat ini sudah ditinggalkan oleh dunia.
Untuk itu cara pandang tersebut harus diubah, dimana cara pandang yang harus di bangun adalah cara pandang yang menempatkan semua makhluk hidup dalam konsep ekologi memiliki ruang yang setara dan adil. Membangun mitigasi konflik dengan menempatkan cara pandang yang setara antara manusia dan satwa, bisa menjadi solusi untuk memastikan kawasan-kawasan satwa sebagai tempat tinggal mereka juga tetap terjaga dan mereka tetap bisa menggunakannya. Jika ini dilakukan, maka konflik manusia dan satwa sesungguhnya bisa diatasi.
Hidup berdampingan
Selanjutnya adalah mengembangkan strategi dan model pengelolaan hidup berdampingan atau koeksistensi. Konsep utama dari koeksisten dalam kerangka ekologi adalah adanya kondisi dimana semua komponen makhluk hidup khususnya manusia, satwa dan tumbuhan bisa hidup berdampingan secara damai. Ruang hidup yang ada ditinggali secara harmoni oleh berbagai komponen makhluk hidup berlandaskan prinsip kesetaraan dan keadilan.
Dalam kerangka itu, maka konsep hidup berdampingan dalam rangka memberikan solusi pada konflik manusia dan satwa adalah adanya pengakuan dan penghormatan atas ruang masing-masing, baik ruang kehidupan manusia, satwa dan tumbuhan. Manusia harus mengakui dan menghormati ruang satwa yang sering dikenal dengan kawasan tempat populasi satwa menjalankan kehidupannya, demikian pula sebaliknya. Konsep ini tidak dimaknai bahwa manusia boleh keluar masuk sesuka hati ke ruang satwa atau mengambil alih ruang satwa. Ini adalah konsep yang salah terkait hidup berdampingan.
Hidup berdampingan menghendaki manusia dan satwa saling menghormati ruang yang tersedia tanpa intervensi pada kawasan tersebut. Jika terlaksana sesungguhnya secara alami akan terwujud penghormatan, dikarenakan konsep hidup berdampingan dilandasi dengan adanya pengakuan, penghormatan, kesetaraan dan keadilan. Inilah hakekat dari hidup berdampingan. Jika model ini bisa diterapkan konflik manusia dan satwa bisa dimitigasi secara baik, ini akan bisa mengurangi hingga menuju titik nol konflik.
Dalam berbagai instrumen hukum yang ada di Indonesia, diksi yang digunakan untuk menggambarkan kondisi antara manusia dan satwa adalah konflik bukan interaksi. Dalam skala global juga menggunakan diksi konflik dan ini terangkum dalam istilah yang kemudian disebut human wildlife conflict (HWC). Diksi ini digunakan untuk memperjelas adanya posisi yang saling bertikai atau berkelahi untuk memperebutkan kawasan. Penggunaan diksi ini akan melacak bagaimana situasi dan penyebab terjadinya.


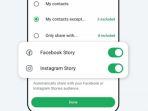











![[FULL] Demo Buruh Kepung Senayan, Said Iqbal: DPR Parah, RUU Setahun Panja Doang, Kasihan Presiden](https://img.youtube.com/vi/TGRtOGQV2Z4/mqdefault.jpg)





Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.