Opini
Memanfaatkan Agglomeration Economies sebagai Lokomotif Baru Pemerataan Ekonomi Aceh
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh per Maret 2023 menunjukkan, tingkat pengangguran terbuka masih berada di angka 5,21%,
Oleh: Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK dan Ketua Dewan Pakar ICMI Orwil Aceh
ACEH, sebuah negeri yang sarat dengan sejarah gemilang, kekayaan alam melimpah, dan ketangguhan masyarakatnya yang legendaris, hingga hari ini masih berjibaku dengan tantangan klasik pembangunan: kesenjangan antara wilayah pesisir dan pedalaman, serta ketergantungan pada sektor tradisional yang rentan fluktuasi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh per Maret 2023 menunjukkan, tingkat pengangguran terbuka masih berada di angka 5,21 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Sementara itu, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh masih jauh di bawah potensi yang dimilikinya.
Dalam konteks inilah, sebuah konsep ekonomi yang telah terbukti mendorong lompatan kemajuan di berbagai belahan dunia “agglomeration economies” perlu dijadikan arsitektur utama dalam perencanaan pembangunan regional Aceh.
Baca juga: Pasar Keuangan yang Likuid dan Cost of Fund Rendah Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
Konsep ini merujuk pada manfaat ekonomi yang timbul ketika perusahaan, industri, dan tenaga kerja terkonsentrasi secara geografis. Manfaatnya beragam, mulai dari pengurangan biaya logistik dan transportasi, akses yang lebih mudah ke pasar dan tenaga kerja terampil, hingga yang terpenting: transfer pengetahuan dan inovasi yang terjadi melalui kedekatan fisik.
Pertanyaannya, bagaimana Pemerintah, baik pusat maupun daerah dapat secara bijak memanfaatkan konsep ini untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan merata, khususnya di wilayah-wilayah tertinggal di Aceh?
Membaca Ulang Potensi Aceh Melalui Lensa Agglomeration
Sebelum merancang kebijakan, kita harus jernih melihat potensi unggulan Aceh yang dapat menjadi benih bagi tumbuhnya kluster industri. Selama ini, ekonomi Aceh seringkali disederhanakan pada komoditas minyak dan gas alam serta perkebunan kelapa sawit. Padahal, ada banyak potensi yang belum tergali optimal seperti.
(1) Ekonomi Biru (Blue Economy): Dengan garis pantai terpanjang di Indonesia, Aceh memiliki potensi perikanan tangkap, budidaya laut (seperti kerapu, lobster, rumput laut), dan bioteknologi kelautan yang sangat besar. (2) Pertanian dan Perkebunan Organik: Kopi Gayo yang telah mendunia, pala, cengkeh, dan kakao adalah komoditas bernilai tinggi yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya melalui industri pengolahan.
(3) Energi Terbarukan: Potensi panas bumi, air, dan matahari di Aceh sangat melimpah, yang dapat menjadi penopang energi bagi industri-industri baru.(4) Pariwisata Halal dan Budaya: Sebagai provinsi yang menerapkan syariat Islam, Aceh memiliki peluang besar menjadi destinasi pariwisata halal yang terintegrasi, mulai dari kuliner, fashion, hingga wisata religi dan sejarah.
Potensi-potensi ini saat ini tersebar dan belum terhubung dalam satu ekosistem industri yang saling menguatkan. Inilah celah di mana kebijakan pemerintah dapat masuk.
Tiga Pilar Kebijakan Strategis untuk Menciptakan Agglomeration di Aceh
Pemerintah tidak bisa hanya menjadi regulator pasif. Dalam konteks mendorong agglomeration economies di wilayah tertinggal, peran pemerintah sebagai katalisator dan fasilitator menjadi kunci. Berikut adalah tiga pilar kebijakan yang dapat diimplementasikan:
Pertama Penciptaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kluster Industri yang Tepat Sasaran. Pemerintah harus bergerak dari kebijakan yang menyebar (spread-out) menjadi terkonsentrasi (cluster-based). Daripada membangun infrastruktur kecil di semua tempat, sumber daya harus dipusatkan untuk menciptakan beberapa lokomotif pertumbuhan.
• KEK Berbasis Maritim di Pantai Barat-Selatan: Pemerintah dapat membangun KEK yang berfokus pada industri pengolahan hasil perikanan di wilayah seperti Meulaboh atau Calang. KEK ini dilengkapi dengan pelabuhan ikan modern, pabrik es dan cold storage, industri pengalengan, serta pusat penelitian bioteknologi kelautan. Dengan memusatkan semua aktivitas ini, nelayan dan pembudidaya ikan tidak perlu jauh-jauh menjual hasil tangkapan, pengusaha pengolahan mendapatkan pasokan yang stabil dengan biaya logistik rendah, dan inovasi produk baru akan lebih mudah muncul.
• Kluster Agro-Industri di Dataran Tinggi Gayo dan Aceh Tengah: Pusatkan pembangunan industri pengolahan kopi, pala, dan cengkeh di jantung penghasilnya. Bangun pusat pelatihan bagi petani untuk meningkatkan kualitas produksi, fasilitas pengolahan dan pengemasan yang memenuhi standar ekspor, serta pusat pemasaran digital yang melayani kluster tersebut. Konsep "from farm to table" akan lebih efisien dan bernilai tinggi ketika seluruh rantai pasok terkonsentrasi.
• Kluster Energi Terbarukan dan Industri Hijau di Aceh Utara: Memanfaatkan lahan eks PLTD dan infrastruktur yang ada, wilayah ini dapat dikembangkan menjadi kluster industri yang digerakkan oleh energi bersih dari panas bumi atau matahari. Insentif dapat diberikan bagi industri yang berpindah ke sini dengan syarat menggunakan energi terbarukan, menciptakan pusat industri hijau yang kompetitif.
| Membaca Fenomena Bullying di Lembaga Pendidikan |

|
|---|
| Perlindungan Anak yang Terlalu Jauh, Kita Sedang Mencetak Generasi Rapuh |

|
|---|
| Pasar Keuangan yang Likuid dan Cost of Fund Rendah Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif |

|
|---|
| Kegagalan Pasar kompetitif dan Sumber Daya Efisien di Tanah Rencong |

|
|---|
| Mengawal Tujuh Misi Mualem 2025-2029 |

|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/uniki-080624-b.jpg)






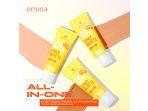







Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.