Opini
MoU Helsinki dan Revisi UUPA: Aceh Kembali Menguji Integritas Demokrasi Indonesia, Lulus atau Lolos?
Maka mengapa menyebut “Helsinki” seolah berlebihan, padahal ia adalah dasar hukum, dasar politik, dan dasar moral dari seluruh konstruksi
Oleh: Ahmad Abdullah Rahil, Aktivis Sosial, Pemerhati Isu Aceh, Founder Rumah Generasi Mulia
DUA dekade setelah perdamaian Aceh ditandatangani, Indonesia kembali berada di titik krusial. Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang kini digodok Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bukan hanya urusan pasal dan ayat—melainkan ujian besar tentang bagaimana negara menghargai perjanjian, menghormati komitmen hukum, dan menjaga integritas demokrasi yang dibangunnya sendiri.
Pernyataan kontroversial salah satu anggota Baleg, Benny K. Harman, yang menyebut sikap pihak Aceh sebagai “sedikit-sedikit Helsinki”, sebenarnya membuka satu ironi besar:
Bukankah MoU Helsinki adalah asbabun nuzul lahirnya UUPA? Bukankah perjanjian damai itu adalah fondasi yang memungkinkan Aceh dan Jakarta kembali duduk bersama dalam bingkai Republik?
Maka mengapa menyebut “Helsinki” seolah berlebihan, padahal ia adalah dasar hukum, dasar politik, dan dasar moral dari seluruh konstruksi kekhususan Aceh?
Justru menjadi aneh bila membahas UUPA tanpa merujuk pada MoU Helsinki.
Baleg, Tiga Orang Aceh, dan Ujian Demokrasi Kolektif-Kolegial
Saat ini revisi UUPA sedang dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang beranggotakan 90 orang. Dari jumlah itu, hanya tiga anggota DPR RI asal Aceh yang berada di Baleg, yakni: Nasir Djamil, TA Khalid dan Muslim Ayub.
Pertanyaan besar pun muncul:
Bagaimana mungkin tiga suara Aceh mengimbangi 87 suara lainnya yang sebagian besar tidak lahir, tumbuh, atau memahami konteks sejarah Aceh?
Di atas kertas, keputusan Baleg diambil secara kolektif-kolegial.
Tetapi dalam praktik, ketika terjadi perbedaan tajam, mekanisme voting lah yang menjadi penentu akhir. Artinya, Aceh kembali berada pada posisi minoritas dalam isu yang justru paling menentukan masa depannya sendiri.
Ini memunculkan pertanyaan krusial:
Mampukah demokrasi Indonesia mengakomodir substansi kebenaran, atau hanya kebenaran yang paling banyak suaranya?
Sekali lagi, ini bukan soal apakah anggota Baleg dari luar Aceh anti-Aceh—bukan. Ini soal sense of Aceh.
Tanpa pemahaman sejarah konflik, dinamika sosial budaya, dan konteks perdamaian, bagaimana mungkin mereka merumuskan revisi yang adil dan tepat?
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Ahmad-Abdullah-Rahil-5.jpg)






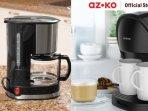
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Mulkan-Fadhli.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/uniki-080624-b.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Agustin-Hanapi-Penulis-Opini.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Kombes-Zahrul-Bawadi-kepala-BNN-Aceh.jpg)


:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Satlantas-saat-memeriksa-kelengkapan-surat-surat-kendaraan-di-BNA.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Drh-Fadhillah-Boy-P3SU.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/batu-pertama-16112025.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/update-harga-emas-hari-ini_harga-emas-antam_harga-emas-batangan_rincian-harga-emas-hari-ini.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Kompol-Mawardi-dipromosikan-menjadi-Kasat-Lantas-Polresta-Banda-Aceh.jpg)