Pojok Humam Hamid
MSAKA21: Indrapatra, Benteng, Candi, dan Jejak Hindu di Pesisir Aceh - Bagian VIII
Indrapatra adalah kompleks benteng bercorak batu bata dengan kanal pertahanan, berukuran besar untuk konteks arsitektur Nusantara awal
Oleh Ahmad Humam Hamid*)
JIKA kita berdiri di sebuah tempat di Ladong, Aceh Besar, menatap ke arah laut lepas, tak jauh dari pantai, ada reruntuhan tua yang dalam diamnya menyimpan lebih banyak cerita daripada batu yang tampak.
Itulah Benteng Indrapatra, yang dalam literatur dan tradisi lisan sering dikaitkan dengan kerajaan Hindu awal di Aceh.
Ia bukan sekadar benteng militer.
Situs ini adalah penanda peradaban, sebuah fragmen dari zaman ketika Aceh belum berwajah Islam, ketika arus India menyusuri jalur niaga, membawa serta bahasa, kepercayaan, dan batu bata yang ditata menjadi candi.
Indrapatra sering ditempatkan dalam spektrum tiga kerajaan Hindu di Aceh--bersama Indrapuri dan Indrapurwa--yang oleh para ahli dianggap sebagai jaringan kerajaan kecil yang mengontrol titik-titik strategis di ujung barat Sumatra.
Dari segi nama, kita segera mendengar gema India: “Indra,” dewa perang dan hujan dalam mitologi Hindu, dan “patra,” wadah atau benteng.
Sebuah benteng yang bernaung di bawah kuasa Indra?
Atau lebih tepat, sebuah simbol bahwa kuasa raja di Aceh kala itu dilegitimasi dengan menautkannya pada dewa dari tanah seberang?
Arkeologi berbicara.
Indrapatra adalah kompleks benteng bercorak batu bata dengan kanal pertahanan, berukuran besar untuk konteks arsitektur Nusantara awal.
Ekskavasi menunjukkan teknik konstruksi yang canggih, dengan lapisan batu kapur yang menyatukan bata merah, mirip dengan pola arsitektur candi-candi di Jawa Tengah.
Jika Borobudur adalah monumen kosmos, maka Indrapatra adalah monumen politik.
Ia berbicara tentang penguasaan ruang, perbentengan, dan dominasi atas jalur perdagangan yang menghubungkan India dan Cina melalui Selat Malaka.
Baca juga: Mahasiswa Pendidikan Sejarah USM Kuliah Lapangan ke Benteng Indrapatra & Makam Laksamana Malahayati
Indrapatra dan peta peradaban Aceh
Tetapi mari kita bergerak lebih jauh dari sekadar catatan teknis.
Apa makna Indrapatra dalam peta besar peradaban Aceh?
Di sinilah, kita bisa mengajukan hipotesis.
Indrapatra merupakan bukti bahwa India bukan sekadar pedagang rempah, tetapi juga penjual legitimasi.
Sebelum Islam masuk ke Aceh, para penguasa lokal tampaknya merasa perlu meminjam kosmologi Hindu-Buddha untuk meneguhkan otoritasnya.
Tidak ada raja tanpa dewa, tidak ada kuasa tanpa mitos.
Indrapatra adalah batu bata yang disusun untuk mengekalkan mitos itu.
Bandingkan dengan dunia yang lebih luas.
Di Kamboja, Jayavarman II membangun Angkor dengan keyakinan bahwa ia adalah devaraja.
Di Jawa, Sailendra menumpahkan tenaga ribuan buruh untuk mendirikan Borobudur dan Prambanan.
Di Aceh, skala mungkin lebih kecil, tapi pola pikirnya sama, kuasa politik harus dikawinkan dengan simbol spiritual.
Indrapatra adalah miniatur dari pola agung itu.
Namun, kita tidak boleh lupa bahwa Aceh adalah tanah persilangan.
Tidak seperti Angkor atau Mataram yang relatif terisolasi, Aceh berhadapan langsung dengan gelombang globalisasi awal, kapal-kapal Gujarat, Persia, bahkan Tiongkok.
Maka Indrapatra, selain menjadi simbol Hindu, juga sekaligus tapal batas yang suatu hari akan diubah fungsinya.
Ketika Islam masuk, benteng ini tidak dihancurkan.
Ia diwarisi, bahkan diberi makna baru.
Sejarawan kolonial Belanda mencatat bahwa Indrapatra pernah digunakan kembali pada era Kesultanan Aceh Darussalam sebagai benteng pertahanan menghadapi Portugis.
Artinya, Indrapatra bukan hanya peninggalan, ia adalah ruang berlapis: Hindu, Islam, kolonial, dan hari ini, pariwisata.
Pertanyaannya lalu, apakah Indrapatra benar-benar “kerajaan”?
Atau ijangan jangan hanya sekadar situs politik yang lebih kecil, bagian dari kuasa kecil yang tidak sempat menjadi pusat besar seperti Pasai atau Aceh Darussalam?
Di sinilah kita masuk ke wilayah yang lebih provokatif.
Mungkin Indrapatra lebih tepat disebut prasasti arsitektural dari sebuah masa peralihan.
Ia menunjukkan bahwa Aceh tidak pernah steril dari pengaruh luar.
Indrapatra adalah bukti bahwa sebelum syahadat bergema di masjid, mantra-mantra Hindu pernah dilantunkan di pesisir ini.
Jika kita mau jujur, Indrapatra juga mengajarkan tentang keterbatasan sejarah resmi.
Buku pelajaran di sekolah cenderung melompati fase Hindu di Aceh, seolah Aceh langsung menjadi Islam sejak awal.
Tetapi benteng di Ladong itu tidak bisa berbohong.
Batu bata itu berbicara: pernah ada masa ketika Aceh adalah bagian dari orbit besar “Indianisasi” Asia Tenggara.
Indrapatra dengan demikian adalah cermin kecil dunia besar, pertemuan India, Islam, dan lokalitas Aceh.
Ia adalah bukti bahwa Aceh selalu menjadi ruang peradaban yang lentur, tidak pernah menolak pengaruh, tetapi selalu menyesuaikannya.
Dari mantra ke syahadat, dari dewa ke Allah, dari kerajaan kecil ke kesultanan besar--semuanya bisa dilacak dari reruntuhan di Ladong itu.
Mungkin, jika kita menatap Indrapatra hari ini, yang paling penting bukan lagi menyibak detail teknis, melainkan mengakui lapisan-lapisan identitas Aceh.
Dan lapisan Hindu itu, walau tipis, tidak boleh dihapus.
Ia adalah bagian dari perjalanan panjang yang menjadikan Aceh bukan hanya “Serambi Mekkah”, tetapi juga simpang peradaban.
Kalau kita menatap reruntuhan bata merah yang sunyi di Ladong, kita sebenarnya sedang berdiri di hadapan sebuah bab yang hampir terhapus dari sejarah Aceh.
Benteng sekaligus candi, candi sekaligus benteng
Indrapatra bukan hanya tumpukan batu tua di tepi laut, bukan sekadar benteng yang pernah dipakai Sultan Iskandar Muda menghadapi Portugis.
Ia lebih dari itu. ia adalah cermin ketika Aceh masih bercakap-cakap dengan India, jauh sebelum ia menyebut dirinya Serambi Mekkah.
Nama Indrapatra saja sudah menyingkap arah angin zaman.
Indra, dewa hujan dan perang dari kosmologi Hindu, dan patra, wadah atau benteng.
Sebuah penguasa di pesisir ujung barat Sumatra menautkan dirinya dengan kosmos India, seolah berkata bahwa ia bukan sekadar kepala suku di muara sungai, tapi bagian dari arus besar peradaban.
Arkeologi berbicara lebih jujur daripada kronik.
Dinding bata merah yang tebal, kanal pertahanan yang masih bisa dikenali, menara pengawas yang kini tinggal fondasi--semua itu menunjuk pada kompleks yang lebih besar dari sekadar barak militer.
Indrapatra adalah benteng sekaligus candi, candi sekaligus benteng, sebagaimana Angkor Thom di Kamboja atau kompleks-kompleks Champa di pesisir Vietnam Tengah.
Pola penyusunan bata, penggunaan kapur sebagai perekat, dan keteraturan tata ruangnya menunjukkan keterhubungan teknologi dengan dunia Asia Tenggara maritim yang sudah lama diindianisasi.
Arsitektur itu adalah pernyataan politik.
Raja di Aceh bukan hanya manusia yang berkuasa atas tanah, tetapi manusia yang sah karena berada dalam orbit kosmik para dewa.
Tapi mari kita tarik garis lebih jauh: mengapa sebuah komunitas di Aceh harus meminjam bahasa India untuk memaknai dirinya?
Karena jalur niaga adalah jalur kosmologi.
Perahu-perahu dari Coromandel dan Gujarat tidak hanya membawa manik-manik, kain, atau logam, tetapi juga kitab, mitos, dan cara berpikir tentang kuasa.
Asia Tenggara pada abad pertama hingga kedelapan adalah laboratorium penerjemahan ide: raja di Jawa menyebut dirinya devaraja, Jayavarman II di Kamboja menobatkan diri sebagai Siwa, dan penguasa di Sumatra memilih nama-nama Sanskerta untuk menunjukkan bahwa mereka tidak sekadar lokal.
Maka Indrapatra berdiri bukan karena kebutuhan pertahanan semata, melainkan karena sebuah penguasa di pesisir ingin mengaitkan kuasanya dengan legitimasi Indra, penguasa hujan, penjamin kesuburan dan kemenangan perang.
Seperti situs-situs besar lain di kawasan ini, Indrapatra tidak mati ketika zaman berubah.
Ia berlapis. Diwarisi, dimaknai ulang, diisi dengan fungsi baru.
Saat Islam masuk ke Aceh, Indrapatra tidak dihancurkan.
Batu-batanya tidak dirobohkan, tetapi maknanya digeser.
Dari pusat upacara Hindu, ia menjadi bagian dari jaringan pertahanan Islam.
Pada abad ke-16, catatan Belanda menyebut bagaimana Kesultanan Aceh menggunakannya menghadapi Portugis.
Di sinilah terlihat wajah khas Asia Tenggara: peradaban tidak dibangun dengan penghancuran total, melainkan dengan adaptasi.
Angkor berubah dari Hindu ke Buddha, Borobudur ditinggalkan tapi tidak dihancurkan, candi-candi Cham diwarisi oleh komunitas Muslim.
Indrapatra pun mengikuti pola yang sama, dari mantra menuju syahadat, dari puja Indra ke doa jihad.
Di sinilah Aceh memperlihatkan dirinya sebagai simpang.
Sejak awal ia adalah gerbang Selat Malaka, pintu keluar-masuk dunia. India datang dari barat, Tiongkok dari timur, Arab menyusul kemudian.
Indrapatra adalah salah satu jejak awal globalisasi itu, sama pentingnya dengan makam Malikussaleh di Pasai.
Yang satu menunjukkan fase Hindu, yang satu menandai fase Islam.
Dari benteng-candi di pesisir menuju nisan marmer berkaligrafi Arab di Samudra Pasai, garis transformasi itu begitu jelas, meski jarang kita akui.
Jangan kunci diri; ini kekuatan
Lalu mengapa Indrapatra sering dilupakan?
Karena Aceh modern telah lama mengunci dirinya dalam narasi tunggal, Serambi Mekkah.
Segala sesuatu yang tidak sejalan dengan narasi itu dianggap gangguan, atau setidaknya tidak penting.
Padahal justru di situlah letak kekuatan.
Islam Aceh tidak datang ke ruang kosong, ia menulis di atas laspisan Hindu-Buddha.
Indrapatra adalah saksi bisu dari lapisan itu.
Menghapusnya dari ingatan berarti mengosongkan separuh cerita bagaimana Aceh menjadi Aceh.
Apa tolok ukur yang bisa kita gunakan untuk menilai Indrapatra sebagai jejak peradaban?
Pertama, namanya sendiri adalah kode kosmologis, meminjam Indra dari India.
Kedua, arsitekturnya adalah bukti transfer teknologi, bata merah dengan perekat kapur yang serupa dengan candi di Jawa dan Champa.
Ketiga, fungsinya bukan sekadar militer, melainkan juga politis, pusat legitimasi raja melalui asosiasi dengan dewa.
Dan keempat, transformasinya membuktikan kesinambungan, diwarisi Islam, dipakai kembali oleh Kesultanan Aceh, bahkan menjadi simbol perlawanan terhadap kolonial.
Empat tolok ukur ini menempatkan Indrapatra dalam peta Indianisasi Asia Tenggara, sekaligus menjelaskan kenapa Aceh begitu cepat mengadopsi Islam--karena tanah ini sudah terbiasa menjadi rumah bagi kosmologi asing.
Kini Indrapatra lebih sering menjadi latar foto wisata.
Tetapi jika kita mau mendengar, batu bata itu masih bersuara.
Ia berbisik bahwa Aceh bukan monolit, bahwa doa kepada Indra pernah menggema sebelum azan, bahwa peradaban selalu lahir dari tumpang tindih, bukan dari kehampaan.
Ia mengingatkan bahwa sejarah lebih adil daripada ideologi.
Ia menempatkan Indrapatra bukan di pinggir, tapi di awal.
Tanpa memahami Indrapatra, kita kehilangan kunci untuk memahami mengapa Islam berakar sedemikian cepat di tanah ini.
Karena hanya tanah yang sudah lama menjadi tuan rumah bagi kosmologi luar yang sanggup menyambut kosmologi baru dengan begitu akrab.
Dan Indrapatra adalah bukti keras bahwa Aceh sejak semula bukan benteng tertutup, melainkan simpang peradaban.
*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.
Artikel dalam rubrik Pojok Humam Hamid ini menjadi tanggung jawab penulis.
sejarah Aceh
kehidupan aceh purba
Peradaban Aceh
Benteng Indrapatra
Cagar Budaya Indrapatra
pojok humam hamid
humam hamid aceh
Serambi Indonesia
| Prabowo dan Transisi Yang Belum Selesai: Inversi Model Mahathir-Najib Atau Sebaliknya? |

|
|---|
| Khan, Aboutaleb, dan Mamdani: Fenomena Migran Muslim Menjadi Pejabat Publik di Eropa dan AS |

|
|---|
| MSAKA21 - Kerajaan Samudera Pasai: Hikayat Raja Raja Pasai dan Catatan Tome Pires – Bagian XVI |

|
|---|
| Gaza dan Yahudi Amerika: Dua Generasi, Dua Hati yang Berbeda |

|
|---|
| Dana Otsus Jilid 2: Lagu Lama vs Otoritas Teknokratis – Bagian Kedua |

|
|---|










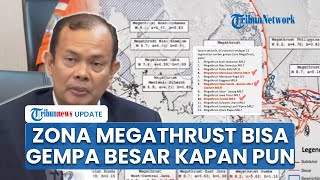




Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.