Kupi Beungoh
Aceh dan Kepemimpinan Militer (IX) - Iskandar Muda: Angkatan Perang, “Mercineries”, dan “Raja Toke”
Iskandar Muda mengawinkan perdagangan dan militer yang tiada duanya dalam sejarah Aceh, dan bahkan mungkin Nusantara.
Oleh Ahmad Humam Hamid*)
ISKANDAR Muda adalah raja tentara yang mempunyai kemampuan kapitalisasi kembaran dua kekuatan yang luar biasa.
Ia mengawinkan perdagangan dan militer yang tiada duanya dalam sejarah Aceh, dan bahkan mungkin Nusantara.
Ia tahu benar memanfaatkan militer untuk menjamin kestabilan dan pertumbuhan kerajaannya.
Ia juga paham benar apa arti kestabilan dan keteraturan Aceh untuk menjadi daya tarik pedagang mancanegara.
Berbagai bangsa berdatangan mulai dari Venesia Italia, Inggris, Belanda, Denmark, dan Perancis sampai ke Turki, Aleppo Syiria, dan Cina.
Dari India umumnya adalah pedagang Gujarat, Benggali, dan Malabar.
Dari kawasanan serantau ada pedagang Siam dan Pegu-Burma.
Sedangkan dari kawasan Nusantara berdatangan pedagang Banten, Jawa, dan Makassar.
Iskandar Muda membangun militer kerajaan Aceh yang terhitung digdaya pada masanya.
Mengutip catatan Laksamana Perancis, Agustin de Beaulieu (1629) sejarawan kondang Asia Tenggara, kelahiran Selandia baru, Anthony Reid, dan Takeshi Ito, Profesor Universitas Sofia, Tokyo (1985) menulis dengan baik bagaimana gambaran kapasitas Iskandar Muda tentang kemiliteran Aceh pada masanya.
Reid dan Ito menyebutkan (1985), dalam tempo 24 jam, Iskandar Muda mampu memobilisir 40.000 tentara untuk siap berperang.
Pada saat yang sama, bersamanya di istana 1.500 pengawal raja juga siap.
Pengawal itu umumnya adalah budak dan serdadu bayaran yang umumnya adalah orang asing-bukan pribumi Aceh.
Di sekitar istananya juga siap 200 pasukan berkuda (Dasgupta 1962).
Iskandar Muda juga mempunyai lebih dari seratus galley- kapal besar, sepertiganya berukuran jauh lebih besar dari kapal perang negara Eropa manapun pada masa itu.
Hal itu membuat angkatan laut Aceh menjadi salah satu yang terbesar pada masanya di kawasan serantau (Beaulieu 1662, dalam Ito1996).
Baca juga: Aceh dan Kepemimpinan Militer (VI) - Sultan Al Mukammil, "Repertoar Raja Boneka”
Baca juga: Aceh dan Kepemimpinan Militer (VII) Al Mukammil: Hard Power dan Shock Therapy
Serdadu Bayaran
Serdadu bayaran yang di dalam istilah kepustakaan disebutkan “mercinery” dalam kaitannya dengan Iskandar Muda pada dasarnya terdiri dari dua komponen.
Yang pertama adalah serdadu bayaran profesional yang terdiri dari orang-orang Turki, Gujarat, dan Malabar, Abesinia-Ethiophia hari ini, dn yang kedua adalah para budak muda (Beaulieu 1996 dalam Perret 2011).
Para budak itu dilatih menjadi tentara dengan berbagai tugas yang diberikan oleh raja, mulai dari eksekutor, pembunuh rahasia, pemelihara gajah, dan berbagai tugas lainnya.
Umumnya mereka tinggal di “dalam”, yakni sebuah kawasan tertutup untuk orang luar yang lokasinya berada di sekitar istana Sultan.
Apa yang menarik tentang para budak yang menjadi pengawal raja adalah usia mereka yang relatif muda.
Ini artinya ada pilihan dan persyaratan yang dibuat oleh Iskandar Muda dalam pembelian budak untuk pengawal dari berbagai kawasan.
Dalam kasus Aceh, pembelian budak bukanlah sesuatu yang langka, karena Aceh sejak awal abad ke 16 dan abad ke 17 dikenal sebagai salah satu pasar budak di kawasan Nusantara (Vander Chijs 1932 dan Martin 1662, dalam Perret 2011).
Para pedagang budak itu umumnya berasal dari berbagai suku bangsa, mulai bangsa Moor-Maroko, Afrika, Coromandel-Tamil Nadu hari ini, dan juga pedagang Inggris dan Denmark.
Paling kurang setiap tahun tidak kurang 2.000 budak diperdagangkan di Aceh dan sejumlah tempat lain, dan umumnya para budak berasal dari kawasan India Selatan, seperti Tamil Nadu.
Secara umum, sekalipun budak yang menjadi tentara pengawal Sultan berasal dari berbagai tempat, mayoritas utamanya adalah budak-budak dari Pantai India Selatan.
Istana Iskandar Muda juga dilengkapi dengan 3.000 pengawal perempuan yang sangat sigap, baik untuk keperluan pengamanan, maupun berbagai tugas lain yang berurusan dengan keamanan dan kemiliteran.
Logistik senjata militer diatur dengan standar operasi yang sangat ketat, dimana terdapat sekitar 2.000 meriam.
Senjata api untuk pasukannya tidak boleh digunakan sepanjang waktu, kecuali hanya pada saat akan menjalani perang atau pertempuran lainnya.
Untuk keperluan perang darat yang besar, Iskandar Muda mempunyai 300 gajah yang terlatih dengan dengan baik untuk angkutan logsitik dan peperangan (Harris dalam Dasgupta 1962).
Baca juga: WAWANCARA EKSKLUSIF - Tun Daim: Saya Banyak Baca Sejarah Aceh, Kagum, Semangat Orang Aceh Luar Biasa
Baca juga: Tan Sri Sanusi Junid Dalam Kenangan Putranya Akhramsyah Muammar Ubaidah
Monopoli Kerajaan
Memiliki tentara yang banyak tentu saja membutuhkan uang dan sumberdaya yang mencukupi.
Iskandar Muda menciptakan mesin uang dari kegiatan perdagangan, terutama perdagangan lada, perdagangan timah, dan berbagai hasil bumi lainnya.
Ia membangun tiga tingkatan mesin uang pada tiga tingkatan wilayah dengan prinsip utama “monopoli kerajaan”.
Pada kenyataannya yang dimaksud dengan “monopoli kerajaan” tidak lain dari semua pemasukan atau kegiatan perdagangan yang dilakukan atas nama kerajaan sama sekali tidak mempunyai analogi dengan kerajaan, akan tetapi dengan dirinya sendiri.
Hampir semua kepustakaan yang menyangkut dengan kegiatan perdagangan, baik aturan, maupun kegiatan selalu berujung pada aliran uang kepada Iskandar Muda, bukan untuk pundi-pundi keuangan kerajaan.
Dalam hal perdagangan misalnya, ia sendiri adakah pedagang besar- yang akan menjadi pembeli pertama dari semua barang yang masuk ke pelabuhan Bandar Aceh.
Lombard (1998) bahkan menyebutkan Iskandar Muda adalah pembeli pertama dan utama.
Tidak cukup dengan kegiatannya sendiri, ia juga menunjuk beberapa pedagang lain untuk melakukan kegiatan jual beli yang juga tak lebih sebagai pedagang perantara sang raja.
Disamping berbagai tugas adminsitrasi kerajaan, para pegawai pelabuhan oleh sang raja diberikan tugas tambahan untuk menangani berbagai kegiatan pedagangan miliknya.
Tugas tambahan itu menyangkut dengan pembelian dan penjualan barang impor dan ekspor, mulai dari kelancaran administrasi, bongkar muat, pergudangan, dan penjualan kembali.
Dalam konteks keuangan, tidak ada batas yang tegas antara kepemilikan dan kekayaaan negara sebagai institusi, dan kekayaan pribadi raja sebagai penguasa.
Negara dan pemimpinnya bersatu dalam individu Iskandar Muda.
Pada tingkatan pertama wilayah yang mempunyai kegiatan utama perekonomiannya lada, sang raja menerapkan kontrol ketat, dimana hanya pedagang-pedagang asing, yang mendapat izin yang boleh beroperasi.
Selanjutnya seluruh lada hanya boleh di ekspor lewat pelabuhan Bandar Aceh.
Mengingat lada sebagai komoditas unggulan perdagangan global-utamanya Eropa, kebijakan kontrol ketat jelas menjadi alat pemasukan uang yang sangat besar bagi Iskandar Muda.
Kebijakan itu berlaku untuk seluruh wilayah pantai barat, pantai timur, dan Kedah di semenanjung Malaysia.
Di Malaysia sendiri kekuasaan Aceh lebih bersifat protektorat, terutama yang menyangkut dengan kerajaan-kerajaan Kedah, Pahang, Perak, dan Johor.
Pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan, terutama dalam hal perdagangan lada, dapat berakibat fatal seperti yang terjadi di Kedah.
Apa yang terjadi di Kedah adalah pemusnahan kebun lada rakyat oleh kerajaan Aceh akibat ketidakpatuhan penguasa Kedah.
Perkebunan lada rakyat Kedah ditebang dan dibakar atas perintah Iskandar Muda.
Ia bahkan pernah mengancam akan membakar lada di wilayah kerajaan Banten, yang dianggap menganggu stabilitas rantai pasok lada Nusantara yang praktis berada dalam monopoli kerajaan Aceh (Shellabear 1898 dalam Lombard 1998).
Mengutip dari berbagai sumber, Lombard (1998) tidak menepis kemungkinan kebijakan pelayaran Hongi VOC yang menebang dan membakar cengkeh rakyat di kepulauan Tarnate pada abad ke 17, tidak lain diilhami salah satunya dari strategi menopoli lada Iskandar Muda yang “disempurnakan”.
Pelayaran Hongi atau Hongitochten yang dimulai pada 1625 adalah pelayaran yang dilakukan oleh VOC menggunakan senjata lengkap untuk mengawasi jalannya monopoli perdagangan rempah.
Perahu atau kapal dagang yang bukan milik VOC di kawasan perairan Ternate dibakar, dan awaknya dibunuh.
Rakyat yang menjual cengkeh atau pala ke pihak non VOC disiksa, dan tanamannya dihancurkan.
Belanda bahkan mengatur pergantian raja dengan memilih Sultan Tarnate, Mandarsyah yang kemudian dipaksa menandatangani kebijakan pelayaran Hongi.
Iskandar Muda membangun institusi penguasa wilayah, yang digelar dengan panglima-utamanya di pantai barat.
Para penguasa wilayah itu digunakan untuk menjamin terlaksananya aturan, utamanya yang menyangkut dengan pemasukan uang kepada kerajaan Aceh.
Pemasukan itu baik kewajiban pedagang, pajak pembelian, dan berbagai biaya lainnya yang menyangkut perdagangan (Reid &Ito 2011).
Sebagai contoh, Tiku dan Pariaman adalah dua wilayah yang berada di bawah panglima masing-masing yang mengontrol pantai barat sampai ke Padang.
Mereka diwajibkan melapor setiap tahun.
Untuk menihilkan potensi penyalahgunaan kekuasaan, para panglima itu diganti setiap tiga tahun.
Kontrol yang serupa juga tetap berlaku untuk pantai timur Aceh dengan cara menunjuk para panglima, sekalipun setelah kematian Iskandar Muda, kelembagaan panglima itu hilang.
Di kawasan-kawasan yang kepentingan ekonomi kerajaan Aceh kurang relevan, terutama kawasan nonlada atau sumber daya penting lainnya, penunjukan panglima tidak dilakukan.
Pilar kedua monopoli perdagangan dilakukan tidak seketat seperti yang terjadi dengan perdagangan lada.
Dua kerajaan vassal- protektorat Aceh di semenanjung Melayu -Pahang dan Perak, disamping penunjukan panglima, Iskandar Muda memerintahkan ekspor timah terhadap pihak yang diinginkannya.
Untuk memastikan kebijakan itu terjadi, kerajaan Aceh menempatkan satuan angkatan laut Aceh di kedua wilayah maritim kerajaan Pahang dan Perak.
Pilar ketiga monopoli perdagangan yang lebih bersifat umum dilakukan dengan menjadikan pelabuhan Bandar Aceh sebagai pelabuhan utama dikawasan.
Memang benar hampir semua kawasan yang berada dibawah kekuasaan ataupun di wiayah pengaruh Aceh mempunyai pelabuhan tersendiri.
Di sebalik itu dengan monopoli ekspor lada hanya terjadi melalui pelabuhan Bandar Aceh, sulit bagi pedagang lain untuk datang ke sejumlah kawasan-kawasan itu.
Disamping itu kedatangan para pedagang Islam dari Timur Tengah dan India, berikut dari kawasan Nusantara, juga menjadi variabel tersendiri yang menguntungkan untuk Aceh.
Mereka tidak mau datang ke Melaka yang berada di bawah kekuasan Portugis.
Disamping itu Iskandar Muda juga menerapkan pajak yang lebih murah terhadap barang-barang impor yang dibawa oleh pedagang muslim ke pelabuhan Bandar Aceh.
Kedatangan berbagai pedagang muslim itu, berikut dengan kebijakan monopoli ekspor lada via pelabuhan Bandar Aceh menjadi salah kunci yang membuat pelabuhan ini termaju di kawasan.
Tidak cukup dengan kebijakan langsung terhadap perdagangan, kekuatan maritim Aceh sekaligus menjadi kembaran perdagangan yang menjadi indikator keamanan kawasan.
Disamping itu Aceh juga memberikan kemudahan untuk pedagang dari berbagai berbangsa dalam bentuk kawasan khusus yang kemungkinan besar diizinkan menjalani gaya hidup mereka masing-masing.
Pemberian kawasan khusus yang dimaksud adalah setiap bangsa yang berasal dari negara yang sama, dan mungkin juga kepercayaan yang sama diberikan sebuah kawasan tertentu.
Ini artinya, kehidupan mereka sehari-hari berada dalam sebuah enclave- kawasan kantong yang mempunyai diskontinuitas dengan budaya Aceh, dan sampai tingkat tertentu hukum.
Baca juga: Penulis Muda Diminta Perbanyak Tulisan Sejarah Aceh
Baca juga: Pemerintah Perjuangkan Jalur Rempah Aceh Jadi Warisan Dunia
Dari Anggur, Candu, Hingga Ie Jok Masam
Apa yang terjadi di kawasan itu adalah sekeping kehidupan dari berbagai bangsa yang datang dan singgah dan berdagang di Aceh.
Ini adalah sebuah kebijakan liberal yang menjadi pasangan dari konsekuensi kota perdagangan dan negara kota.
Disamping itu, dengan modal angin monsoon Samudra Hindia yang bertukar arah timur-barat selama enam bulan, maka masa tinggal pedagang akan membutuhkan yang relatif lama menunggu perobahan angin terjadi.
Ini artinya membiarkan pedagang asing terlalu lama “berlibur” dari kebiasaannya sehari-hari dalam waktu yang relatif lama akan menjadi faktor disinsentif kepada mereka untuk datang dan berdagang di Aceh.
Salah satu bukti kebijakan “liberalisasi” itu adalah ditemukannya sejumlah item dan daftar barang impor yang masuk ke pelabuhan Aceh merupakan barang-barang nonislami.
Barang-barang impor itu adalah anggur, minuman perangsang, dan candu-opium (Adat Aceh dalam Voorhouve dan Drewes 1958, Iskandar 1958, dalam Lombard 1998).
Sebenarnya tanpa impor anggur pun yang notabene mengandung alkohol, di Aceh tetap saja ada komunitas peminum anggur aceh -ie jok masam, yang kandugan alkoholnya tidak kalah bahkan kadang lebih tinggi dari sejumlah minuman alkohol dari berbagai negara.
Catatan pengunjung Aceh, seperti Marco Polo-Italia, Frederick de Houtman-Belanda, dan James Lancaster-Inggris, menyebutan tentang hal itu, mulai dari Pasai hingga ke Banda Aceh.
Komunitas “ie jok-masam” itu sampai hari inipun masih dapat ditemui di sejumlah tempat di Aceh.
*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.
KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.
Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/humam-hamid-aceh-1.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Veesam-SamohMahasiswa-USK-Banda-Aceh-asal-Thailand.jpg)



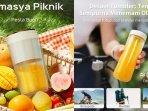



![[FULL] Ekonom Celios Sebut Indonesia Belum Siap Redenominasi Rupiah: RI Butuh 8 hingga 9 Tahun Lagi](https://img.youtube.com/vi/E_lguIar2Dg/mqdefault.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/titi-anggraini-perludem.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Humam-Hamid-Whoosh.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/FERI-IRAWAN-Magelang.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Veesam-SamohMahasiswa-USK-Banda-Aceh-asal-Thailand.jpg)