Opini
19 Tahun Tsunami: Parade Kesedihan dan Sigap Bencana
Salah satu perubahan besar yang terjadi setelah gempa tsunami menghantam Aceh 19 tahun silam adalah berakhirnya perang antara Gerakan Aceh Merdeka (GA
Khairil Miswar, Alumnus Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
TANGGAL 26 Desember 2004 adalah titik awal lahirnya era baru bagi masyarakat Aceh. Hal ini ditandai dengan munculnya frasa pascatsunami dalam penulisan sejarah sosial masyarakat Aceh di kemudian hari. Frasa ini merupakan bagian dari periodisasi sejarah Aceh kontemporer yang dilandaskan pada satu peristiwa besar bernama tsunami, di mana peristiwa dimaksud diyakini telah mengubah wajah Aceh di masa-masa kemudian.
Salah satu perubahan besar yang terjadi setelah gempa tsunami menghantam Aceh 19 tahun silam adalah berakhirnya perang antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan aparat Republik Indonesia setahun setelahnya, tepatnya pada 15 Agustus 2005.
Sejarah mencatat bahwa peristiwa tsunami memiliki kontribusi besar dalam mendorong para pihak yang bertikai untuk berunding dan mengakhiri perang dengan alasan kemanusiaan. Dengan adanya kesepakatan damai ini kedua pihak memiliki kesempatan untuk membangun kembali Aceh yang kala itu telah menjadi puing.
Parade kesedihan
Sebagai masyarakat Aceh, saya menyaksikan sendiri kerusakan yang terjadi setelah gelombang tsunami menyapu bersih daratan. Mayat bergelimpangan dan tersangkut di sejumlah bangunan; sebagiannya terimpit reruntuhan bangunan dan potongan kayu.
Sebagian yang lain mengambang terapung di gerangan air dengan tubuh yang telah membengkak. Sejumlah mobil hancur berserakan sepanjang jalan sementara pengemudi dan penumpang telah menjadi mayat. Perahu-perahu nelayan tampak mendarat di atap-atap gedung bersama sampah yang menumpuk. Ratusan dan bahkan ribuan mayat tak dikenali dikubur satu liang dalam iringan tangisan dan doa.
Pemandangan demikian tentu melahirkan kesedihan mendalam, khususnya bagi mereka yang kehilangan keluarga dan teman akibat bencana dahsyat yang tak pernah diduga sebelumnya. Pedihnya lagi, kesedihan ini harus diratapi di tenda-tenda pengungsian yang kala itu menyemak di seantero Aceh. Untung saja pemerintah sigap dan bantuan internasional pun berdatangan sehingga Aceh bisa kembali bangkit seperti sedia kala.
Namun sayangnya, secara faktual kesedihan ini kembali muncul ketika peristiwa itu diperingati saban tahun. Air mata yang dulunya telah kering kembali menitik saat peristiwa kelam itu diingat dan diceritakan kembali dalam momen peringatan tsunami pada setiap 26 Desember. Tanpa sadar luka yang sedianya telah pulih seiring perjalanan waktu kembali menganga.
Dalam konteks sosio-kultural, memperingati peristiwa-peristiwa besar memang telah menjadi tradisi bangsa-bangsa di dunia. Secara prinsip hal ini dimaksudkan sebagai medium untuk mengambil ibrah dari peristiwa yang telah terjadi agar kita lebih bijaksana dalam menyikapi kehidupan di masa depan.
Namun, dalam konteks peringatan peristiwa tsunami di Aceh, yang terjadi justru “parade kesedihan” yang sama sekali tidak produktif bagi kebangkitan Aceh di masa depan. Hal ini dibuktikan dengan kembali munculnya kisah-kisah sedih di panggung peringatan yang membuat keluarga korban kembali meratap.
Idealnya peringatan peristiwa tsunami di masa depan harus mampu dikemas dalam bentuk yang lebih produktif sehingga bisa melahirkan optimisme untuk terus bangkit, bukan justru menjadi medium merawat luka. Peristiwa kelam di masa lalu tersebut mestilah menjadi alat pecut bagi masyarakat Aceh untuk semakin tanggap terhadap bencana yang terus mengintai saban hari.
Selain persoalan takdir dan kemunculannya yang tiba-tiba, harus diakui bahwa besarnya jumlah korban dalam peristiwa tsunami Aceh 189 tahun lalu juga disebabkan oleh belum adanya sikap sadar bencana di kalangan masyarakat.
Tafsir bencana
Sejauh ini sebagian masyarakat Aceh masih menafsirkan bencana hanya sebagai “hukuman Tuhan” atas ketidakpatuhan dan maksiat yang disebut-sebut kian merajalela. Memang dalam konteks teologis, salah satu sebab terjadinya bencana karena adanya dosa dan maksiat. Hal ini sesuai dengan Quran surat Asy-Syuraa ayat 30. Dalam hal ini juga terdapat perkataan Ali bin Abi Thalib yang dengan tegas menyebut musibah turun karena adanya dosa. Namun demikian, kita tidak bisa menafikan pesan lainnya dalam Alquran tentang kontribusi manusia dalam mengundang bencana. Hal ini di antaranya disebut dalam Quran surat Ar-Rum (41-42) bahwa manusia memiliki andil dalam merusak bumi sehingga bencana pun bermunculan.
Dalam konteks ini aksi perusakan bumi seperti penambangan liar, penebangan dan pembakaran hutan, limbah industri, membuang sampah sembarangan dan pencemaran laut adalah ulah manusia yang dapat dikategorikan sebagai maksiat yang kemudian menghadirkan bencana alam. Dalam hal ini jelas bahwa bencana memiliki korelasi dengan ketidakbecusan manusia dalam merawat bumi sehingga ia menjadi salah satu medium hukuman yang diberikan Tuhan kepada manusia.
Karena itu, kesadaran masyarakat dalam merawat bumi juga menjadi salah satu poin penting guna menghindari terjadinya bencana. Dengan kata lain, terjadinya bencana bukan saja disebabkan oleh konser musik sebagaimana dipahami oleh sebagian kalangan, tapi juga dipicu oleh perilaku kita sendiri yang tanpa sadar setiap saat merusak bumi demi keuntungan pribadi.
Sigap bencana
Selain edukasi soal tafsir bencana yang kerap dipahami secara parsial dan bahkan keliru, peringatan tsunami juga hendaknya bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat agar sigap dan tanggap terhadap bencana yang terus terjadi.
Hal ini penting agar peringatan tsunami memiliki nilai edukasi, khususnya terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana. Edukasi ini menjadi poin dalam membangun kesadaran masyarakat, khususnya di daerah rawan bencana agar korban jiwa dapat diminimalisir.
Pemahaman tentang kesadaran masyarakat terhadap bencana ini bukan dilakukan ketika bencana sudah terlanjur terjadi, tetapi mesti ditanamkan jauh-jauh hari sebelum bencana itu datang. Artinya, sedari awal masyarakat sudah harus dibekali dengan berbagai pengetahuan tentang kebencanaan, mulai dari menjauhi daerah-daerah rawan bencana sampai dengan pengetahuan tentang strategi menghadapi bencana ketika mereka terjebak di daerah-daerah tersebut.
Jelasnya pendidikan tanggap bencana meliputi tiga fase, yaitu: fase pra bencana, saat bencana terjadi dan pascabencana sebagai upaya pemulihan. Kesadaran dan kesigapan terhadap bencana ini memiliki korelasi dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Dia tidak akan mengubah keadaan suatu kaum tanpa ada usaha dan upaya dari kaum itu sendiri (QS. Ar-Ra’d: 11).
Dalam konteks ini, kesigapan terhadap bencana menjadi hal penting yang mesti terus ditanamkan kepada masyarakat, di mana kesigapan ini menjadi salah satu strategi agar tercapainya keselamatan sehingga jumlah korban jiwa dapat berkurang.
Selain kesadaran dan kesigapan masyarakat secara personal terhadap bencana, pemerintah setempat juga dituntut aktif dalam mitigasi bencana seperti pemetaan wilayah rawan, penanaman pohon bakau, penghijauan dan hal-hal lain yang dianggap perlu sebelum bencana terjadi.
Program ini mesti terus dilakukan dan dikampanyekan secara berulang agar ketahanan kita terhadap ancaman bencana semakin kuat. Dalam hal ini juga dibutuhkan sejumlah regulasi yang mendukung upaya tersebut sehingga mitigasi bencana tidak hanya berada pada tataran konseptual belaka, tapi juga terwujud dalam aksi nyata.
Kita berharap agar peringatan bencana seperti peristiwa tsunami di masa depan tidak lagi terjebak dalam “parade kesedihan” seperti yang berlangsung selama ini, tapi harus mampu menjadi medium dalam menciptakan masyarakat yang sigap bencana melalui edukasi yang intens.















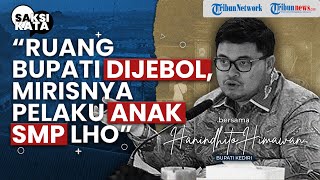




Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.