Kupi Beungoh
Waspada Pelecehan Berselimut Candaan di Media Sosial
Meskipun di dunia maya, namun kekerasan yang terjadi di dalamnya meninggalkan luka yang sangat nyata.
Oleh Syifaul Nazila *)
Pernahkah kamu membaca komentar seperti “tobrut” di media sosial? Atau barangkali lebih familiar dengan kalimat seperti, “Ada yang bulat tapi bukan tekad, ada yang menonjol tapi bukan bakat,”?
Frasa-frasa seperti ini tampak sepele, bahkan sering dianggap lucu.
Tapi coba renungkan kembali, adakah sisi kelucuan dari sebuah komentar yang secara terang-terangan merendahkan tubuh perempuan dan menjadikannya objek seksual?
Di balik layar ponsel, laptop, dan jaringan internet, ruang digital Indonesia sedang menghadapi darurat kekerasan yang kerap tak terlihat mata, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO).
Meskipun di dunia maya, namun kekerasan yang terjadi di dalamnya meninggalkan luka yang sangat nyata.
Tidak ada yang benar-benar “maya” bagi korban, karena yang mereka rasakan adalah ketakutan, trauma, kehilangan rasa aman, dan dalam banyak kasus, berdampak hingga ke dunia nyata.
Komnas Perempuan mencatat bahwa sepanjang tahun 2022 terdapat 1.697 kasus KGBO.
Angka ini naik dibanding tahun sebelumnya dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun angka ini sesungguhnya bukan gambaran utuh.
Banyak korban memilih diam. Alasannya? Mulai dari rasa malu, takut disalahkan, hingga tidak tahu harus melapor ke mana.
Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami bahwa pelecehan seksual tidak harus terjadi secara langsung di ruang publik.
Banyak juga yang belum menyadari bahwa apa yang mereka alami atau bahkan mereka lakukan adalah bentuk kekerasan seksual.
Secara global, masalah ini tak kalah mengkhawatirkan. Survei yang dilakukan Plan International pada tahun 2020 terhadap 14.000 perempuan muda di 31 negara menunjukkan bahwa 58 persen pernah mengalami pelecehan di dunia maya.
Separuh dari mereka mengatakan bahwa pelecehan di ruang digital lebih sering mereka alami dibanding pelecehan di ruang publik.
Ini mengindikasikan bahwa platform digital yang seharusnya menjadi media ekspresi diri, justru menjadi ladang subur kekerasan seksual.
Kekerasan gender berbasis online sering kali tersembunyi dalam bentuk-bentuk yang dianggap wajar atau bahkan lucu.
Istilah “tobrut atau singkatan dari “toket brutal” adalah salah satu contohnya.
Komentar ini kerap muncul di kolom komentar konten video perempuan, entah karena mereka berpakaian tertentu, sedang berjoget, atau sekadar berbicara di depan kamera.
Sementara sebagian orang menganggapnya guyonan, korban justru mengalami tekanan psikis.
Ini bukan sekadar “candaan”, ini adalah bentuk verbal sexual harassment yang membidik tubuh perempuan dan menjadikannya objek hiburan. Pertanyaannya, dimanakah letak lucunya?
Bahasa semacam ini bukan sekadar tidak sopan. Ia mengandung kekerasan simbolik yang terus-menerus menciptakan stigma, memperkuat stereotip, dan melemahkan posisi perempuan di ruang publik.
Perempuan akhirnya terpaksa membatasi diri, menyensor diri, atau bahkan keluar dari media sosial demi menjaga kesehatan mentalnya. Diulang terus menerus, komentar seperti ini menciptakan atmosfer yang tidak aman bagi perempuan di ruang digital.
Lebih parah lagi, ia bisa menjadi pintu masuk bagi bentuk kekerasan seksual secara langung.
Jika ditelusuri lebih dalam, KGBO adalah cerminan dari kekuasaan yang timpang dalam masyarakat patriarki.
Dunia digital, meski terlihat netral, sesungguhnya tidak bebas nilai. Ia membawa serta bias, budaya, dan cara pandang dunia nyata ke dalam ranah daring.
Maka tidak mengherankan jika kekerasan terhadap perempuan tetap subur di platform-platform digital.
Dalam masyarakat yang terbiasa melihat perempuan sebagai objek, platform digital hanya memperbesar skala dan kecepatannya. Komentar seksis bisa menyebar dalam hitungan detik, diperkuat algoritma, dan diulang oleh ratusan bahkan ribuan pengguna lain.
Sebuah unggahan yang seharusnya menjadi bentuk ekspresi diri bisa berubah menjadi ladang serangan verbal.
Sayangnya, banyak yang memilih menyalahkan korban, “Ngapain juga tampil begitu?” atau “Salah sendiri, upload video joget-joget.”
Mentalitas victim blaming ini tidak hanya memperburuk kondisi korban, tapi juga memperkuat kekuasaan pelaku.
Alih-alih fokus pada tindakan pelaku yang melanggar, publik malah mengadili korban. Meskipun perilaku korban tidak selalu benar dan sesuai nilai, namun bukan berarti tindakan pelaku bisa dibenarkan.
Lebih mengherankan, tidak sedikit yang menjadi korban termasuk mereka yang berpakaian sopan.
Dampak dari kekerasan daring tidak berhenti di layar. Korban KGBO mengalami gangguan kecemasan, depresi, insomnia, penurunan kepercayaan diri, hingga trauma berat.
Beberapa bahkan memilih keluar dari media sosial, kehilangan pekerjaan, atau memutus hubungan sosial mereka.
Sebagai aktivis kesehatan, saya melihat langsung dampak dari kekerasan berbasis gender, baik yang terjadi di dunia nyata maupun digital.
Banyak perempuan datang ke layanan konseling karena tekanan mental akibat body shaming, cyberbullying, hingga pelecehan seksual. Trauma ini tidak hanya menghantui secara emosional, tapi juga bisa memicu gangguan tidur, depresi, hingga kecenderungan bunuh diri.
Korban KGBO banyak dapat yang mengalami gangguan kecemasan, depresi, bahkan kehilangan minat hidup.
Mereka tak hanya takut membuka media sosial, tapi juga kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan sosialnya.
Dampak ini lebih berat bagi perempuan muda dan remaja yang masih membentuk identitas dirinya.
Rasa malu, takut, dan inferior bisa melekat hingga dewasa, memengaruhi relasi interpersonal, pendidikan, dan karier mereka ke depan.
Ironisnya, korban seringkali disalahkan. Mereka dianggap baper, terlalu lebay, atau mencari perhatian.
Padahal, mereka sedang berjuang untuk mempertahankan martabat dan harga diri.
Di sinilah letak bahayanya, ketika sistem dan budaya sama-sama menyalahkan korban, maka kekerasan bukan hanya dibiarkan, tapi diwariskan.
Jika kekerasan seperti ini terus dinormalisasi, kita sedang membentuk generasi yang tidak lagi peka terhadap perasaan orang lain, serta tidak memiliki batasan moral terhadap apa yang layak dan tidak layak dilakukan terhadap sesama manusia.
Salah satu pertanyaan paling krusial dalam isu ini adalah, siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kekerasan berbasis gender di media sosial?
Jawabannya adalah semua pihak. Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah regulasi yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan daring, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), KUHP, serta UU Penghapusan Kekerasan Seksual (TPKS).
Namun implementasinya belum maksimal. Banyak kasus yang berhenti di tahap pelaporan.
Oleh karena itu, selain memperbaiki regulasi, kita juga butuh pendekatan yang berpihak pada korban, termasuk penyediaan layanan bantuan hukum, psikologis, dan pendampingan selama proses pelaporan.
Sudah terlalu sering kita melihat korban harus “membuat kegaduhan” dulu di media sosial agar mendapatkan perhatian. Harus membuat thread panjang, menangis di video, atau bahkan membuka luka lama secara publik.
Barulah aparat, masyarakat, dan media merespons. Mau sampai kapan? Keadilan tidak boleh bersyarat viral. Kita tidak bisa terus mengandalkan perhatian massa sebagai satu-satunya alat perlawanan.
Negara, institusi, dan masyarakat harus punya sistem yang menjamin keamanan dan keadilan sejak awal, bukan setelah ramai.
Perlu disadari, tanggung jawab menciptakan ruang digital yang aman tidak bisa dibebankan pada korban semata.
Memblokir akun pelaku, menghapus komentar, atau menghindari media sosial hanya menyelesaikan permukaan masalah.
Akar persoalannya ada pada budaya permisif terhadap pelecehan, serta minimnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan secara online.
Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, mulai dari diri sendiri.
Stop menggunakan istilah atau komentar yang merendahkan, seksis, dan melecehkan.
Kedua, edukasi publik tentang KGBO harus diperluas, khususnya bagi generasi muda pengguna aktif media sosial.
Literasi digital tidak cukup hanya sebatas cara menggunakan teknologi, tapi juga etika dan nilai kemanusiaan di dalamnya.
Ketiga, dorong platform digital untuk bertanggung jawab.
Algoritma media sosial harus diberi tekanan untuk tidak memperkuat konten pelecehan.
Laporan pengguna harus ditindaklanjuti dengan serius, bukan hanya formalitas. Keempat, negara tidak bisa diam. Regulasi perlindungan pengguna, khususnya perempuan, harus diperkuat.
Aparat penegak hukum perlu pelatihan khusus agar mampu menangani kasus KGBO dengan perspektif gender yang adil dan empatik.
Ini bukan sekadar tentang konten viral. Ini tentang arah budaya kita ke depan.
Apakah kita ingin membentuk generasi yang kebal empati dan menganggap kekerasan sebagai hiburan? Atau kita ingin membangun masyarakat yang peduli, beradab, dan menolak normalisasi kekerasan, dalam bentuk apa pun?
Mari mulai dari hal kecil.
Tidak menertawakan konten seksis, tidak ikut menyebarkan video yang melecehkan, tidak menyalahkan korban.
Mari lebih banyak mendengar, lebih banyak mendukung, dan lebih banyak bersuara. Karena bercanda dan pelecehan adalah dua hal yang sangat berbeda.
Dan jika kita tak bisa membedakannya, barangkali kitalah masalahnya.
Sudah saatnya kita berhenti menunggu korban untuk viral agar masalah ini mendapat perhatian.
Kita harus bergerak sekarang sebelum lebih banyak lagi yang terluka dalam diam. (*)
*) PENULIS adalah Anggota Generasi Edukasi Nanggroe Aceh (GEN-A) dan Mahasiswa Ilmu Keperawatan USK
KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.
| Refleksi 20 Tahun Damai Aceh: Menanti Peran Anak Syuhada Menjaga Damai Aceh Lewat Ketahanan Pangan |

|
|---|
| Utang: Membangun Negeri atau Menyandera Masa Depan? |

|
|---|
| Melihat Peluang dan Tantangan Potensi Migas Lepas Pantai Aceh |

|
|---|
| Dua Dekade Damai, Rakyat Masih Menanti Keadilan Pengelolaan Sumber Daya Alam |

|
|---|
| Kampung Haji Indonesia dan Wakaf Baitul Asyi |

|
|---|










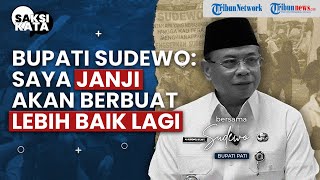





Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.