Opini
Gampong Mandiri Pangan
Gagasan ini mencerminkan kepedulian terhadap kualitas gizi generasi muda, sekaligus upaya menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas SDM seja
DR IR AZHARI MSC, Dosen Departemen Agribisnis-Fakultas Pertanian USK, dan Tim Penulis Buku Pertanian, Kehutanan dan Kemakmuran Petani (2021)
SALAH satu janji politik paling menonjol Presiden Prabowo Subianto dalam Pemilu 2024 adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi murid sekolah di seluruh Indonesia. Gagasan ini mencerminkan kepedulian terhadap kualitas gizi generasi muda, sekaligus upaya menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas SDM sejak usia dini.
Namun, di balik ide yang ambisius ini, muncul pertanyaan mendasar: dari mana bahan pangan bergizi itu akan dipasok? Siapa yang akan menyuplai telur, sayur, ikan, dan daging untuk ratusan ribu dapur MBG yang tersebar di seluruh Indonesia? Dan yang paling penting, bagaimana posisi desa atau gampong dalam konteks Aceh dalam skema besar ini?
Sebagai daerah dengan basis agraris yang kuat, gampong-gampong di Aceh menyimpan potensi besar untuk menopang ketahanan pangan nasional.
Lebih dari 6.500 gampong memiliki struktur sosial, lahan pertanian, sistem produksi pangan, dan sumber daya manusia yang cukup untuk menjadi produsen pangan lokal. Sayangnya, selama ini gampong lebih sering diposisikan sebagai sasaran program, bukan mitra strategis. Jika pendekatan ini berlanjut dalam implementasi MBG, kita akan kehilangan peluang besar untuk memperkuat kemandirian pangan dari akar rumput.
Secara teoritis, MBG dapat menjadi bagian dari strategi kedaulatan pangan yang menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam siklus produksi, distribusi, dan konsumsi pangan (Patel, 2009; FAO, 2012). Namun, jika pendekatan program ini hanya mengandalkan logika proyek, seperti menyerahkan pengadaan pangan kepada kontraktor besar atau rantai distribusi korporasi pangan, maka manfaatnya tidak akan terasa di desa. Lebih jauh, ini bisa menjadi bentuk ketergantungan baru yang justru bertolak belakang dengan semangat kemandirian.
Potensi gampong Aceh
Potensi pangan di gampong Aceh sebenarnya cukup menjanjikan. Petani hortikultura di Saree Aceh Besar mampu memproduksi sayur-mayur dalam jumlah besar setiap hari. Peternak ayam petelur di Bireuen dan Aceh Utara sudah terbiasa menyuplai kebutuhan telur lokal. Nelayan di pesisir Barat Selatan seperti Aceh Jaya dan Aceh Selatan menangkap ikan segar setiap pagi.
Di daerah pegunungan seperti Aceh Tengah, hasil pertanian seperti kentang, wortel, dan buah lokal juga melimpah. Semua ini menunjukkan bahwa basis produksi pangan lokal telah ada, tinggal bagaimana menjembatani antara produksi di desa dan permintaan yang masif dari dapur MBG.
Masalah utama yang selama ini menghambat desa menjadi pemasok utama adalah lemahnya kelembagaan ekonomi lokal. Banyak gampong belum memiliki Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang kuat atau koperasi tani yang terorganisir.
Akses ke pasar juga masih terbatas. Sistem logistik tidak efisien dan banyak pelaku usaha desa kesulitan menjaga standar kualitas dan kontinuitas pasokan. Maka dari itu, jika MBG ingin sukses sekaligus memperkuat ekonomi desa, perlu ada intervensi kebijakan yang menjadikan gampong sebagai mitra penyedia pangan, bukan sekadar lokasi konsumsi.
Beberapa inisiatif lokal bisa menjadi inspirasi. Di Aceh Barat Daya, koperasi wanita tani dilaporkan secara rutin menyuplai sayuran organik ke warung makan dan sekolah-sekolah mitra (P3A Abdya, 2022). Aktivitas ini menunjukkan bagaimana kelompok perempuan dapat berperan aktif dalam sistem pangan lokal sekaligus memperkuat ekonomi rumah tangga melalui pertanian berkelanjutan.
Sementara itu, di Kabupaten Pidie, sejumlah Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) mulai menjajaki usaha peternakan ayam petelur secara komunal. Meskipun skalanya masih terbatas dan bersifat percontohan di beberapa gampong, inisiatif ini menggambarkan semangat inovasi ekonomi desa yang patut mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah maupun mitra pembangunan.
Di kawasan pesisir Banda Aceh, tepatnya di Gampong Lampulo, kelompok nelayan telah lama menjalankan sistem pemasaran langsung ke pasar tradisional dan koperasi nelayan (DKP Banda Aceh, 2023). Pola ini tidak hanya memperpendek rantai distribusi tetapi juga memberikan harga jual yang lebih adil bagi nelayan. Ketiga contoh tersebut menunjukkan adanya dinamika positif di tingkat akar rumput dalam mengelola usaha berbasis sumber daya lokal.
Namun, perlu dicatat bahwa keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada dukungan kelembagaan, akses pasar, serta konsistensi pendampingan teknis. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan lokal seperti koperasi, BUMG, dan kelompok tani atau nelayan seyogianya menjadi perhatian utama dalam desain kebijakan pembangunan berbasis masyarakat.
Opini Hari Ini
Dr Ir Azhar MSc
Penulis Opini
Gampong Mandiri Pangan
Presiden Prabowo Subianto
Janji Politik
Janji Politik Prabowo
| Masa Depan Pertanian Aceh Pascabanjir |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Muhammad-Yasar-OKE.jpg)
|
|---|
| Transformasi Digital dan Stabilitas Makroekonomi Mesin Penggerak Pertumbuhan Ekonomi |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/apridarrr.jpg)
|
|---|
| Polri sebagai Penopang Harapan di Tengah Bencana |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Jabbar-ookkl.jpg)
|
|---|
| Belajar Sabar dari Aceh yang Terluka |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Prof-M-Shabri-Abd-Majid-Prof-Bidang-Ilmu-Ekonomi-USK-Banda-Aceh.jpg)
|
|---|
| Saat Pemimpin tak Hadir di Tengah Bencana: Dilema Etika Antara Hak Personal & Tanggung Jawab Publik |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/bencana-0okl.jpg)
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Dr-Ir-Azhar-MSc.jpg)








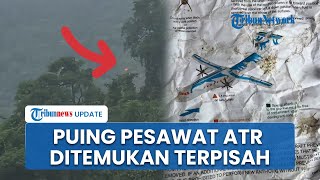
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Isa-Alima-_koperasi-merah-putih_2025.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Prof-M-Shabri-Abd-Majid-Prof-Bidang-Ilmu-Ekonomi-USK-Banda-Aceh.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Muhammad-Yasar-OKE.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Iwan-Daumy-BARU.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Adam-Malik-Awards-2026-Serambi-Indonesia.jpg)