Opini
Urgensi Revisi UUPA di Tengah Polemik Perpanjangan Dana Otonomi Khusus Aceh
Ini menegaskan bahwa penambahan alokasi fiskal tanpa perbaikan sistemik hanya akan memperbesar inefisiensi.
Efatha Filomeno Borromeu Duarte, Akademisi Ilmu Politik Universitas Udayana & Pendiri Malleum Iustitiae Institute
SELAMA periode 2008-2024, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Aceh senilai lebih dari Rp 103,8 triliun sebagai instrumen vital pascaresolusi konflik. Namun, terjadi kesenjangan implementasi yang signifikan: alokasi fiskal masif ini belum menghasilkan outcome pembangunan yang sepadan.
Dengan angka kemiskinan yang stagnan di 14,7 persen dan kualitas infrastruktur serta modal manusia di bawah rata-rata nasional, persoalan fundamental tidak terletak pada kuantitas dana, melainkan pada efikasi tata kelola. Penyerapan anggaran yang rendah secara kronis dan lemahnya akuntabilitas berbasis kinerja menjadi hambatan utama. Momentum revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan kesempatan krusial untuk melakukan reorientasi kebijakan, dari sekadar menambah alokasi menjadi mentransformasi kerangka kerja Otsus agar fokus pada kinerja dan dampak terukur.
Data menunjukkan sebuah paradoks. Di satu sisi, komitmen fiskal sangat tinggi. Di sisi lain, kapasitas penyerapan anggaran pemerintah daerah secara konsisten rendah, dengan realisasi menurun dari 87,6 % (2019) hingga 82,4 % (2021). Hal ini menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) senilai triliunan rupiah dan dana produktif yang gagal ditransformasikan menjadi layanan publik dan program pembangunan. Akibatnya, indikator kesejahteraan kunci tidak menunjukkan perbaikan signifikan. Ini menegaskan bahwa penambahan alokasi fiskal tanpa perbaikan sistemik hanya akan memperbesar inefisiensi.
Ketergantungan struktural
Kegagalan memaksimalkan Dana Otsus bersumber dari dua tantangan sistemik: Pertama, Defisiensi Siklus Anggaran. Proses perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi menunjukkan "permasalahan klasik" berupa ketidaksinkronan antara program dan prioritas pembangunan strategis. Akuntabilitas cenderung berhenti pada pemenuhan syarat administratif (laporan dan kwitansi), bukan pada evaluasi dampak (outcome evaluation) terhadap penurunan kemiskinan atau peningkatan daya saing ekonomi lokal.
Kedua, Ketergantungan Struktural. Perekonomian Aceh masih ditopang oleh sektor primer (pertanian) dan belanja pemerintah. Sektor industri pengolahan yang bernilai tambah tinggi masih sangat minim (<5>
Usulan kenaikan alokasi Dana Otsus dalam draf revisi UUPA harus disikapi secara kritis. Tanpa adanya prasyarat perbaikan tata kelola, kebijakan ini berisiko menjadi solusi yang tidak menjawab akar masalah. Oleh karena itu, momentum legislasi ini harus dimanfaatkan sebagai policy window untuk mengintegrasikan mekanisme baru yang mengikat alokasi dana dengan kinerja. Tujuannya adalah memastikan setiap rupiah yang dialokasikan memiliki efikasi maksimal dalam mencapai target Visi Aceh 2045.
Untuk mentransformasi dana Otsus dari sekadar transfer fiskal menjadi instrumen pembangunan yang efektif, direkomendasikan tiga pilar reformasi untuk diintegrasikan ke dalam kerangka UUPA: Pertama, Mengimplementasikan Skema Alokasi Berbasis Kinerja (Performance-Based Grant). Struktur dana diubah menjadi hibrida, yaitu 70 % sebagai hibah blok (block grant) untuk pelayanan dasar dan 30 % sebagai hibah berbasis kinerja (performance grant). Pencairan hibah kinerja ini dikondisikan pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang jelas, seperti tingkat penurunan kemiskinan, laju pertumbuhan investasi swasta, dan peningkatan Indeks Modal Manusia.
Proses evaluasi IKU harus dilakukan oleh komite independen untuk menjaga kredibilitas dan objektivitas. Kedua, Mewajibkan Alokasi Belanja Modal Produktif. Menetapkan mandat alokasi minimum (misalnya 40 % ) dari dana Otsus untuk belanja modal yang bersifat produktif dan strategis. Fokusnya adalah infrastruktur pendukung hilirisasi komoditas unggulan (kopi, sawit), modernisasi logistik dan pelabuhan, serta investasi pada ekosistem ekonomi digital dan talenta.
Setiap proyek harus didasari studi kelayakan (feasibility study) yang kredibel dan selaras dengan Rencana Induk Pembangunan daerah untuk mencegah proyek mangkrak. Ketiga, Menyusun Peta Jalan Kemandirian Fiskal (Fiscal Independence Roadmap). Memformulasikan skema phasing-out Dana Otsus dalam kerangka waktu 20-30 tahun.
Pengurangan persentase dana dari pusat secara gradual harus diiringi dengan target peningkatan PAD yang terukur dan wajib dicapai oleh pemerintah daerah. Peta jalan ini menciptakan urgensi positif untuk melakukan reformasi birokrasi, perbaikan iklim investasi, dan inovasi dalam penggalian sumber-sumber pendapatan baru, sebagai jalan menuju kemandirian dan martabat fiskal.
Para pemangku kebijakan kini berada di ujung jalan, mempertahankan status quo yang melanggengkan ketergantungan atau melakukan reformasi fundamental menuju efektivitas dan kemandirian. Pilihan kedua, meskipun menantang, adalah satu-satunya jalan untuk memastikan dana Otsus benar-benar bertransformasi menjadi lokomotif ekonomi yang mensejahterakan rakyat Aceh secara terukur berkelanjutan. Keberanian tata kelola politik untuk mengeksekusi reformasi tata kelola ini akan menjadi penentu warisan dari salah satu investasi perdamaian terpenting dalam sejarah Indonesia.
Revisi UUPA
Sekarang ini ramai para elite dan rakyat Aceh menyuarakan revisi UUPA. Niatnya pasti baik. Dalam drafnya, terdapat usulan krusial untuk mengubah Pasal 183, yakni menaikkan alokasi Dana Otsus menjadi setara 2,25?ri plafon Dana Alokasi Umum Nasional. Ini adalah sebuah niat baik untuk akselerasi pembangunan.













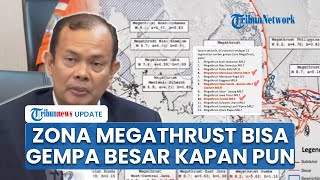



Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.