Kupi Beungoh
Melihat Peluang dan Tantangan Potensi Migas Lepas Pantai Aceh
Secara regional, Aceh terletak di ujung utara Cekungan Sumatera yang terbagi menjadi beberapa sub-cekungan berbeda.
*) Oleh: Prof. Dr. Ir. Muhammad Irham, S.Si, M.Si.
ACEH dipandang memiliki potensi besar di sektor migas berkat karakter geologi yang kompleks.
Secara regional, Aceh terletak di ujung utara Cekungan Sumatera yang terbagi menjadi beberapa sub-cekungan berbeda.
Misalnya, cekungan Cekungan Sumatera Utara yang membentang dari Aceh Tamiang hingga Pidie serta Laut Aceh (Selat Malaka), sedangkan di lepas pantai barat Aceh terdapat struktur cekungan busur muka Simeulue (fore-arc Simeulue).
Kedua ini struktur kaya sedimen hingga tua yang berpotensi mengandung hidrokarbon.
Studi terkini menunjukkan bahwa wilayah perairan barat Aceh (Cekungan Busur Muka Simeulue) sangat prospektif, termasuk indikasi adanya gas hidrat di sedimen laut dalam.
Selain itu, karakteristik geologi ini didukung oleh penelitian geokimia, misalnya, formasi Batuan Baong Bawah (Miosen Tengah) di Lhokseumawe (Sumatera Utara/Aceh) mengandung batubara aktif (TOC sekitar 1,5 persen, jenis kerogen II–III) yang telah menjadi sumber (source) minyak lokal.
Kondisi ini menandakan Aceh memiliki unsur penting dalam sistem perminyakan (source, reservoir, migration, trap dan seal) yang cukup memungkinkan akumulasi migas.
Eksplorasi dan Cadangan Migas Aceh
Beberapa lapangan migas utama telah ditemukan di Aceh, dan eksplorasi terus berlanjut.
Contohnya Lapangan Arun di pantai utara Aceh (Lhokseumawe) adalah lapangan gas raksasa yang sejak 1975 sudah memproduksi gas dan kondensat.
Data lama menyebut Arun memiliki cadangan terbukti sekitar 16 TCF (triliun kaki⊃3;) gas, meski produksinya kini telah menurun.
Selain Arun, North Sumatra Offshore (NSO) yang terletak dekat Aceh Selatan juga tercatat memiliki cadangan gas besar, sekitar 5 TCF.
Baru-baru ini, eksplorasi di perairan Aceh menunjukkan penemuan cadangan baru.
Misalnya, Pertamina Hulu Energi North Sumatera Offshore melaporkan bahwa sumur eksplorasi di Lhokseumawe (Desember 2022–Maret 2023) menemukan gas hidrokarbon dan kondensat dengan aliran gas hingga 12,65 MMSCFD.
Penemuan ini memanfaatkan formasi karbonat Formasi Malaka dalam.
Di sektor lepas pantai, konsorsium internasional juga melaporkan penemuan besar, seperti Mubadala Energy (UEA) menemukan potensi gas lebih dari 6 TCF di Blok Andaman Selatan (Lepas Pantai Aceh), dengan rencana produksi dimulai sekitar tahun 2028.
Lebih jauh, dalam konferensi akhir 2024 BPMA (Badan Pengelola Migas Aceh) mengungkap bahwa konsorsium Repsol–BPMA–Mubadala–Harbour Energy menemukan gas cadangan sekitar 9 TCF di blok Andaman Barat Aceh, sehingga total potensi cadangan migas lepas pantai Aceh diperkirakan mencapai sekitar 24 TCF.
Faktor teknis lain yang patut diperhatikan adalah potensi gas hidrat (metana padat) di Aceh Barat. Studi geofisika menduga adanya zona stabilitas gas hidrat di cekungan busur muka Simeulue (lepas pantai barat Aceh).
Secara nasional, cadangan gas hidrat sangat besar, diperkirakan mencapai 3.000 TCF di seluruh Indonesia yang menandakan bahwa sumber energi non-konvensional ini bisa menjadi masa depan migas Aceh jika teknologi eksplorasi dan produksi gas hidrat sudah matang.
Dampak terhadap Pembangunan Ekonomi Aceh
Potensi migas Aceh diharapkan meningkatkan pendapatan dan pembangunan daerah.
Penerimaan migas merupakan sumber utama APBD Aceh (pajak dan bagi hasil), dan cadangan besar seperti yang disebut di atas memberi peluang peningkatan anggaran.
Misalnya, PT Pembangunan Aceh (PEMA, BUMD migas) melaporkan bahwa 60 % gas migas Aceh saat ini diserap untuk industri pupuk (Pupuk Iskandar Muda), yaitu sekitar 46 MMSCFD dari total produksi 96 MMSCFD.
Hal ini menunjukkan migas sudah digunakan untuk mendukung industri hulu lokal dan ketahanan pangan.
Ke depan, cadangan baru bisa memicu investasi besar, seperti fasilitas LNG kecil, pembangkit listrik gas, atau pabrik pupuk tambahan, yang pada gilirannya menyerap energi kerja lokal.
Namun, Aceh yang masih menghadapi tingkat kemiskinan yang relatif tinggi (sekitar 10–15 % populasi) perlu memanfaatkan migas untuk pembangunan berkelanjutan.
Oleh karena itu, keberhasilan ekonomi jangka panjang menuntut diversifikasi usaha.
PEMA misalnya mulai merambah sektor pangan (olah hasil tani/peternakan), perikanan, kehutanan, properti, dan energi terbarukan (proyek panas bumi Seulawah).
Program hilirisasi kelapa sawit, perdagangan kopi, dan pengembangan energi hijau juga diutamakan untuk membuka lapangan kerja baru.
Selain itu, Aceh berencana menerapkan teknologi penangkapan karbon di Lapangan Arun untuk mendukung target net-zero Indonesia sekaligus membuka sumber pendapatan baru (emisii rendah).
Pengelola migas di Aceh juga mmenekankan pentingnya reinvestasi pendapatan migas ke sektor lain. Statistik Aceh menunjukkan sektor pertambangan (termasuk migas) menyumbang ~7,1 % PDB Aceh (Q3 2024).
Ahli ekonomi Aceh menekankan bahwa pendapatan dari migas sebaiknya digunakan untuk mengembangkan industri, pariwisata, dan teknologi local sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan.
Tantangan dan Pengelolaan Lingkungan
Meskipun menjanjikan, pengembangan migas Aceh tidak lepas dari tantangan teknis dan lingkungan.
Secara geologi, sedimentasi di cekungan-cekungan Aceh sangat tebal dan kompleks, yang memberikan interpretasi seismik.
Data seismik 2D lawas (jauh antar lintasan) dinilai belum mampu untuk menghitung cadangan secara akurat.
Kini perlu dilakukan survei 3D dan uji pengeboran untuk memvalidasi sumber dan perangkap migas.
BPMA mencatat tantangan pembangunan migas Aceh terletak pada lamanya aktivitas seismik (30–40 tahun yang lalu).
Kini perusahaan migas (mis. PGE di Aceh Utara) kembali menjalankan survei seismik ke depan, dengan harapan temuan baru dapat dieksploitasi 5–10 tahun mendatang.
Dalam aspek lingkungan, eksplorasi migas lepas pantai harus diperketat pemantauan agar tidak merusak ekosistem pesisir dan laut.
Beberapa kelompok lokal sudah memperingatkan dampak survei dan eksploitasi terhadap mata pencaharian nelayan dan hutan bakau.
Oleh karena itu, praktik terbaik seperti menepati studi lingkungan seperti AMDAL, membatasi dampak gangguan bawah laut (untuk mamalia laut), serta menyiapkan rencana mitigasi tumpahnya minyak sangat penting.
Di sisi lain, pengembangan gas sebagai bahan bakar bersih (lebih rendah karbon daripada bahan bakar fosil cair) dapat menjadi energi transisi.
Aceh juga dapat memanfaatkan potensi carbon capture and storage (CCS) di cekungan tua (misalnya Lapangan Arun) untuk mengurangi emisi sekaligus memperpanjang umur migasnya.
Pengelola dan pemerintah daerah perlu mengawasi ketatnya kegiatan migas serta melibatkan masyarakat lokal agar hasilnya benar-benar meningkatkan kesejahteraan wilayah, bukan hanya pendapatan jangka pendek.
Sebagai penutup, dapat dikatakan bahwa Aceh memiliki cadangan migas onshore dan offshore yang sangat prospektif, mulai dari formasi karbonat Miosen (Arun) hingga cekungan perairan dalam Simeulue dan Andaman Selatan.
Temuan eksplorasi terbaru (PHE, Repsol–Mubadala, dll.) mengkonfirmasi potensi gas raksasa >10–20 TCF di lepas pantai Aceh.
Dengan cadangan sebesar itu, pengembangan migas Aceh berpeluang signifikan mendorong pendapatan daerah dan lapangan kerja.
Namun, keberhasilannya menuntut strategi holistik: investasi besar untuk seismik dan pengeboran, kebijakan ramah investasi, serta fokus pada penggunaan migas secara produktif.
Pulihnya perekonomian Aceh tidak cukup hanya mengandalkan migas, pemerintah dan BUMD seperti PEMA harus menyiapkan diversifikasi ke bidang pertanian, perikanan, energi terbarukan dan infrastruktur untuk memastikan pertumbuhan inklusif.
Secara keseluruhan, pengembangan migas Aceh harus berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
Partisipasi Aceh dalam forum migas nasional (misalnya IPA Convex 2025) menunjukkan komitmen untuk memperkenalkan potensi lokal sekaligus menarik investasi.
Jika dikelola dengan hati-hati, kekayaan migas Aceh dapat menjadi pendorong kemajuan ekonomi daerah sekaligus tetap menjaga keanekaragaman hayati laut dan darat Aceh. (*)
*) PENULIS adalah Geologist dan Guru Besar di Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala, sekaligus Pemerhati Energi dan Lingkungan
KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.
BACA TULISAN KUPI BEUNGOH LAINNYA DI SINI















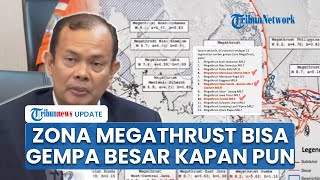




Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.