Pojok Humam Hamid
Indonesia dan BRICS: Posisi Bebas Aktif dan Ketidaksenangan AS
Di tengah semua itu, bendera Merah Putih Indonesia berkibar. Bukan di pinggir lapangan, tapi di tengah gelanggang BRICS.
Oleh: Ahmad Humam Hamid*)
SEJARAH kadang bergerak seperti jarum jam yang longgar—berputar tergesa di satu detik, melambat di detik berikutnya, lalu tiba-tiba melompat melewati angka-angka yang dulu dianggap tak terbayangkan.
Tahun 2025 mungkin akan dikenang sebagai salah satu lompatan itu.
Ketika BRICS--forum ekonomi yang dulu dipandang sebagai klub eksotik negara-negara berkembang--tiba-tiba menjadi magnet bagi kekuatan menengah yang ingin mengubah peta permainan dunia.
Dan di tengah semua itu, bendera Merah Putih Indonesia berkibar.
Bukan di pinggir lapangan, tapi di tengah gelanggang.
Di sebuah ruang pertemuan berlampu gantung kristal di Rio de Junairo, bahasa yang terdengar bercampur: Portugis, Rusia, Hindi, Mandarin, Arab, dan bahasa Indonesia.
Di ujung ruangan, bendera-bendera BRICS berkibar seperti kanvas masa depan yang sedang dilukis ulang.
Dari luar, hujan tipis membasahi jalan, tapi di dalam, udara dipenuhi senyum diplomatis, bisik-bisik strategi, dan tatapan penuh kalkulasi.
Masuknya Indonesia ke BRICS bukan sekadar catatan kaki dalam buletin diplomatik.
Ini adalah pesan, bahwa kita tidak puas lagi hanya menjadi penonton ketika peta ekonomi global digambar ulang.
BRICS hari ini mencakup lebih dari 45 persen populasi dunia, 36 % PDB global, dan hampir 20 % perdagangan internasional.
Lebih penting lagi, ia menjadi simbol keinginan negara-negara non-Barat untuk berdagang, berinvestasi, dan bernegosiasi di luar orbit tunggal dolar AS.
Washington tentu mendengar pesan itu, dan tidak menyukainya.
Baca juga: Trump Ngamuk ke BRICS, Ancam Kenakan Tarif Tambahan 10 Persen ke Anggotanya, Indonesia Terancam
Ujian awal bagi Indonesia
Bagi Amerika, BRICS bukan sekadar forum ekonomi.
BRICS adalah gejala, tanda bahwa monopoli kekuasaan finansial yang dibangun pasca-Perang Dunia II mulai retak.
Dan kini, ancaman datang langsung dari Donald Trump: tarif tambahan 10 % untuk negara yang “menyelaraskan diri” dengan kebijakan anti-Amerika ala BRICS.
Tarif, bagi Trump, bukan sekadar instrumen fiskal. Itu adalah senjata, sama tuanya dengan sejarah perdagangan modern.
Inggris menggunakannya di abad ke-19 untuk melindungi industri tekstilnya dari kapas India.
Amerika sendiri pernah memanfaatkan tarif Smoot-Hawley tahun 1930--yang malah memperdalam Depresi Besar--sebagai dinding ekonomi yang menghalangi impor.
Uni Soviet menimpali dengan tarif balasan di tahun-tahun awal Perang Dingin.
Kini, pola itu terulang, tapi dengan cita rasa abad ke-21.
Tarif bukan hanya soal uang, tapi sinyal politik, pengukur keberanian, dan tes loyalitas.
Trump tahu tarif adalah peluru yang bisa memukul dua sasaran sekaligus.
Ia menekan ekonomi lawan dan mengirim pesan ke penonton global.
Trump menghukum lewat pasar, sambil memberi pesan politik.
Pilih kami-AS, atau bayar harga.
Bagi Indonesia, ini adalah ujian awal sebagai anggota penuh BRICS.
Prabowo bisa saja membalas dengan retorika keras, memukul meja, mengklaim kedaulatan di hadapan kamera.
Tapi itu akan memberi Trump narasi yang ia inginkan, bahwa BRICS memang musuh.
Prabowo bisa saja diam, tapi diam di dunia sekarang dibaca sebagai tanda takut.
Indonesia memilih jalan yang, bagi diplomat kawakan, terdengar seperti musik klasik Mozart.
Indonesia menegaskan bahwa BRICS bukan blok anti-AS, melainkan forum kerja sama yang terbuka.
Retorik, aman, tapi penuh kalkulasi.
Bebas aktif versi abad ke-21.
Di balik kalimat itu ada realitas keras yang tak terbantahkan.
AS adalah pasar ekspor utama Indonesia, USD 25 miliar pada 2024, dengan surplus di pihak kita.
Tarif 10 % akan memukul tekstil, alas kaki, furnitur--sektor yang memberi makan jutaan keluarga Indonesia.
Tapi Prabowo juga tahu, BRICS adalah pasar yang sama potensialnya, bahkan dalam jangka panjang bisa menjadi lebih besar.
Nikel ke Cina, batu bara ke India, kopi ke Rusia, karet ke Brasil.
Dan ada kartu lain yakni yang amat sangat penting dan strategis, pangan.
BRICS adalah lumbung pangan dunia--Brasil dengan kedelai dan gula, Rusia dengan gandum, India dengan beras, Cina dengan jagung, Afrika Selatan dengan buah.
Dalam krisis pangan global, Indonesia akan memiliki akses prioritas ke pasokan, dan ini adalah senjata strategis.
Indonesia, yang masih bergantung pada impor gandum, gula, kedelai, tak boleh lalai, apalagi mengabaikan manfaat ini.
Jaringan perdagangan adalah benteng menghadapi badai.
Gelanggang Penuh Persaingan
BRICS, jika dimainkan dengan cerdas, bisa menjadi jaringan versi modern, bukan dengan layar dan dayung, tapi dengan diplomasi dan perjanjian dagang.
Namun, masuk BRICS juga berarti masuk gelanggang penuh persaingan kepentingan.
Di sana ada Cina dan India yang saling curiga, Rusia yang berkonflik dengan Barat, Brasil dengan politik domestik yang labil.
Indonesia harus memastikan, datang ke meja itu dengan agenda sendiri, bukan sebagai penumpang di kapal orang lain.
Ancaman tarif Trump justru menjadi pengingat bahwa di dunia sekarang, keamanan ekonomi tidak cukup dijaga dengan hubungan bilateral yang hangat.
Ia butuh kaki cadangan, pasar alternatif, jalur pasokan diversifikasi, dan kekuatan domestik yang sanggup menyerap guncangan.
Diplomasi, dalam arti ini, adalah seni mengatur jarak.
Probowo-Indonesia, harus cukup dekat dengan Washington untuk tetap berdagang, tapi cukup jauh untuk tidak terseret ke dalam orbit perintah tunggal.
Sama halnya, Indonesia harus cukup aktif di BRICS untuk memetik manfaatnya, tapi cukup bebas untuk tidak ikut terbawa ambisi yang bukan milik kita.
Bayangkan sebuah pohon yang tumbuh di perbatasan gurun dan hutan.
Dari satu sisi, matahari memberi energi dan peluang.
Dari sisi lain, angin panas membawa badai kecurigaan dari kawan lama.
Pohon itu hanya akan bertahan jika akarnya menghujam dalam, ke tanah ekonomi domestik yang kuat, pasar ekspor yang terdiversifikasi, dan politik luar negeri yang konsisten pada kompas bebas aktif.
Bebas aktif bukan artefak museum.
Ia adalah mekanisme bertahan yang lahir dari sejarah panjang kita, dari KTT Non Blok-Asia Afrika, Bandung 1955.
Pertemuan yang digagas Sukarno itu menantang dua blok besar, hingga manuver Orde Baru yang menyeimbangkan Barat dan Timur.
Ini adalah pengingat bahwa di dunia yang makin bising, suara yang tenang justru bisa memegang kendali.
Belajar menari di antara dua matahari
Trump mungkin berharap ancamannya akan membuat Indonesia ragu.
Tapi sejarah sering berpihak pada mereka yang mengubah tekanan menjadi peluang.
Jika dimainkan dengan tepat, tarif itu bisa menjadi katalis untuk mempercepat diversifikasi ekonomi dan memperkuat aliansi baru.
Ketika arsip sejarah abad ke-21 nanti dibuka, mungkin orang akan melihat 2025 bukan sebagai tahun Indonesia tunduk pada satu kutub, tapi sebagai tahun kita belajar menari di antara dua matahari.
Indonesia tetap harus mampu menjaga jarak agar tidak terbakar, tapi cukup dekat untuk menyerap panasnya.
Sebuah langkah yang tidak hanya menjaga kita tetap hidup di panggung dunia, tapi membuat kita relevan di drama besar sejarah yang sedang berlangsung.
*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.
Artikel dalam rubrik Pojok Humam Hamid ini menjadi tanggung jawab penulis.
| Tambang Rakyat di Aceh: Potensi, Prospek, dan Tantangan |

|
|---|
| Proposal Trump, Otoritas Teknokratis, dan Prospek Damai Palestina |

|
|---|
| MSAKA21 - Kerajaan Lamuri: Maritim, Inklusif, dan Terbuka – Bagian XII |

|
|---|
| Kekonyolan Bobby dan “Hikayat Ketergantungan”: Yunnan, Bihar, Minas Gerais, dan Aceh |

|
|---|
| Ironi Palestina: Koalisi Keuangan Internasional dan Retak Internal Berkelanjutan |

|
|---|








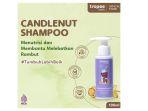

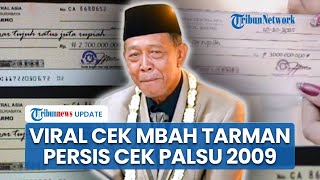



Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.