Kupi Beungoh
Restorative Justice dan Peradilan Adat, Antara Barang Baru dan Tradisi Turun Temurun di Aceh
Terkadang penyelesaian melalui peradilan adat, seolah dianggap kurang ‘bertaring’ jika berhadapan dengan hukum formal.
Tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat
Tidak berdampak konflik sosial
Tidak berpotensi memecah belah bangsa
Tidak bersifat radikalisme dan separatism
Dan bukan pelaku pengulangan (residivis) tindak pidana
Serta bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.
Sedangkan persyaratan formil yang mesti dipenuhi diantaranya; sudah ada perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali kasus tindak pidana narkoba, adanya pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.
Selebihnya, diperlukan formalitas berupa surat kesepakatan perdamaian secara tertulis dari para pihak.
Sedangkan pada tingkat kejaksaan, persyaratan RJ diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15/2020 yaitu:
a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).
Baca juga: Fungsikan Peradilan Adat untuk Cegah Duel Maut
RJ dan Peradilan Adat
Apabila kita kaitkan dengan penyelesaian sengketa melalui peradilan adat, konsep RJ bukan barang baru bagi kita.
Dalam masyarakat kita (Aceh), konsep “uleu beumatee ranteng bek patah” (ular harus mati, ranting pemukul tidak patah) adalah penyelesaian sengketa yang telah memperhatikan kepentingan kedua belah pihak.


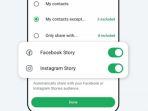






![[FULL] Demo Buruh Kepung Senayan, Said Iqbal: DPR Parah, RUU Setahun Panja Doang, Kasihan Presiden](https://img.youtube.com/vi/TGRtOGQV2Z4/mqdefault.jpg)




