Kupi Beungoh
Dari Pica ke Stecu, Dek Tia pun Bernyanyi: Catatan Sosial atas Irama, Budaya, & Tanggung Jawab Kita
Fenomena ini secara sosiologis mencerminkan konsep glokalisasi pertemuan antara budaya global dan kearifan lokal.
Perpaduan ini bukan hanya soal estetika suara, tapi juga mencerminkan realitas komunikasi masyarakat Aceh masa kini yang sering menggunakan dua bahasa secara bergantian dalam kehidupan sehari-hari.
Campuran bahasa tersebut memberi warna lokal yang kuat sekaligus mudah diterima oleh pendengar yang lebih luas, menjadikan lagu ini sebagai jembatan budaya yang menghubungkan tradisi dengan modernitas, serta simbol identitas yang fleksibel di era globalisasi.
Di sini, musik berfungsi bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai narasi sosial yang mencerminkan cara masyarakat menertawakan, menyindir, dan merayakan diri mereka sendiri.
Kita hidup dalam masyarakat yang tumbuh dari lisan pantun, syair, dan humor adalah bagian dari identitas sosial kita. Maka jangan heran jika lirik-lirik ringan itu bisa membuat orang tertawa sekaligus terngiang.
“Pica-pica” misalnya, tidak punya makna jelas secara harfiah, tapi mengandung daya tarik fonetik yang kuat, seperti suara bayi menyebut sesuatu dengan lucu. Di platform seperti TikTok, muncul pula lagu Minang versi remix DJ seperti “Galodo Kampuang Jo Nagari” yang viral setelah digunakan dalam konten lipsync oleh sejumlah figur muda populer, termasuk Aishar dan Fuji.
Meskipun mereka bukan pencipta atau penyanyi lagu tersebut, kemunculan wajah-wajah familiar di balik konten kreatif itu memperkuat daya sebar lagu dan membuat irama Minang memasuki ruang-ruang digital secara masif.
Fenomena ini menunjukkan bagaimana budaya lokal dapat mengalami revitalisasi digital, berubah bentuk tanpa kehilangan identitas, dan esensinya jelas lagu-lagu ini menyambung keterikatan emosi pemirsa dengan kampung halaman, kesadaran kita tentang betapa kayanya Indonesia dengan ragam Bahasa semeski lewat lipsync dan irama DJ.
Namun di sinilah letak kerentanannya, makna bisa ditafsirkan secara bebas, dan sayangnya tidak semua tafsir membawa kebaikan.
Dalam ruang digital yang sangat cair, ambiguitas bisa membuka celah eksploitasi, terutama jika dikaitkan dengan konten visual yang provokatif. Maka kita butuh literasi budaya. Bukan hanya tahu dari mana lagu berasal, tapi juga paham konteks sosialnya.
Viralitas yang Harus Didampingi
Fenomena ini memang menunjukkan kreativitas luar biasa. Lagu-lagu daerah yang sebelumnya tak terdengar kini kembali menggema berkat format remix dan media sosial. Tapi, kreativitas juga membawa risiko, terutama ketika musik berubah jadi alat komodifikasi instan.
Hari ini, sebuah lagu bisa viral hanya karena satu potongan lirik yang lucu atau gerakan yang heboh. Bukan karena musikalitas atau pesan di dalamnya. Akibatnya, banyak kreator yang tergoda untuk “mencari celah” membuat konten yang semakin sensasional agar cepat dikenal, meski harus mengorbankan etika atau norma budaya.
Etika di sini bukan hanya soal sopan atau tidak. Tapi lebih pada bagaimana kita memahami musik sebagai bagian dari ruang publik. Apakah pantas anak kecil berjoget dengan gerakan dewasa demi FYP? Apakah lagu daerah boleh diubah seenaknya hanya demi views?
Ini bukan sekadar soal moral, tapi juga soal tanggung jawab sosial. Kreativitas tanpa batas memang menggembirakan. Tapi dalam masyarakat yang beragam dan kompleks seperti Indonesia, kita butuh batasan yang dibentuk oleh kesadaran bersama. Karena pada akhirnya, budaya bukan hanya untuk ditonton tapi untuk dimaknai dan diwariskan.
TikTok dan media sosial lainnya kini menjadi panggung utama budaya pop lokal. Lagu seperti “Stecu-Stecu” yang dulunya hanya populer di lingkup komunitas, kini bisa viral dalam hitungan jam. Tapi semakin luas penyebarannya, semakin besar pula tanggung jawabnya.











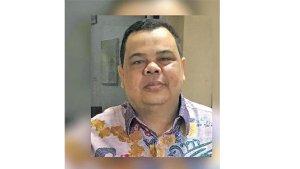








Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.