Pojok Humam Hamid
Serial MSAKA21: Membaca Sejarah Aceh dengan Kacamata Abad ke-21 – Bagian 1
Tulisan yang berpenampilan serial ini saya beri judul “Membaca Sejarah Aceh dengan Kacamata Abad ke-21”, selanjutnya disingkat MSAKA21.
Oleh: Ahmad Humam Hamid*)
HARI ini adalah awal dari sebuah pengembaraan intelektual yang belum saya tahu kapan akan berakhir.
Saya, insya Allah, akan menulis setiap akhir pekan--semampu saya--sesuatu tentang sejarah Aceh, bukan sebagai laporan akademik, bukan pula sebagai doktrin identitas.
Tulisan yang berpenampilan serial ini saya beri judul “Membaca Sejarah Aceh dengan Kacamata Abad ke-21”, selanjutnya disingkat MSAKA21.
Sejarah Aceh bukanlah kitab suci.
Ia tidak turun dari langit dan tidak boleh dibacakan dengan nada khusyuk sambil menundukkan kepala.
Sejarah Aceh, sebagaimana sejarah mana pun di dunia, adalah arena pertempuran ingatan--antara yang ingin dilupakan dan yang ingin dipertahankan, antara mereka yang dulu memegang kuasa dan mereka yang tak pernah ditulis.
Serial yang akan saya tulis bukanlah upaya memuja, melainkan membongkar.
Membaca sejarah Aceh dengan kacamata abad ke-21 bukan berarti mengganti lensa dengan yang lebih terang, tapi mungkin justru lebih buram, karena hanya dengan kabut kita bisa melihat bahwa masa lalu bukan peta datar, melainkan ladang ranjau.
Baca juga: Dana Otsus: Apa Beda “Penyakit Belanda” dan “Penyakit Aceh”?
Pelajaran untuk Gen-Z
Saya menulis untuk mereka yang akan hidup lebih lama dari saya.
Generasi Z Aceh dan Indonesia yang sekarang disodori identitas siap saji, slogan kosong, dan monumen tanpa makna.
Mereka berhak bertanya.
Mengapa kita dikuliahi tentang perang, tapi tidak tentang perdamaian yang dibangun perempuan?
Mengapa kita hafal nama sultan, tapi tidak tahu siapa yang membangun masjid Indrapuri di atas sebuah kuil kecil tempat umat hindu memuja para dewa?
Mengapa sejarah selalu ditulis dari pinggir meja istana, tapi bukan dari serambi dayah atau pojok pasar?
Jika gen Z merasa bosan membaca sejarah, jangan salahkan mereka.
Mungkin sejarah yang mereka baca memang membosankan, karena ia ditulis untuk mematikan imajinasi, bukan membangkitkannya.
Panggung Global
Sebelum Aceh bernama Aceh, wilayah ini sudah menjadi panggung global.
Fansur di Singkil bukan fiksi.
Ia disebut dalam catatan Arab, Yunani, dan Tionghoa sebagai tempat di mana kayu, rempah, dan manusia bertemu dalam sistem dagang yang lebih tua dari VOC.
Perlak bukan hanya kerajaan kecil.
Ia adalah laboratorium sosial tempat Islam, adat, dan dagang bersintesis.
Samudra Pasai bukan sekadar kerajaan Islam pertama di Nusantara, tetapi mungkin juga pusat intelektual yang menghubungkan Gujarat dan Melaka.
Tapi siapa yang mencatat ini dalam buku pelajaran sejarah?
Ketika Aceh menjadi kekuatan maritim di abad ke-16, itu bukan karena ia kuat, tapi karena ia tahu bagaimana bertahan di tengah kekacauan.
Sultan Iskandar Muda membangun negara bukan dari mimpi besar, tetapi dari pembacaan jeli terhadap ancaman global.
Portugis yang menguasai Melaka, Johor yang tak jelas, dan para pedagang Portugis yang membawa injil dalam peti rempah adalah ancaman lama berkelanjutan yang berubah bentuk semenjak masa Sultan Ali Mughayatsyah.
Karena itulah Iskandar Muda berperang.
Ia berperang karena Islam, karena ingin menjadikan Aceh sebagai pusat perdangan antar bangsa, dan karenanya, Aceh harus menjadi penguasa tunggal Selat Malaka
Tapi ingat, kekuasaan bukanlah cermin keagungan semata.
Di balik mahkota ada pengasingan, pemberontakan, dan suara-suara yang dipaksa diam.
Di situlah sejarah Aceh sejatinya hidup, dalam ketegangan, bukan ketentraman.
Dari Narasi Kolonial Hingga Pemodal yang Menjadi Korban
Ketika kolonialisme datang, Aceh tidak hanya melawan dengan senjata.
Ia melawan dengan doa, dengan hikayat, dengan sistem ekonomi lokal yang coba bertahan di antara peluru dan propaganda.
Tapi kolonialisme yang paling licik adalah yang berhasil menuliskan sejarah musuhnya dengan narasinya sendiri.
Maka Aceh pun diperas ke dalam babak “perlawanan” dan “darah”, seolah seluruh sejarah Aceh adalah soal mengangkat rencong dan tombak.
Padahal, Aceh pernah menjadi tempat lahirnya perdebatan hukum Islam, pemikiran ekonomi wakaf, dan gerakan pendidikan perempuan.
Semua itu hilang dalam narasi yang lebih senang melihat Aceh sebagai daerah “keras kepala” daripada “berkepala tajam.”
Lalu datanglah kemerdekaan dan nasionalisme.
Aceh kembali menjadi catatan kaki, lalu berubah menjadi tajuk utama.
Dari pemodal menjadi korban, lalu menjadi pemberontak, namun kemudian berdamai.
Tak lama kemudian “gaduh” itu tampil lagi.
Kemudian ia bergerak dari wilayah darurat menjadi laboratorium damai.
MoU Helsinki 2005 bukan hanya sekedar perjanjian damai.
Ia adalah jeda sejarah.
Tapi siapa yang berani menulis ulang narasi setelah itu?
Siapa yang berani bertanya mengapa pendidikan tetap mandek, mengapa anak muda pergi ke Malaysia, dan mengapa saudagar kaya sangat sedikit?
Sejarah Aceh bukan berhenti di marwah dan keadilan yang sering disebut, tapi justru baru mulai ketika kita bertanya, marwah dań keadilan untuk siapa?
Membaca sejarah Aceh dengan kacamata abad ke-21 berarti berani mencurigai semuanya.
Siapa yang menulis sejarah Aceh?
Untuk siapa ia ditulis?
Mengapa sebagian nama diabadikan menjadi jalan, dan sebagian lainnya dikubur dalam hikayat yang dilupakan?
Jangan pernah percaya pada buku sejarah yang tak mengajarkan keraguan. Jangan hormati tokoh sejarah yang dijadikan “manusia suci” -tak pernah salah.
Sejarah yang sehat seharusnya adalah sejarah yang membuat para gen Z tak nyaman.
Karena hanya ketidaknyamanan yang melahirkan pikiran baru.
Tak Perlu Dibesarkan dengan Kebohongan
Serial yang akan tampil bukan proyek nostalgia. Saya tidak sedang mencari kejayaan masa lalu untuk dijadikan pelarian.
Aceh tidak perlu dibesarkan dengan kebohongan.
Tapi ia juga tak layak dikecilkan oleh amnesia.
Sejarah Aceh harus ditulis ulang--bukan untuk membalas dendam pada masa lalu, tapi untuk membuka ruang pada masa depan.
Dan menulis ulang bukan berarti menghapus, tapi memilih dengan sadar.
Mana yang layak dikenang, mana yang harus diingat justru agar tak terulang.
Saya percaya masa depan Aceh tak akan ditentukan oleh elite, tetapi oleh mereka yang hari ini duduk di warkop sambil scroll TikTok dan bertanya dalam hati.
“Apa sebenarnya makna tanah ini?”
Jika tulisan ini bisa membuat satu orang muda masing-masing di Sigli, Kutacane dan Meulaboh, bangkit dan berkata, “Saya ingin menulis sejarah versi saya sendiri,” maka serial ini tak sia-sia.
Kita butuh sejarah yang bisa dibaca dengan air mata, tapi juga dengan marah.
Dan itu seringkali harus ditulis ulang.
Kita butuh sejarah yang tidak selesai di ruang seminar, tapi hidup di lagu Rafli Kande, syair Seudati, “dawa lam keude kupi”, ceramah dakwah yang kocak, dan di kampus progresif, tempat ide-ide belum mati.
Sejarah populer bukanlah milik ruang seminar tempat para “manusia langit” berkacamata tebal merumuskan teori sambil menyeruput kopi dingin karena terlupa.
Ia adalah cerita yang akan menyeberang dari kertas ke lidah, dan dari layar ke ladang dan pantai.
Kadang ia berlari cepat, kadang tenggelam sebentar ketika ekonomi gampong mati, lalu muncul kembali ketika panen padi telah selesai
Sejarah populer sejainya akan menjadi percakapan hangat di kedai kopi sore hari di Teupin Raya Pidie, terselip dalam tawa ceria perempuan pembelah pinang di Geuredong Pase Aceh Utara, dalam gumam para penangkap kepiting di Gosong Talaga menunggu pasang surut di hening Singkil.
Dan, ia akan hidup dalam sabetan parang dan nyanyian burung di kebun tebu Silih Nara, Gayo.
Saya tidak menulis karena saya tahu segalanya.
Saya menulis karena saya mulai bosan dengan kebisuan.
Karena sejarah yang dibiarkan diam terlalu lama akan jadi senjata bagi mereka yang ingin menghapus kita dari peta.
Maka, mari mulai.
Bukan dari awal.
Tapi dari titik di mana kita berhenti percaya bahwa masa lalu sudah selesai.
Sejarah Aceh, dalam serial ini, akan dituturkan bukan hanya dengan tinta yang tidak sangat ilmiah, tapi juga dengan gaya para pendongeng di meunasah, suara para perantau Pidie dulu yang mengarang hikayat dalam kerinduan, dan dramatisme yang kadang lebih dekat ke Bollywood daripada bibliografi.
Kita akan melompat dari hikayat klasik yang bisa ditulis ulang oleh Pramoedya, ke alur silat epik yang terasa seperti lempengan Kho Ping Hoo yang diterjemahkan ke dalam rencong dan rempah.
Karena sejarah, bila terlalu serius, akan kehilangan jiwanya.
Tulisan ini bukan akhir.
Ia adalah pintu.
Setiap pekan, kita buka satu jendela kecil ke rumah besar yang kita sebut sejarah Aceh--dan semoga dari sana, kita bisa melihat dunia, dan diri kita sendiri, dengan cara yang lebih jernih dan berani.
*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.
Artikel dalam rubrik Pojok Humam Hamid ini menjadi tanggung jawab penulis.
| Tambang Rakyat di Aceh: Potensi, Prospek, dan Tantangan |

|
|---|
| Proposal Trump, Otoritas Teknokratis, dan Prospek Damai Palestina |

|
|---|
| MSAKA21 - Kerajaan Lamuri: Maritim, Inklusif, dan Terbuka – Bagian XII |

|
|---|
| Kekonyolan Bobby dan “Hikayat Ketergantungan”: Yunnan, Bihar, Minas Gerais, dan Aceh |

|
|---|
| Ironi Palestina: Koalisi Keuangan Internasional dan Retak Internal Berkelanjutan |

|
|---|









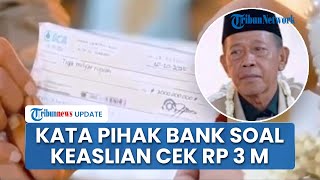





Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.