Kupi Beungoh
Pajak Sama Mulianya dengan Zakat: Tafsir Baru atau Distorsi Syariat?
Keduanya memiliki tujuan sosial yang sejalan, namun berdiri pada prinsip yang berbeda: zakat adalah kewajiban ilahi, pajak merupakan kewajiban sipil.
Oleh: Dr. Muhammad Nasir*)
DALAM perdebatan publik mengenai keadilan fiskal, muncul wacana yang menimbulkan kontroversi: pajak dianggap setara dengan zakat.
Bagi sebagian pihak, klaim ini terlihat progresif, bahkan visioner, sebagai upaya menyelaraskan kewajiban agama dengan kewajiban negara.
Namun, dari perspektif syariat, pertanyaan mendasar muncul: apakah pajak dapat disetarakan dengan zakat yang bersumber dari wahyu?
Ataukah pernyataan ini justru mengaburkan hakikat ibadah Islam yang paling fundamental?
Pertanyaan ini bukan semata akademis. Ia menyentuh inti hubungan antara agama, negara, dan masyarakat.
Pajak diperlukan untuk membiayai pembangunan, sedangkan zakat adalah ibadah transendental yang menata hati sekaligus struktur sosial.
Keduanya memiliki tujuan sosial yang sejalan, namun berdiri pada prinsip yang berbeda: zakat adalah kewajiban ilahi, pajak merupakan kewajiban sipil.
Baca juga: Tarif Pajak Jadi Sorotan, Kemenkeu Tegaskan tak Ada Perubahan Kebijakan PPN
Zakat: Ibadah Sakral dan Instrumen Keadilan Sosial
Zakat bukan sekadar pungutan harta, melainkan rukun Islam yang tata caranya diatur oleh wahyu.
Nisab, haul, dan delapan golongan penerima (asnaf) menjadi parameter yang jelas dalam Al-Qur’an.
Ia membersihkan harta, menenangkan jiwa, dan memperkuat ikatan vertikal antara manusia dan Tuhan, sekaligus membangun solidaritas horizontal antar sesama.
Ulama terkemuka, termasuk Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili, menegaskan bahwa zakat tidak dapat digantikan oleh instrumen buatan manusia.
Pajak bisa berfungsi tambahan bila zakat tidak mencukupi, tetapi tidak bisa meniadakan hakikat ibadah.
Zakat mengatur distribusi kekayaan, membatasi keserakahan, dan menumbuhkan empati, sekaligus membentuk moral sosial.
Pajak: Instrumen Fiskal Negara
Berbeda dengan zakat, pajak lahir dari kesepakatan hukum dan legitimasi negara.
Pajak dipungut untuk membiayai infrastruktur, gaji aparatur, layanan publik, dan subsidi sosial.
Ia bersifat duniawi, fleksibel, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan fiskal.
Pajak tidak mengenal nisab, haul, atau mustahik, melainkan diukur melalui proporsionalitas, efektivitas, dan keadilan distributif.
Dalam perspektif fikih, pajak termasuk maslahah mursalah, ditoleransi sejauh memberi manfaat nyata.
Kaidah klasik menyatakan: taṣarruf al-imām ‘ala ar-ra‘iyyah manūṭun bil-maṣlaḥah (kepemimpinan bergantung pada kemaslahatan rakyat).
Rasulullah SAW memperingatkan: “Tidak akan masuk surga pemungut al-maks (pungutan zalim).”
Pajak sah bila adil dan proporsional; pengklaiman sakralitas otomatis tanpa evaluasi etis adalah distorsi.
Sejarah menegaskan perbedaan ini.
Pada era Abbasiyah dan Utsmani, pendapatan negara bersumber dari pajak seperti kharaj dan jizyah, sementara zakat tetap eksis sebagai ibadah.
Di era modern, Arab Saudi memisahkan zakat dari pajak, sedangkan Malaysia mengintegrasikan keduanya melalui tax rebate, tanpa menyamakan status.
Realitas Kontemporer dan Kontroversi
Forum nasional terakhir menampilkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa zakat, wakaf, dan pajak memiliki tujuan sosial yang sama.
Meski berniat harmonisasi, klaim ini menimbulkan protes publik.
Majelis Ulama Indonesia menegaskan: zakat adalah kewajiban transendental umat Islam, bersumber dari wahyu, dan memiliki dimensi ibadah yang tidak dapat digantikan.
Pajak, sebaliknya, merupakan kewajiban sipil yang bersifat universal.
Data fiskal 2024 menunjukkan penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp1.932,4 triliun dengan rasio terhadap PDB 10,1 persen, sementara zakat yang dihimpun BAZNAS sepanjang 2023 hanya Rp33 triliun.
Angka ini menegaskan dua hal: pajak menjadi tulang punggung pembangunan, sementara zakat tetap memiliki posisi unik sebagai kewajiban spiritual.
Kegaduhan muncul ketika pajak dipaksakan dengan narasi sakral.
Di sejumlah daerah, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai ratusan persen, memicu protes besar.
Fenomena ini mengingatkan hadis Rasulullah SAW: pemungut al-maks, pungutan yang menyalahi keadilan, tidak akan mendapat ridha Tuhan.
Imam al-Mawardi menegaskan pungutan sah bila adil, proporsional, dan temporer, sedangkan Ibnu Khaldun menekankan pajak berat akan melemahkan produktivitas dan merugikan negara.
Baca juga: BAZNAS Pariaman Studi ke Aceh, Tertarik Sistem Zakat Masuk PAD
Sinergi Zakat dan Pajak: Strategi Fiskal dan Sosial
Zakat dan pajak memiliki tujuan sosial yang sama, keadilan dan kesejahteraan, meski berasal dari ranah berbeda: zakat dari wahyu, pajak dari hukum positif.
Jalan bijak bukan menyamakan, melainkan membangun sinergi strategis.
Indonesia sudah memiliki dasar hukum, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 dan UU Nomor 7 Tahun 2021, yang memungkinkan zakat mengurangi penghasilan kena pajak jika dibayarkan melalui lembaga resmi.
Namun, implementasinya terbatas.
Regulasi yang lebih spesifik dan aplikatif, misalnya zakat mengurangi jumlah pajak terutang secara langsung, akan mendorong kepatuhan berzakat sekaligus memperluas manfaat sosialnya.
Sinergi ini membawa multiplier effect: meningkatkan kepatuhan, memperluas penyaluran zakat produktif, mengurangi kemiskinan, dan membuka lapangan kerja.
Pajak tetap menopang pembangunan, sementara zakat menjadi katalis sosial yang nyata.
Aceh merupakan laboratorium ideal untuk pilot project ini, dengan dukungan masyarakat religius, regulasi lokal yang matang, dan pengalaman pengelolaan zakat yang sistematis.
Integrasi zakat dan pajak bukan sekadar insentif fiskal; ia merupakan inovasi moral, sosial, dan ekonomi.
Dengan kebijakan tegas dan terukur, fiskal negara diperkuat, ibadah dipertahankan kesuciannya, dan kesejahteraan umat dapat dicapai secara adil dan berkelanjutan.
Bahaya Distorsi Syariat
Menyetarakan zakat dengan pajak berpotensi mereduksi makna ibadah.
Zakat memiliki rukun, nisab, haul, dan asnaf; tidak dapat digunakan untuk semua tujuan.
Pajak fleksibel dan digunakan sesuai kebutuhan negara. Jika disamakan, sakralitas zakat akan larut menjadi “pungutan negara” tanpa dimensi spiritual.
Ibn Taimiyah hingga Yusuf al-Qaradawi menegaskan: pajak tidak menggantikan zakat.
Upaya tersebut bukan sekadar kekeliruan akademis, tetapi juga spiritual.
Jalan Tengah yang Arif
Zakat dan pajak tidak identik, tetapi dapat diarahkan untuk tujuan sama: keadilan sosial.
Zakat tetap sakral sebagai ibadah, pajak tetap instrumen negara.
Sinergi cerdas, misalnya insentif pajak bagi pembayar zakat resmi, memungkinkan keduanya mendukung kesejahteraan tanpa mengurangi makna wahyu.
Pemerintah dan masyarakat menghadapi tantangan strategis: menjaga fiskal negara kuat, keadilan sosial terwujud, dan kesucian ibadah tetap terjaga.
Pragmatism fiskal tidak boleh mengikis makna spiritual.
Zakat menyucikan jiwa dan harta, pajak menopang pembangunan, dan keduanya dapat bersinergi menuju keadilan sosial yang diridhai Tuhan dan dirasakan rakyat.
Wallahu’alam bissawab.
*) PENULIS adalah Dosen Magister Keuangan Islam Terapan, Politeknik Negeri Lhokseumawe. Pembina Yayasan Generasi Cahaya Peradaban. Penulis Buku Manajemen ZISWAF.
KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.
BACA TULISAN KUPI BEUNGOH LAINNYA DI SINI
perbedaan pajak dan zakat
pajak dan zakat adalah
pajak dan zakat dalam perspektif islam
kupi beungoh
Serambinews
Serambi Indonesia
| Refleksi Kemerdekaan dalam Menikmati Kemerdekaan |

|
|---|
| RAPBN 2026: Alokasi Ambisius, Harapan Besar, dan Tantangan Implementasi |

|
|---|
| Revitalisasi Nilai-Nilai Kemerdekaan Dalam 80 Tahun Kemerdekaan Indonesia |

|
|---|
| Aceh dan Kemerdekaan yang Masih Tertunda |
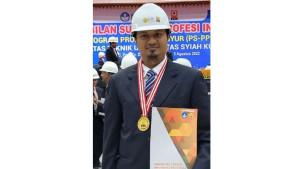
|
|---|
| Merdeka yang Tertunda: Dari Proklamasi ke Penjajahan Nafsu dan HIV/AIDS |

|
|---|









![[FULL] Meski Koordinator Aksi Damai & Demo Jilid II Batal, Pakar: Sulit Warga Maafkan Bupati Pati](https://img.youtube.com/vi/0qdqol4f7aU/mqdefault.jpg)



Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.