Kupi Beungoh
Birokrasi, Elit, dan Masa Depan Lingkungan Aceh
Beberapa bulan terakhir, perdebatan tentang penutupan tambang emas ilegal kembali mencuat di Aceh.
Oleh: Akhsanul Khalis
Beberapa bulan terakhir, perdebatan tentang penutupan tambang emas ilegal kembali mencuat di Aceh. Gubernur, Muzakir Manaf, menyampaikan keinginannya agar masyarakat kecil diberi ruang lebih besar dalam mengelola sumber daya lewat tambang rakyat.
Di telinga banyak orang, gagasan itu terdengar populis, seolah berpihak pada eco-social: keselamatan lingkungan dan rakyat kecil yang selama ini tersisih oleh pebisnis tambang.
Persoalan sesungguhnya justru terletak pada bagaimana birokrasi menerjemahkan gagasan itu dalam kebijakan konkret. Sejarah panjang birokrasi Indonesia memperlihatkan bahwa politik lingkungan hampir selalu kalah dari logika investasi.
Argumentasi ekologis sering dianggap hambatan pembangunan, sementara konsesi dan izin tambang menjadi ruang kompromi antara elit politik;birokrat dan pemodal.
Absennya paradigma ekologi
Berbicara teori birokrasi Weber, birokrasi dirancang sebagai organisasi yang rasional. Birokrasi di atas kertas memang identik dengan regulasi, prosedur, dan mekanisme kontrol. Tak heran, dalam praktiknya yang kemudian justru birokrat bekerja mengikuti sebagaimana logika politik dan akumulasi kapital, bukan logika pelayanan bagi kelas bawah.
Sejak awal penciptaanya bahwa birokrasi bukanlah entitas rasional yang netral, melainkan bagian dari superstruktur yang menopang kepentingan kelas dominan.
Dalam perspektif kiri, Marx menyebut birokrasi sebagai “ilusi universalitas.” kerja birokrasi seolah mewakili kepentingan umum, padahal sejatinya hanya memfasilitasi privatisasi agenda kelompok pemilik modal (borjuasi).
Konteks Aceh kontemporer, kelas dominan itu terdiri dari elit politik pasca konflik, birokrat senior, dan jejaring pengusaha yang kini membentuk (akumulasi lewat perampasan): privatisasi dan ekstraksi sumber daya alam.
Baca juga: Wanita di Malaysia Potong Anu Kekasihnya, Kesal Dengar Pengakuan Punya Istri di Bangladesh
Alhasil, birokrasi memainkan peran komprador: perantara kepentingan pemodal untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Regulasi yang semestinya melindungi publik justru menjadi alat distribusi rente.
Dampaknya besar. Walhi mencatat, Aceh kehilangan sekitar 23 ribu hektar hutan hujan tropis per tahun akibat tambang dan perkebunan skala besar. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan pertanda rapuhnya ekosistem yang mestinya menjadi penopang kehidupan jangka panjang.
Kasus kerusakan lingkungan di Geumpang, Pidie dan Beutong Ateuh Nagan Raya bisa jadi cermin. Sejak tambang emas ilegal beroperasi, aliran sungai mulai keruh, ikan-ikan hilang, sawah tak lagi panen maksimal. Masyarakat di hulu hanya menerima dampak kerusakan, sedangkan keuntungan besar mengalir ke luar.
Data juga menunjukkan sebagai catatan penting, hingga 2024 terdapat lebih puluhan jumlah IUP aktif, bahkan meningkat pada 2022. Kenaikan itu terjadi justru di masa Aceh dipimpin oleh pejabat gubernur, notabene dari kalangan birokrat yang mestinya netral.
Artinya, mekanisme izin berjalan tidak untuk menahan ekspansi tambang, melainkan memfasilitasi. Ini persoalan mendasar birokrasi Aceh, bukan hanya inefisiensi, melainkan juga absennya paradigma lingkungan.
Berdasarkan data itu, konteks wacana tambang rakyat yang kini digadang-gadang juga berpotensi jatuh ke pola lama: legitimasi populis yang berujung pada eksploitasi. Kemungkinan kedepan istilah tambang rakyat yang kini populer tidak sepenuhnya akan berwajah rakyat.
| Dibalik Kerudung Hijaunya Hutan Aceh: Krisis Deforestasi Dan Seruan Aksi Bersama |

|
|---|
| MQK Internasional: Kontestasi Kitab, Reproduksi Ulama, dan Jalan Peradaban Nusantara |

|
|---|
| Beasiswa dan Perusak Generasi Aceh |

|
|---|
| Menghadirkan “Efek Purbaya” pada Penanganan Stunting di Aceh |

|
|---|
| Aceh, Pemuda, dan Qanun yang Mati Muda |

|
|---|





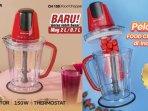








Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.