Kupi Beungoh
Romantisasi Kerja Tanpa Pamrih
Pertanyaannya, mungkinkah manusia bekerja tanpa pamrih dan tidak terasing? Mungkin saja jika relasi kerja dan keadilan sosial ditata ulang
Karl Marx, sosok filsuf yang membongkar logika kapitalisme, ia kemudian membaca ini secara berbeda. Dari beberapa literatur utama, kelangkaan yang disebut-sebut sebagai “hukum alam ekonomi” itu, hanyalah konstruksi agar nilai tukar menghasilkan nilai lebih bagi pemilik modal tetap tinggi dan roda kapital berputar.
Bagi Marx, kerja bukanlah barang netral. Kerja tak pernah berdiri di ruang hampa; selalu berkelindan dalam relasi produksi. Keberadaan upah tidak pernah benar-benar memperbaiki persoalan keadilan. Ketegangan kelas pekerja dan pemilik modal (kapitalis) akan terus terjadi. Inilah kemudian disebut metafisika materialisme historis, beranjak dari kenyataan sebagai antitesa idealisme spekulatif.
Baca juga: 10 Prompt Gemini AI Edit Foto Prewedding Berbagai Tema, Cocok Bagi Pasangan yang Budget Pas-pasan
Dimulai era itu, Marx membedakan istilah kerja antara: work dan labour. Work adalah ketika kita bekerja karena bebas dan kreatif, seperti menanam bunga, mengajar, menulis, atau mencipta sesuatu yang terasa terhubung dengan hasrat diri kita sendiri.
Sementara labour adalah kerja yang dijual, tenaga yang ditukar dengan upah, dan ini kelompok mayoritas di dunia. Di pabrik atau kantor, buruh menukar tenaganya untuk menutupi kebutuhan yang mendesak: dapur harus tetap berasap.
Karena pekerja tidak memiliki alat produksi atau modal; yang tersisa hanyalah tubuhnya dan pikiran sendiri untuk dijual ke pemilik modal, sehingga hidup pekerja ditentukan oleh jam kerja dan target produksi.
Marx menyebut keadaan ini sebagai keterasingan. Bayangkan seorang buruh di pabrik sepatu yang tak pernah mampu membeli sepasang sepatu hasil kerjanya sendiri. Ia hanya menjadi sekrup kecil dari mesin besar bernama produksi.
Hasil kerjanya tak lagi menjadi cermin dirinya, melainkan milik orang lain. Dari sanalah makna kerja kemanusiaan mulai terdistorsi.
Ini bisa kita rasakan sendiri, kian nyata dalam realitas sosial yang kapitalistik, banyak orang bekerja bukan untuk berkarya, tetapi karena tuntutan biaya hidup: sewa rumah, cicilan, dan harga kebutuhan yang terus naik.
Perlahan, pekerja kehilangan dirinya, tenggelam dalam rutinitas yang makin absurd. Budaya “kerja keras” acapkali digaungkan motivator justru itu normalisasi kesibukan tanpa makna, menjauhkan kita dari esensi kerja itu sendiri.
Baca juga: Gadis 12 Tahun di Banda Aceh Dinodai Pacar di Rumah, Modus Mau Makan Nasi & Berakhir Digerebek Warga
Mungkinkah kerja tanpa pamrih?
Pertanyaannya, mungkinkah manusia bekerja tanpa pamrih dan tidak terasing? Mungkin saja jika relasi kerja dan keadilan sosial ditata ulang walaupun di tengah gurita kapitalisme yang menempel hingga ke hal-hal paling sederhana dalam hidup, bahkan sekadar duduk memandang matahari tenggelam di pantai belakang rumah, wajib bayar.
Banyak hal kemudian diatur oleh uang. Pada akhirnya, ajakan “bekerja tanpa pamrih” menyisakan sikap sinis.
Dengan begitu perlu menyesuaikan teks dan konteks antara work sebagai ekspresi diri dan labour sebagai tenaga yang dijual. Terlalu sering, batas demarkasi antara keduanya sering dibuat kabur. Eksploitasi terjadi di wilayah terarsir (abu-abu) itu. Pekerja diminta ikhlas sementara hak-haknya ditunda.
Kultur kerja kerap dibingkai dengan pengabdian namun prakteknya tidak selalu bebas dari hirarkis dan relasi kuasa. Keputusan dan sumber daya tetap dikuasai segelintir orang.
Sehingga, kerja yang lahir dari ketulusan yang terlalu ideal patut juga dicurigai ketika tanpa dilandasi hak dasar yang pasti: upah layak, waktu istirahat yang cukup, dan rasa aman. Tanpa itu semua, romantisme “kerja ikhlas” hanya menjadi tirai untuk menutupi ketidakadilan.
Pada dasarnya kecenderungan filsafat Marxism, menganggap kerja adalah inti kemanusiaan. Di dalam setiap gerak tangan, beban pikiran dan tetesan keringat, ada kesadaran dan daya cipta yang membuat manusia berbeda dari makhluk lain.
| 3 Kuda Poni Kematian Finansial: Judi Online, Pinjol & Penipuan Menghancurkan Kelas Menengah Digital |

|
|---|
| Kisah Pilu Nelayan di Peukan Bada: Hidup di Gubuk Reot, Anak-anak Putus Sekolah |

|
|---|
| Rendah Mutu Dan Reputasi Kampus: Akibat Stagnasi Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi |
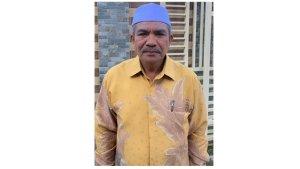
|
|---|
| Migas Aceh, Hantu di Bawah Tanah, Bayang-bayang di Atas Kemiskinan |

|
|---|
| Saat Perpustakaan Tak Lagi Jadi Tempat Favorit Anak Muda |

|
|---|









![[FULL] Pakar: Prabowo Tanggungjawab Whoosh Bukti Jadi Pelindung Jokowi, Fase Geng Solo Berantakan](https://img.youtube.com/vi/sFZRRPEHZQ4/mqdefault.jpg)





Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.