Kupi Beungoh
Mampukah Damai Aceh Menuju Kesejahteraan ?
Dua dekade damai telah lewat. Aceh menerima dana otonomi khusus, kewenangan diperluas, dan hak lebih besar atas hasil migas
Oleh: Akhsanul Khalis
Dua dekade damai telah lewat. Aceh menerima dana otonomi khusus, kewenangan diperluas, dan hak lebih besar atas hasil migas, Namun, janji kesejahteraan tak kunjung tiba.
Angka kemiskinan tetap tinggi, industri tak tumbuh, dan Aceh masih terperangkap dalam kutukan sumber daya.
Akhirnya, kita sampai terlalu percaya dengan kutukan itu. Seringkali kutukan sumber daya dilihat dengan kacamata kosmologis, dibandingkan hukum kausalitas (sebab akibat).
Padahal kutukan itu berulang di banyak tempat: Afrika, Asia, hingga Aceh. Kekayaan alam justru menjadi jebakan ketika institusi politik dan ekonomi dikuasai elite (extractive institutions) yang menutup ruang inovasi, seperti digambarkan Acemoglu dan Robinson dalam Why Nations Fail.
Pola itu kini kentara di Aceh: APBA habis untuk belanja rutin dan proyek mercusuar yang lebih memoles pencitraan ketimbang produktivitas, sementara elit politik sibuk mengamankan rente, bukan menyiapkan fondasi ekonomi yang bisa mengangkat rakyat keluar dari kemiskinan.
Baca juga: Pesona Wisata Aceh di Stan Disbudpar, Raih Predikat Terbaik di Expo Hari Damai
Objek eksploitasi
Melihat masalah ini hanya dari teori kelemahan institusi tidak cukup. Aceh adalah bagian dari ekonomi global yang bekerja dengan logika neo-imperialisme. Seperti dijelaskan Intan Suwandi dalam Value Chains: The New Economic Imperialism.
Nilai tambah terbesar dari sumber daya alam di negara berkembang justru dieksploitasi perusahaan di negara industri maju melalui mekanisme value capture.
Mereka mengendalikan harga, menetapkan standar produksi, dan mengatur kontrak pasok dari jarak jauh (indirect control), sambil menekan produksi dengan cost-price squeeze: harga ditekan serendah mungkin, sementara dampak lingkungan dibebankan pada daerah penghasil. Hasilnya, kekayaan lokal menguap sebelum sempat menjadi pembangunan nyata bagi masyarakat.
Sejarah pengelolaan SDA di Aceh juga menunjukkan pola relasi timpang. Pada masa Orde Baru, pengelolaan migas menganut sentralistik. Hak eksklusif bagi perusahaan besar dan pemerintah pusat.
Masyarakat lokal tersingkir, sementara keuntungan deras mengalir ke luar. Pasca-damai, kontrak jangka panjang yang diteken puluhan tahun lalu masih berlaku, sering kali tak bisa dinegosiasi ulang karena tekanan hukum internasional dan lemahnya kapasitas pemerintah daerah.
Model kontrak sektor ekstraktif pun memperparah ketimpangan. Royalti kecil, tenaga kerja lokal terbatas, dan teknologi tetap dimonopoli perusahaan luar.
Baca juga: Janji Damai Omong Kosong? Putin Sebut Ingin Damai, Tapi Malam Itu Juga Ukraina Dibombardir 270 Drone
Aceh hanya menjadi “penyedia lapak” lahan dan izin. Inilah indirect control: kendali harga, teknologi, dan pasar berada di luar Aceh. Surplus nilai keluar, sementara infrastruktur dan lapangan kerja berkualitas tak kunjung hadir.
Contoh nyata posisi hulu rantai nilai global. Gas alam Arun diekspor mentah selama puluhan tahun, menghasilkan produk petrokimia bernilai tinggi yang diproses di luar negeri, sementara di Aceh hanya tersisa PT PIM.
Batubara dari Aceh Barat dikirim dalam bentuk curah, sawit hanya diolah menjadi CPO, hasil laut dijual segar atau beku. Industri pengolahan modern nyaris absen.
| Wahai Umat Islam: Mari Saling Peduli Menjaga Generasi Dari Bahaya HIV/AIDS Karena Zina dan LGBT |

|
|---|
| Retak Harmonisasi Kampus: Lemah Kebijakan Manajemen Konflik Perguruan Tinggi |
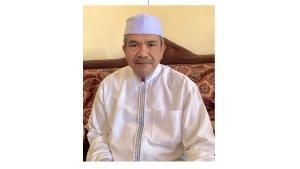
|
|---|
| Membaca Ulang “Semak Liar/Nipah”sebagai Masa Depan Ekonomi Hijau Aceh Barat |

|
|---|
| Gula Darah Melonjak, Tubuh Mengirim Sinyal Bahaya |

|
|---|
| Melupakan MoU Helsinki, Apa Tidak Salah Bung Benny K. Harman? |
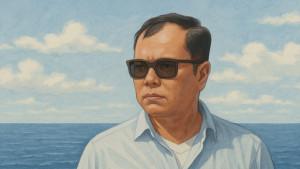
|
|---|














