Kupi Beungoh
Biaya Hidup Melonjak dan Krisis Pekerjaan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Filsafat Ilmu
Jika ditelusuri lebih jauh, krisis biaya hidup dan pekerjaan ini sesungguhnya mencerminkan krisis filsafat ilmu itu sendiri.
Oleh: Teuku Alvinnur, S.Pd.,
Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia hidup dalam ketegangan ekonomi yang semakin terasa nyata.
Kenaikan harga bahan pokok, keterbatasan lapangan kerja, dan ketidakpastian ekonomi menjadi topik utama di warung kopi, ruang keluarga, hingga sidang parlemen.
Fenomena ini bukan sekadar problem ekonomi ia merupakan potret krisis kemanusiaan dan krisis ilmu pengetahuan dalam memahami kesejahteraan manusia.
Kita sering mendengar istilah “pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat,” tetapi di sisi lain, masyarakat di lapisan bawah justru merasa hidupnya semakin berat. Maka, perlu refleksi yang lebih dalam: apakah ilmu ekonomi yang kita anut masih berpihak pada manusia, atau justru terjebak dalam logika pasar semata?
Melalui pendekatan filsafat ilmu, kita dapat menelusuri akar masalah ini secara lebih mendalam melihat hakikat realitasnya (ontologi), cara kita mengetahuinya (epistemologi), dan nilai yang seharusnya menuntun solusi (aksiologi).
Baca juga: 4 Amalan Sunnah Hari Jumat, Mudah Dikerjakan, Raih Pahala, Bisa Menghapus Dosa-dosa
Kajian Ontologis: Hakikat Krisis dan Realitas Manusia
Kajian ontologis berfokus pada pertanyaan: apa yang sebenarnya ada? Apa hakikat dari krisis ekonomi yang tengah melanda masyarakat Indonesia?
Secara ontologis, krisis biaya hidup dan sulitnya pekerjaan bukan hanya fenomena angka atau grafik ekonomi, melainkan fenomena kemanusiaan.
Di balik data inflasi dan statistik pengangguran, terdapat manusia-manusia nyata yang berjuang mempertahankan martabat hidupnya para ibu rumah tangga yang mengatur uang belanja yang tak cukup, para pemuda yang kehilangan semangat mencari kerja, dan para pekerja yang upahnya tak sebanding dengan harga beras yang terus naik.
Realitas seperti ini menegaskan bahwa ilmu ekonomi tidak boleh dipahami hanya sebagai sistem mekanis yang tunduk pada hukum pasar. Secara ontologis, ilmu ekonomi adalah ilmu tentang manusia dan kesejahteraannya, bukan sekadar tentang angka, modal, dan laba.
Sayangnya, paradigma pembangunan yang dominan di Indonesia cenderung positivistik dan materialistik. Manusia ditempatkan sebagai objek produksi, bukan subjek kehidupan. Orientasi pembangunan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, bukan dari pertumbuhan nilai dan kebahagiaan manusia.
Padahal, menurut pandangan filsafat ilmu, realitas sosial-ekonomi memiliki dimensi materi dan makna. Kenaikan harga beras bukan hanya peristiwa pasar, melainkan cerminan hilangnya keseimbangan antara sistem ekonomi dan moralitas publik.
Maka, memahami krisis ekonomi harus berangkat dari pemahaman bahwa realitas manusia bersifat multidimensional: ekonomi, sosial, etis, dan spiritual.
Dengan kata lain, ontologi kesejahteraan tidak bisa dilepaskan dari hakikat kemanusiaan itu sendiri.
Baca juga: Dari Soekarno ke Prabowo, Dubes Kanada Kenang Panjangnya Persahabatan Indonesia–Kanada di USK
Kajian Epistemologis: Krisis Pengetahuan dan Kebenaran Sosial
Dimensi epistemologi bertanya: bagaimana kita mengetahui bahwa krisis ini benar-benar terjadi? Apa sumber pengetahuan yang kita gunakan untuk memahami realitas sosial ini?
| Romantisasi Kerja Tanpa Pamrih |

|
|---|
| 3 Kuda Poni Kematian Finansial: Judi Online, Pinjol & Penipuan Menghancurkan Kelas Menengah Digital |

|
|---|
| Kisah Pilu Nelayan di Peukan Bada: Hidup di Gubuk Reot, Anak-anak Putus Sekolah |

|
|---|
| Rendah Mutu Dan Reputasi Kampus: Akibat Stagnasi Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi |
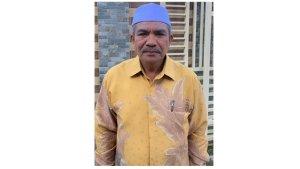
|
|---|
| Migas Aceh, Hantu di Bawah Tanah, Bayang-bayang di Atas Kemiskinan |

|
|---|









![[FULL] Roy Suryo Berlindung di Balik Penelitian, Pakar: Kalau Malah Menyerang Personal Tetap Pidana](https://img.youtube.com/vi/8fzdVBIhfxw/mqdefault.jpg)




Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.